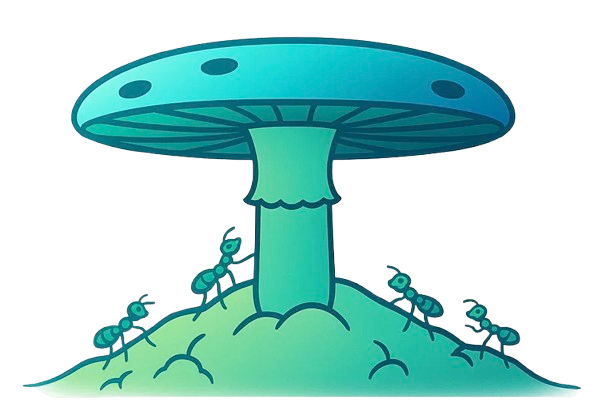Chapter 1: Kita
NISA (PoV)
Semilir angin kemarau menerpa wajahku ketika untuk pertama kalinya aku menginjakkan kakiku di sini, di kota kelahiran yang nyaris sepuluh tahun ini tak pernah kusambangi. Sebuah kerinduan menyeruak ke dalam hatiku ketika melihat lalu lalang mobil yang melintas di sebelah barat alun-alun kota ini.
“Bu, saya lapar. Kapan kita makan?” suara bocah sembilan tahun yang menggenggam erat tanganku ini membuatku terseret dari arus lamunanku.
Aku menunduk padanya dan menghadiahkan senyum terbaik yang selalu kuberikan padanya.
“Kita akan makan di bakso langganan ibu ketika sekolah dulu. Fariz mau?” tanyaku padanya.
Meski sejujurnya aku tahu jawabannya. Dia pasti akan menyukai tawaranku karena semenjak dia mengenal makanan setelah ASI, makanan yang paling disukainya adalah bakso. Membelinya setiap hari tak membuat dia jemu. Maka kali ini aku membawanya ke sini, di sebuah depot bakso dengan nama Goyang Lidah. Depot bakso kesukaanku ketika dulu masih sekolah.
Kugandeng tangan kecilnya menuju ke depot ini. Masih dengan tampilan yang sama ketika aku masuk ke dalam depot ini.
“Ngersakne nopo, Bu?” seorang anak remaja tanggung menyambutku dengan kesantunan yang menyejukkan telinga.
“Sebentar, Mas,” ucapku sambil melihat menu yang menempel di dinding depot ini. Aku menyimaknya dan memilih.
“Bakso kosong dua, teh es satu dan dawet gempol satu, ya?” Meski sedikit kurang pas, aku tetap memilih bakso dengan dawet gempol, dawet khas kotaku ini.
“Nggih, Bu. Sekedap, nggih?” Remaja tanggung itu kemudian keluar ke arah teras untuk meracik bakso.
“Apa Ibu dulu sering beli bakso di sini?” Fariz ikut mengedarkan pandangannya ke seisi depot sederhana ini, sepertiku yang melakukan hal yang sama. Menikmati nuansa nyaman dan sederhana depot bakso ini.
“Ya. Tetapi tidak sering.” Aku menatap mata polosnya yang berbinar.
Sungguh, mata bulat dengan hidung yang runcing ini benar-benar mengingatkan aku padanya, pada seseorang yang bahkan tak pernah kulupakan meski satu dasawarsa sudah berlalu. Waktu yang begitu cepat berlalu, ataukah mungkin karena aku tak tak bisa beranjak dari kenangan-kenangan tentangnya? Entahlah, bahkan aku sendiri tak tahu apa jawabannya.
“Mengapa, Bu? Bukankah Ibu menyukai bakso sepertiku juga?” tanya Fariz bertepatan dengan datangnya dua mangkuk bakso yang kami pesan tadi. Seorang pelayan yang lain menyuguhkan teh es dan dawet gempol.
“Makanlah dulu. Nanti Ibu cerita.” Aku menyodorkan es teh kesukaannya dan semangkuk bakso.
Fariz mengangguk dan mulai makan baksonya. Sementara aku, hanya mengaduk-aduk bakso yang kupesan. Sekilas kulihat Fariz sudah lapah dengan baksonya. Putraku ini memang doyan makan bakso. Maka tak heran jika dia terlihat sangat menikmatinya kali ini.
Namun, aku kehilangan selera makanku ketika ribuan bayangan berkelebat pesat, menggempur ingatanku. Bayangan seseorang yang membuatku tak bisa mencintai orang lain seperti aku mencintai dirinya. Tak bisa mengalihkan kehidupanku yang sekarang untuk tidak terikat dengan masa laluku bersamanya.
Tanpa kusadari, senyumku terukir masam. Mengasihani diriku sendiri yang tak juga menemukan penggantinya yang menghilang entah kemana, meninggalkan aku dalam kesunyian meskipun dunia demikian hiruk pikuk.
Di sini, di depot ini, aku pernah makan bakso bersamanya. Menikmati masa lalu sebagai remaja dengan demikian menyenangkan. Mencintainya dengan sepenuh hati, tak peduli apakah dia mencintaiku atau tidak. Ketika itu, aku hanya tahu bahwa mencintainya dengan tulus adalah ekspresi perasaanku.
“Apakah kamu tidak berniat mencarinya?” tanya Trio, teman remajaku ketika tahu bahwa aku hamil tanpa dia ketahui bahwa dia sudah memberiku benih cinta dalam kesalahan satu malam. Kesalahanku yang buta dalam mencintainya.
Aku yang ketika itu sebenarnya panik, hanya menggeleng.
“Kamu akan membesarkannya sendirian?” Trio menatapku tak percaya.
Aku yang kalut hanya mengangguk.
“Nis, membesarkan bayi sendirian bukan hal mudah. Kamu butuh uang untuk menghidupinya!” Trio marah ketika aku memutuskan untuk membesarkan bayiku sendirian, meski tanpa dia.
“Aku akan bekerja,” jawabku ketika itu. Meski saat itu aku tak tahu, pekerjaan macam apa yang bisa dilakukan oleh perempuan hamil sepertiku.
“Kamu pikir ada yang mau mempekerjakan perempuan hamil?” tanya Trio demikian pedas ketika itu.
Aku tak marah karena aku tahu, dia juga panik dengan keadaanku.
“Aku akan bekerja apa saja,” jawabku yakin. Sebenarnya sedang membohongi diriku sendiri karena aku sejujurnya juga tidak yakin.
Mengapa kamu tidak menggugurkannya saja?” Trio mengusulkan hal gila.
Aku menatapnya tajam. “Menggugurkannya? Kamu sudah gila?” Aku menghardiknya tajam.
“Karena dia akan menjadi beban hidupmu selamanya!” Trio balik menatapku tajam.
Aku menggeleng kuat, tak menyangka dia akan menyarankan hal bodoh seperti itu, Bagaimana mungkin aku menggugurkannya? Dia satu-satunya peninggalan yang kumiliki dari dirinya.
Tidak! Aku tidak akan melakukannya.
“Aku sudah melakukan sebuah dosa dengan tidur bersamanya. Aku tak akan menambah dosa besarku dengan membunuh bayi ini!” Kupegang erat perutku yang meski belum besar namun aku sudah begitu menyayanginya.
“Tapi dia akan lahir tanpa ayah, kau tahu? Kehidupan macam mana yang akan kamu suguhkan padanya? Bagaimana jika kelak dia menanyakan siapa ayahnya?” Pertanyaan Trio kembali menyudutkan posisiku.
Dan Trio benar. Meski pada akhirnya aku bisa bekerja atas kebaikan seorang pemilik kantor konsultan keuangan yang menerimaku bekerja sesuai kemampuanku, tapi nyatanya aku tak memiliki jawaban memuaskan ketika Fariz bertanya siapa ayahnya.
Hatiku bagai tersayat setiap kali dia bertanya siapa ayahnya. Apalagi ketika dia sering menangis ketika pulang sekolah karena diolok temannya. Yang kulakukan hanya memeluknya dengan hati perih penuh rasa bersalah. Semua rasa sakit yang dirasakan Fariz adalah karena kesalahanku.
“Nanti. Nanti kita akan menemui ayahmu,” janjiku pada akhirnya demi membuatnya berhenti menangis.
“Sungguh, Bu?” Fariz menghentikan tangisnya, menatapku dengan air mata berurai.
Tak sanggup melihatnya menangis, kujawab pertanyaannya dengan anggukan sambil kuusap pipinya.
“Ya. Ibu janji.” Dan aku tak bisa membendung tangisku ketika kupeluk dia erat. Kamu menangis berdua. Dan ketika liburan sekolah tiba, aku sengaja meminta cuti pada bos di kantor untuk menemaninya pulang ke kampung halaman. Tempat yang semula takut aku datangi, karena aku tak ingin memasuki masa laluku lagi.
“Ibu? Mengapa Ibu tidak makan baksonya?” Suara Fariz menyeretku kembali dari lamunanku.
Aku menatapnya dan tersenyum. Kulihat bakso di mangkuknya sudah habis.
“Fariz mau lagi?” tanyaku.
Bocah itu mengangguk dengan senyum malu.
“Mau makan punya Ibu?” tanyaku.
Bocah itu mengangguk, membuatku tersenyum. Lalu kuberikan bakso yang belum kumakan itu padanya. “Makanlah. Ibu masih kenyang.”
Dan selanjutnya, aku lebih menikmati melihat Fariz yang makan dengan lahap. Tak peduli dia sudah menghabiskan semangkuk bakso sebelumnya.
Lalu kudengar suara pembeli yang masuk ke depot ini.
“Bakso kosong satu sama ed dawet gempol satu, Pak.” Suara itu sepertinya pernah kudengar, tapi aku tak berani berspekulasi.
“Seleranya selalu seperti ini, Mas, bertahun-tahun?” tukang bakso menanyakannya.
“Hanya dengan cara seperti aku mengenangnya, Pak,” jawab si pembeli.
Aku mencoba mengabaikan percakapan mereka.
Tapi ketika pembeli itu duduk di kursi pandang yang ada di depanku, aku tak bisa lagi mengabaikannya. Tanpa sengaja, aku melihatnya. Menatap matanya. Dan dunia bagai berhenti berputar, bahkan detak jantungku rasanya berhenti berdetak selama beberapa saat ketika mata kami saling bersirobok pandang.
Aku menatap matanya. Dia menatap mataku. Lidahku kelu. Dia juga kehilangan kata-kata. Sementara jantungku yang kembali berdetak seketika bagai dihantam palu. Hingga suara Fariz mengejutkanku.
“Ibu? Mengapa Ibu memandang om ini seperti itu? Ibu mengenalnya?” tanya Fariz dengan polosnya.
Leherku rasanya kaku ketika aku menoleh untuk menatap Fariz. Haruskan kukatakan bahwa laki-laki di depan kami ini adalah ayah biologisnya?
***
PRAS (PoV)
Angin semilir menerpa wajahku ketika lidahku tiba-tiba ingin mengecap kembali rasa makanan khas kesukaanku. Tidak. Bukan kesukaanku sebenarnya. Aku menyukai bakso setelah aku merasa kehilangan seseorang yang kuanggap tak penting awalnya.
Namanya Nisa.
Tak cantik sebagaimana gadis muda umumnya. Hanya perempuan berkulit coklat yang sangat commoner, berpenampilan sederhana, dan mungkin juga sederhana kehidupannya. Karena yang pasti aku tak mengenalnya sedemikian detil. Dia begitu menyukai makanan bernama bakso, membuatku sedikit terbiasa dan berakhir dengan suka.
Pertemuanku dengannya juga tak terduga, bahkan tak pernah kuanggap istimewa. Perkenalan yang membuat kami menjadi dekat meski aku tak tahu dimana rumahnya, namun dia tahu siapa aku dan bahkan di mana rumahku. Aku tak tahu bahwa dia menyimpan sebuah cinta padaku, yang kuanggap konyol ketika itu. Karena aku juga tak tahu, apa yang membuatnya melabuhkan hati pada laki-laki tak punya masa depan seperti aku, ketika itu.
Bagaimana tidak konyol?
Kami sering bertemu meski tidak sengaja, di sekitaran alun-alun kota. Dan dalam setiap pertemuan itu, obrolan kami mengalir santai. Dia yang gadis lurus, tak peduli siapa dan bagaimana kehidupan berandalku. Namun, sepertinya dalam setiap pertemuan selalu tak cukup untuknya. Karena suratnya hampir setiap minggu suratnya datang ke rumahku.
“Surat lagi?” tanya ibuku ketika pak pos datang mengantar surat itu.
Aku hanya tersenyum masam mendengar komentar ibu.
“Dari siapa? Gadis yang sama?” Ibuku sepertinya mulai penasaran.
Dan lagi-lagi aku hanya tersenyum. Seharusnya Ibu tidak bertanya karena sudah tahu jawabannya. Aku langsung menuju ke kamar, membuka amplop panjang warna putih dengan alamat yang tertera jelas itu.
To : Agus Prasetyo, Jalan Kenanga.
Aku tersenyum melihat gaya gadis itu setiap mengirim surat. Penuh kreatifitas dengan diberinya gambar-gambar bunga di setiap sudut suratnya. Kertas sesederhana itu bisa menjadi demikian pantas dipandang, dan artistik.
Dan kalimat yang menghambur selalu berisi sebuah kalimat ketulusan. Bahwa dia mencintaiku tanpa syarat. Harusnya aku tertawa ketika seorang gadis bilang cinta tanpa syarat. Memangnya ada, cinta seperti itu? Atau ini hanya sebuah rayuan konyol karena dia kehabisan bahan pembicaraan?
Entahlah.
Yang pasti, aku menikmati pertemanan kami. Berjalan di sekitaran alun-alun membuat pertemanan kami begitu nyaman. Dan ya, aku bisa merasakan ketulusannya menyayangiku. Mengacak rambutnya yang sebagu sudah menjadi kebiasaanku jika bersamanya.
“Satu Muharam aku menunggumu di bawah patung singa. Kita habiskan malam dengan terjaga hingga pagi.” Aku memintanya bertemu untuk merayakan malam tahun baru.
“Sungguh? Jam berapa?” Matanya berbinar penuh semangat mendengar ajakanku.
“Jam tujuh malam. Kayak biasanya. Nanti yang datang duluan, nunggu,ya?” kataku menjanjikan pertemuan.
Dia mengangguk. “Awas kalau kamu ingkar janji!” ancamnya dengan wajah cemberut.
Aku tertawa melihat wajahnya yang lucu. Kuacak rambut di kepalanya dengan sayang.
Eh? Sayang? Benarkah?
Lalu ketika Malam Muharam itu tiba, aku sudah bersiap menemuinya di tempat yang kami janjikan. Aku bahkan sudah bersiap dengan mengenakan baju yang sedikit pantas untuk kencan. Bukan, sebenarnya bukan sebuah kencan karena dia bukan pacarku. Kami hanya teman yang sedikit mesra.
Aku bahkan sudah menunggunya satu jam sebelum waktu yang kujanjikan, tetapi seorang teman tiba-tiba datang. Namanya Ruri, teman satu kelompok yang sering nongkrong di sekitaran alun-alun ini.
“Gus, antar gw, dong?” ujarnya dengan wajah panik.
“Kemana?” tanyaku santai.
“Ke simpang tiga ujung. Abangku tawuran di sana, aku harus nolongin dia. Ayo, dong?” Rurimenyeret tanganku.
“Eh, Ruri! Tapi aku ada janji sama temenku.” Aku hendak menolak karena memang aku sedang nungguin Nisa kali ini.
“Nanti juga dia bakalan nungguin kamu. Tapi Abangku harus kuselamatkan. Ayo!” Ruri menyeret tanganku sehingga mau tak mau aku ikut dengannya.
Aku tak menyadari bahwa ternyata malam itu aku harus berurusan dengan yang berwajib karena ternyata abangnya Ruri yang tawuran itu tertangkap. Sialnya, polisi datang ketika aku baru saja tiba di lokasi tawuran sehingga mereka juga menangkapku.
Aku benar-benar sial malam itu.
Beberapa hari setelahnya aku menemuinya di barat alun-alun. Aku menemui Nisa yang waktu itu kebetulan sedang di sana. Aku mendatanginya untuk meminta maaf karena tak bisa menemuinya malam itu. Wajahnya cemberut dan aku merasa bersalah.
“Kamu marah?” tanyaku ketika kulihat wajahnya cemberut.
Awalnya dia membuang muka. Namun tak berapa lama dia menatapku dengan mata yang mula digenangi oleh air mata meski tidak sampai merembes. Aku tahu dia marah dan mungkin juga kesal. Tapi satu yang membuat rasa bersalahku semakin besar adalah ketika aku melihatnya menggeleng, sebagai jawaban bahwa dia tidak marah.
Ayolah, dia tidak marah tapi raut mukanya jelas menunjukkan kekecewaan. Kalau boleh memilih, aku lebih memilih dia menamparku sepuas hatinya. dari pada mendiamkan aku seperti ini. Sungguh, aku merasakan sakit yang tak terhingga hanya karena dia diam dan bersikap seolah it is fine. Sementara aku tahu itu tidak demikian.
Didera oleh rasa bersalah, aku menarik tangannya dan kubawa pergi ke rumah salah seorang teman yang kebetulan tinggal sendirian karena orang tuanya merantau ke Jakarta. Di tempat itu, kutuntaskan segala ganjalan yang ada di hatiku. Kukatakan yang sejujurnya mengenai malam itu hingga akhirnya matanya berbinar mengerti.
“Maaf kalau aku tadi marah,” katanya dengan lugu sambil menunduk.
Aku tersenyum. Entah mengapa aku tiba-tiba memeluknya, ingin meredakan segala rasa tak nyaman yang menerpa hatinya. Ingin memberinya rasa aman tak tak harus khawatir karena semuanya akan baik-baik saja. Lalu entah bagaimana awalnya, pelukan hangat itu tiba-tiba berubah menjadi tak terkendali ketika aku mengecupnya dengan lembut.
Dan entah setan mana yang kemudian berhasil membujukku sehingga begitu saja aku bergelung menurutkan hasratku bersamanya. Sempat kuucapkan maaf karena lupa diri, namun dia hanya mengangguk dengan air mata menetes. Aku memeluknya erat untuk memberinya penghiburan.
Aku tak menyadari bahwa itu pertemuan dan pelukan terakhirku padanya. Karena setelahnya peristiwa itu, aku kehilangan dia. Dia menghilang begitu saja bagai ditelan bumi. Aku juga tak tahu harus mencarinya kemana karena aku tak tahu alamatnya dimana.
Semenjak hari itu, aku mencarinya kesana kemari. Kucari tahu ke beberapa temannya, namun mereka tak tahu dimana keberadaan Nisa. Aku merindukan ketulusannya, merindukan surat-suratnya yang tak pernah lagi datang semenjak hari itu.
Dan hari ini, aku kembali berdiri di sini. Di sisi barat alun-alun sekedar mengingat dia yang dulu selalu kutemui di sini. Dan entah mengapa aku mencium aroma kuah bakso yang semakin menyeret langkahku untuk ke sana.
“Bakso kosong satu sama es dawet gempol satu, Pak.” Aku memesan menu yang dulu juga selalu dia pesan ketika ke sini.
“Seleranya selalu seperti ini, Mas, bertahun-tahun?” Aku tersenyum mendengar pertanyaan tukang bakso langganan ini.
“Hanya ini satu-satunya cara untuk mengenangnya, Pak.” Aku menjawab dengan nada kering yang terdengar menyakitkan, bahkan di telingaku sendiri.
Aku lalu masuk ke dalam untuk duduk. Kulihat seorang perempuan bersama seorang anak laki-laki sedang makan di sana. Lalu entah mengapa aku mengambil tempat duduk di kursi panjang yang ada di depan perempuan itu, padahal di sisi yang lain banyak kursi yang kosong.
Tanpa pikir panjang, aku duduk. Namun detak jantungku seakan menggelepar lebih cepat ketika aku tanpa sengaja melihat matanya yang juga melihatku. Kami merasakan keterkejutan yang nyata dan bagai terbungkam tak bisa berkata-kata. Mulutku terkunci, mulutnya juga sama. Hingga pertanyaan si bocah membuatku ikut menatap anak lelaki tampan itu.
“Ibu? Mengapa Ibu memandang om ini seperti itu? Ibu mengenalnya?”
Deg!
Aku menatap anak lelaki itu. Dan demi Tuhan, aku bagai melihat diriku ketika masih ana-anak. Aku seperti bercermin.
Apakah dia ….
***
Daftar Chapter
Chapter 1: Kita
2,319 kata
Komentar Chapter (0)
Login untuk memberikan komentar
LoginBelum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan komentar!