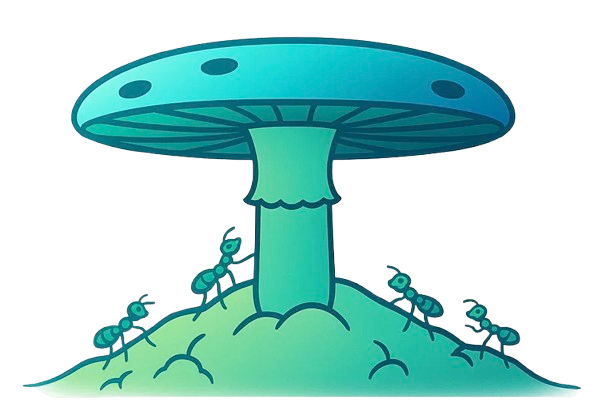Chapter 5: Rahasia yang Tak Pernah Dibagi
Malam berlabuh perlahan di Jeonsa, menyisakan nyala lampu jalan yang menguning pucat di sela-sela bayang tembok dan pohon kering. Dari balik jendela kamarnya yang terbuka separuh, Jongdae menatap langit yang tampak rendah, seolah bisa disentuh bila ia mengulurkan tangannya. Hening, hanya suara jarum jam yang pelan berdetak dari dinding dan embusan kipas angin yang berputar malas.
Ia tak bisa tidur. Bukan karena kopi sachet yang tadi ia minum bersama Areum di ruang makan kecil milik keluarganya, tapi karena isi kepalanya terlalu gaduh. Wajah-wajah orang yang ia temui hari ini berkelebat di balik kelopak matanya yang lelah: Honyun yang gemetar di hadapan pria-pria bertubuh kekar, Areum yang menangis sambil meremas ujung bajunya, Kinam yang tertawa tak tahu apa-apa, dan Seowon… yang bahkan tak lagi menoleh padanya.
Jongdae menghela napas pelan. Ia memejamkan mata, berharap semua bayangan itu menguap, tapi justru semakin nyata. Tumpang tindih. Berisik. Menguras isi dadanya seperti saringan yang bocor. Ia membalikkan tubuh di kasur tipisnya dan menatap langit-langit kamar. Suara nafas Areum dari ruang sebelah terdengar lembut. Gadis itu tidur di atas futon kecil yang biasanya dipakai Naari jika menginap. Jongdae bersyukur Naari sedang pergi ke rumah tantenya di Namyangju. Kalau tidak, ia pasti tak akan tahu harus menempatkan Areum di mana malam ini.
Apa yang harus ia lakukan?
Apa yang bisa ia bantu?
Pertanyaan-pertanyaan itu berputar seperti roda yang kehilangan arah. Ia merasa seperti sedang menonton film yang tak tahu kapan akan berakhir, dan yang paling aneh, ia adalah salah satu tokoh utamanya. Jongdae menelungkupkan tangan di atas perutnya dan menatap kosong ke luar jendela. Sejak kapan semuanya jadi serumit ini? Dulu, hidupnya cuma berisi dua hal—belajar dan bekerja. Kini, semuanya bercabang. Ada nama-nama yang mulai tinggal di dalam hatinya dan tak pernah benar-benar pergi: Areum, Seowon, Jo Anna, Kinam, bahkan Jaewoo dan Honyun.
Dunia remaja bernama Geum Jongdae pelan-pelan berubah menjadi dunia yang harus memeluk terlalu banyak rahasia.
Pagi datang seperti kabut yang mengambang tenang di antara sela tirai tipis apartemen kecil milik keluarga Geum. Jam dinding berdetak pelan menuju pukul sembilan, sementara sinar matahari menerobos masuk dari celah jendela, menyorot lantai kayu yang mengilat karena baru dipel. Aroma sabun pel dan sup miso tipis mengambang perlahan di udara.
Ruang tengah apartemen itu tak besar, tapi hangat. Sebuah karpet rajut warna krem pucat terbentang di antara meja kayu rendah dan sofa tua berwarna biru kelam. Di dinding tergantung kalender bertema panen musim gugur, sedikit miring. Di sudut ruangan berdiri rak buku kecil yang menampung beberapa komik, novel tipis, dan satu dua foto keluarga. Tak ada yang istimewa, tapi setiap benda di sana punya nyawa, seperti diam-diam menyaksikan semua yang terjadi dalam rumah itu tanpa bisa berkata-kata.
Jongdae menuang sup ke dalam dua mangkuk, lalu membawa sepiring telur dadar ke meja. Ia menyodorkan sebotol susu pisang yang baru ia keluarkan dari kulkas—hadiah diam-diam dari Seowon yang ia simpan di rak khusus, tak pernah disentuh sampai hari ini.
Areum duduk bersila di karpet, mengenakan hoodie besar milik Naari dan celana training kebesaran yang digulung di mata kaki. Rambutnya dikuncir asal, matanya masih bengkak tapi lebih hidup dibanding semalam. Ia menatap susu pisang itu sejenak sebelum akhirnya tersenyum tipis.
“Tidur nyenyak?” tanya Jongdae sembari duduk di seberangnya.
Areum mengangguk kecil. “Cukup… nyaman.”
“Aku harus kabari ibumu?”
Areum menggeleng. “Aku sudah bilang padanya, aku enggak akan pulang dulu. Beberapa hari mungkin.”
Kalimat itu membuat Jongdae diam. Ia menunduk, menatap ujung sumpit di tangannya. Suara kipas angin menggantikan jeda percakapan. Di dalam dirinya, sebuah perasaan samar muncul, seperti kabut yang menyelimuti tubuh tanpa terasa—campuran antara khawatir, kasihan, dan kekosongan yang tak punya nama.
Ia tak tahu seperti apa rasanya takut pulang ke rumah. Ia bahkan tidak tahu bagaimana bentuk seorang ayah. Tapi saat melihat Areum berkata seperti itu, seolah ia sedang melihat sebuah bunga liar yang diinjak berkali-kali tapi tetap berusaha mekar di tengah beton.
Perutnya terasa kosong meski ia sudah menyuap satu sendok nasi.
Areum menarik napas, lalu bicara pelan, “Aku benci dia. Ayahku. Aku benci banget. Tapi yang paling menyakitkan itu bukan karena dia jahat… tapi karena ibuku enggak bisa—atau enggak mau—melawan. Aku kasihan sama dia, tapi aku juga muak. Aku… enggak bisa nyelametin siapa-siapa. Bahkan diriku sendiri.”
Jongdae menoleh pelan, memandangi wajah Areum yang tertunduk. Ia ingin berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja, tapi ia tak mau berbohong. Ia tahu tidak ada yang bisa menjamin itu. Jadi ia memilih keheningan sejenak, lalu menatap ke arah jendela.
“Kau sudah cukup hebat, Areum. Bertahan di rumah seperti itu, tetap datang kerja, tetap bisa tersenyum sedikit waktu Jaewoo hampir lempar spatula ke Honyun…” Nada suaranya lembut, tapi penuh lapisan rasa.
Areum menoleh, matanya sedikit berkaca-kaca sebelum terangkat pelan. “Kalau bukan karena Jaewoo dan sumpahnya yang absurd itu, mungkin aku nggak akan bisa ketawa malam tadi.”
Jongdae menyengir. “Aku masih gak percaya dia bisa bilang ‘kalau Honyun reinkarnasi manusia, berarti aku semut’. Itu kalimat paling filosofis yang pernah aku denger dari dapur restoran ayam goreng.”
Mereka tertawa. Ringan. Pelan. Tapi tawa itu nyata—bukan basa-basi atau bentuk kasihan—melainkan semacam pelampiasan dari kelelahan yang menumpuk. Di luar, angin pagi menggerakkan tirai tipis, membawa udara segar dan aroma gang Jeonsa yang belum ramai. Dunia belum berubah, tapi pagi ini terasa sedikit lebih mudah dijalani.
Keduanya berjalan menyusuri trotoar yang masih sepi, diteduhi langit biru pucat dengan awan tipis yang digiring angin pelan seperti kapas hanyut. Udara pagi ini bersih dan ringan; tidak terlalu dingin, tidak juga gerah—cukup hangat untuk membuka jaket sedikit, cukup teduh untuk tetap betah berjalan.
Langkah kaki mereka berdampingan. Areum sesekali menatap ke atas, memperhatikan burung-burung kecil yang beterbangan dari kabel ke kabel. Jongdae membawa tas selempangnya dengan satu tangan dan tangan satunya dimasukkan ke dalam saku jaket. Jalanan Jeonsa mulai hidup perlahan: kios sayur membuka terpal, suara pelajar dari halte ujung gang, dan aroma kimbap dari warung kecil mulai memenuhi udara.
“Aku rindu suara Jaewoo marah-marah,” gumam Areum pelan, membuat Jongdae tersenyum samar.
“Dan spatulanya yang bisa jadi senjata pemusnah massal,” timpal Jongdae.
Areum tertawa pendek. “Tapi... semalam, waktu kita dengar suara Honyun di gang sempit itu... kamu sempat mikir sesuatu nggak, tentang dia?”
Jongdae menoleh, ekspresinya sedikit berubah.
“Aku rasa... dia sedang dalam masalah besar. Orang-orang yang mendatanginya, mereka bukan sekadar kolektor utang biasa. Mungkin keluarganya punya beban yang dia pendam sendiri. Mungkin dia—nggak tahu caranya minta tolong.”
Areum mengangguk pelan. “Ayahku pernah didatangi orang-orang seperti itu juga... Aku hafal suara mereka, cara mereka bicara. Dingin, penuh tekanan, kayak mencabik dari dalam kepala. Waktu itu cuma Ibu yang keluar hadapi mereka. Ayahku malah kabur ke tempat judi. Dan kami—aku dan adikku—harus pura-pura nggak dengar apa-apa dari kamar.”
Jongdae tidak langsung menjawab. Matanya menatap jauh ke depan, ke arah stasiun trem yang mulai terlihat. Ia bisa mendengar suara deru roda besi yang merayap dari kejauhan, membelah pagi yang semula tenang.
“Aku cuma bisa nebak-nebak soal Honyun,” katanya akhirnya. “Tapi kalau aku benar... dia pasti sedang menggenggam sesuatu yang terlalu berat, dan tidak tahu bagaimana cara meletakkannya.”
Areum tidak menyahut, hanya menghela napas pelan.
“Kamu sendiri, hari ini mau ke mana?” tanya Jongdae sambil mempercepat langkah.
Areum menggigit bibirnya sebentar. “Menjemput adikku... Dia kabur ke rumah salah satu kerabatku. Semalam... ayahku mukul dia.”
Langkah Jongdae berhenti sesaat. Ia menatap Areum, yang tetap berjalan pelan di depannya, seolah kalimat barusan terlalu biasa untuk diberi jeda.
“Aku... maaf, Areum. Aku nggak tahu harus bilang apa.”
Areum menoleh sedikit. “Kamu udah bantu aku. Kalau bukan karena kamu kemarin... mungkin aku udah nggak di sini.”
Mereka berjalan lebih pelan sekarang, menyusuri zebra cross yang mulai ramai. Seorang pria tua menyapu di depan toko baju, anak kecil berlarian mengejar gelembung sabun dari mesin kecil, dan seorang ibu membawa dua kantong belanjaan sambil berbicara di telepon.
Jongdae tidak langsung merespon. Ia membiarkan Areum berjalan di sisinya, sementara pikirannya seperti daun yang hanyut di sungai yang tenang namun dalam.
Berapa banyak orang yang berjalan seperti ini setiap hari, berpura-pura baik-baik saja padahal jiwanya sudah tercabik berkali-kali? pikirnya. Berapa banyak yang bertahan hanya agar tak mati di tangan sendiri?
Akhirnya ia berkata, “Kalau ada apa-apa... kabari aku ya. Aku akan datang kapan pun kamu butuh. Sebagai teman.”
Areum berhenti di ujung stasiun. Ia menatap Jongdae, mata itu tampak lebih jernih dari hari kemarin—tidak karena sembuh, tapi karena seseorang menolongnya menyalakan cahaya kecil.
“Jongdae,” katanya lembut, “kamu bukan cuma teman. Kamu itu rumah... yang nggak pernah aku punya.” Kata-kata itu jatuh seperti embun di ujung daun. Jongdae tak langsung menjawab. Tapi sorot matanya berubah—lebih hangat, lebih tenang.
Trem datang. Areum melangkah naik dan berdiri di balik kaca. Jongdae melambaikan tangan kecil dan Areum membalasnya sambil tersenyum samar.
Hari itu, langit tetap biru. Dan Jongdae percaya, mungkin segalanya bisa pelan-pelan membaik.
Trem melaju di atas jalurnya yang dingin, seperti waktu yang tak pernah menoleh ke belakang. Jongdae berdiri dekat jendela, matanya menatap keluar pada bayang-bayang Seoul yang terus menggeliat dalam kerutinannya. Kota ini, pikirnya, selalu terjaga. Bahkan saat seseorang kehilangan segalanya, jalanan tetap ramai, toko-toko tetap buka, dan kereta tetap berjalan seperti tidak pernah ada luka yang tertinggal di jantung siapa pun. Gedung-gedung menjulang seperti benteng perasaan yang tak bisa diganggu, dan langit—meski terang—terasa terlalu jauh untuk dijangkau oleh manusia yang memikul beban masing-masing di punggungnya.
Jongdae menarik napas panjang. Dalam dadanya, suara Areum masih terpantul: kalimat-kalimat lirih yang penuh rasa bersalah dan kelelahan. Dan lebih dari itu, rasa takutnya. Ketakutan seorang anak yang melihat orangtuanya bukan sebagai pelindung, tapi sebagai sosok yang harus dihindari. Ia tahu rasa itu. Ia mengenal sunyi yang membuat seseorang lebih nyaman di luar rumah dibanding dalam pelukannya sendiri.
Ia mengingat susu pisang dari Seowon di atas meja kecil ruang tengah apartemennya. Ia mengingat tawa pelan Areum, tatapan tajamnya pada Honyun, Jaewoo yang selalu meludah dengan penuh niat, spatula yang sempat hampir melayang, hingga suara pria-pria berbadan kekar yang mengintimidasi seperti bayangan dari mimpi buruk masa kecil. Semuanya menyatu dalam benaknya seperti lembar-lembar buku yang tak selesai ditulis. Jongdae merasa seperti sedang hidup di dalam fragmen-fragmen milik orang lain, ikut bernafas di ruang sempit yang bukan miliknya, tetapi tetap saja ia tak bisa pergi. Ia bukan pahlawan, bukan penyelamat siapa-siapa—ia hanya seseorang yang terlalu terbiasa menunda kesedihan untuk memberi ruang bagi luka orang lain.
Ketika ia turun dari trem, suara jalanan kembali riuh. Klakson, percakapan cepat para pengantar makanan, aroma kopi dari kafe kecil yang baru buka. Semua kembali bergerak seperti biasa. Tapi Jongdae tahu, ada yang berubah di dalam dirinya. Ia berjalan ke arah restoran Kinam, melewati jalan kecil yang dihiasi tiang listrik berkarat dan poster konser yang mulai luntur. Di kejauhan, papan nama restoran yang mulai memudar tampak menggantung lesu, tapi tetap berdiri.
Ia menatapnya sejenak sebelum membuka pintu.
Kadang dunia tidak memberi kita pilihan untuk hidup dengan mudah, pikir Jongdae. Tapi jika hari ini masih bisa dijalani... maka mungkin itu cukup untuk disebut kuat.
Restoran itu belum sepenuhnya buka saat Jongdae tiba. Udara pagi masih mengandung sisa embun, walau matahari telah mulai menyengat aspal dan genting-genting tua. Ia membuka pintu geser yang agak macet di ujung bawahnya—sudah berkali-kali disarankan diganti oleh Kinam, tapi ayahnya hanya bilang, “Kalau belum benar-benar jebol, jangan diganti. Itu artinya masih kuat.” Kalimat yang seolah berlaku untuk semuanya di rumah itu—pintu, wajan, bahkan anak-anaknya.
Begitu masuk, aroma kuah kaldu menyambutnya seperti pelukan hangat yang familiar. Jongdae meletakkan tasnya di balik rak sendal dapur dan mengganti sepatu. Langkahnya terdengar pelan, tapi mantap. Ada sesuatu yang menenangkan dari suara sendok yang berbenturan, dentingan panci, dan suara gemericik keran yang dibiarkan terbuka oleh seseorang yang pasti sedang ceroboh.
“Pagi, Jongdae!” suara Kinam menyambut ceria dari balik pintu dapur yang setengah terbuka. “Kamu bawa angin pagi dari arah mana tuh? Bau kamu kayak... eh, sabun hotel ya?”
“Sabun rumah,” balas Jongdae tenang, meletakkan celemek yang sudah kusut di gantungan dinding. “Areum masih di rumah, aku yang masak sarapan tadi.”
Kinam mendekat, mencium sedikit leher Jongdae lalu mengerutkan hidung, “Hmm, ya bener sih. Sabun rumah yang disponsori diskon cuci gudang.”
Jongdae menghela napas, tapi matanya tertawa. Kinam memang seperti itu. Melempar komentar seenaknya dengan wajah penuh percaya diri. Tapi hari itu, bahkan candaan murahan terasa menyenangkan. Seolah dunia tidak seberat malam kemarin.
“Ayah lagi di pasar?” tanya Jongdae.
“Lagi debat soal harga tauge sama ahjumma penjual daging. Dua-duanya sama keras kepala. Kayaknya sih dia bakal pulang dengan luka batin.”
Langkah kaki menyusul dari arah dapur. Salah satu staff laki-laki yang bernama Seungho masuk terburu-buru, membawa dus telur dengan kedua tangan. Tapi tak sengaja karung tepung yang disandarkan di dinding terpeleset dan membuat Seungho tersandung.
“YA! Tolong! Telurku dalam bahaya ini!” teriak Seungho dramatis sambil berusaha menyelamatkan isi dus seperti menyelamatkan bayi burung dari bencana alam.
Jongdae sigap menyambut, menahan dus telur sebelum jatuh. Kinam ikut terkekeh.
“Aku rasa telur-telur itu lebih punya masa depan daripada hubungan percintaan Seungho,” ucap Kinam sambil menyendok potongan daun bawang dengan gaya anggun seperti chef selebriti.
Seungho berdiri, menatap Kinam dengan kekecewaan mendalam. “Kamu tahu nggak? Luka dari kata-kata itu lebih dalam daripada goresan pisau dapur.”
“Pisau dapur nggak pernah nyakitin kamu karena kamu nggak pernah cukup rajin buat motong apa-apa,” sela salah satu staff perempuan bernama Mira dari arah meja potong.
Tawa meletus di ruang dapur. Jongdae mengaduk sup dalam panci sambil tersenyum kecil. Di tengah segala kegetiran yang ia simpan sendiri, kehidupan tetap menawarkan tawa. Bahkan jika itu berasal dari celetukan absurd dan wajah-wajah yang ia lihat setiap hari. Dapur sempit itu terasa seperti panggung kecil yang penuh absurditas, tapi juga penuh ketulusan.
Ia tidak lupa malam kemarin. Tidak lupa suara Areum, tidak lupa sorot mata Honyun yang ketakutan, atau wajah-wajah pria bertubuh kekar yang bersembunyi di balik jas formal. Tapi pagi ini, Jongdae memilih untuk tertawa. Setidaknya untuk sekarang. Setidaknya untuk bisa memberi napas pada dada yang terlalu lama menahan beban. Karena mungkin hidup memang seperti dapur restoran—panas, ramai, sempit, dan tidak pernah benar-benar tenang. Tapi selama ada satu dua sendok tawa di antaranya, semua bisa dijalani.
Aroma kaldu yang mendidih menyusup ke dinding-dinding, bercampur dengan wangi harum dari irisan daun bawang, bawang putih goreng, dan wajan panas yang mendesis saat potongan daging menyentuh permukaannya. Jam masih menunjukkan pukul sebelas, tapi restoran Jeonghwa Ramen sudah dipadati pelanggan.
Setiap akhir pekan, restoran itu berubah menjadi ruang hidup yang riuh—tempat berkumpulnya para pekerja kantoran yang ingin bersantai, keluarga kecil yang mencari makan siang hangat, sampai pasangan muda yang tertawa pelan di pojok jendela, menyendok ramen dan sesekali saling menyeka mulut satu sama lain.
Jeonghwa Ramen berdiri di antara deretan pertokoan tua yang sudah diperbarui, menempati dua lantai bangunan dengan sentuhan kayu ek di setiap sudutnya. Pintu geser otomatis membuka setiap kali pelanggan masuk, mengalirkan udara dingin dari pendingin ruangan yang tersebar merata. Interiornya hangat dan lapang—meja-meja kayu dengan permukaan mengilap ditata rapi berjajar. Dindingnya dihiasi poster nostalgia bergaya retro dengan gambar mangkuk ramen besar dan ilustrasi Kinam kecil bersama ayahnya, tersenyum sambil memegang sumpit. Lampu-lampu gantung dari rotan menyebarkan cahaya kuning lembut yang memeluk ruangan seperti senja yang tidak pernah berakhir.
Musik lo-fi instrumental mengalun pelan di latar, hampir tenggelam oleh suara sumpit, tawa, dan ucapan waitress yang dengan lincah melayani pelanggan.
“Selamat siang! Mau dibantu, Kak?” suara salah satu waitress menyapa pasangan muda yang baru masuk dan masih terdiam memandangi papan menu digital di dekat pintu. Wajah mereka bingung, tetapi segera mencair saat salah satu petugas kasir—Haesun, gadis bermata sipit dan senyum manis—menjelaskan menu rekomendasi dengan gaya ceria yang menular.
Di dapur, Jongdae berdiri di garis api bersama lima staff lainnya—dua di antaranya adalah koki senior, sementara dua lagi adalah anak-anak magang yang masih tampak canggung menggenggam pisau. Jongdae bekerja cepat, menyusun topping, memeriksa mie yang baru diangkat dari rebusan, menyendok kuah, dan menaruh telur setengah matang yang kuningnya masih bergetar lembut.
“Siap meja tujuh! Tambah sambal satu, jangan salah letak lagi kayak tadi ya!” teriak Jongdae, tapi senyumnya tak hilang.
“Siap, senior!” jawab salah satu anak magang sambil tergopoh-gopoh mengambil mangkuk.
“Eh, eh, kamu mangkoknya masih ada uap panas tuh—liat, liat! Itu, tangan kamu mau saya bungkus rumput laut dulu biar nggak kebakar?” canda Seungho yang sibuk dengan bagian topping ayam pedas.
Mira, si tukang sayur potong, menyahut, “Tolong jangan korbanin rumput laut, kita lagi promo ‘nori gratis’ minggu ini.”
Tawa meledak kecil. Di antara kepulan uap dan tumpukan order, dapur Jeonghwa Ramen tetap menjadi ruang hidup yang ramai dengan celetukan dan tawa—seolah semua orang di dalamnya tahu bahwa hari akan berat, tapi mereka tidak harus menjalaninya dengan wajah tegang.
Kepala staff dapur, pria separuh baya bernama Gwangil, mengawasi dapur dari balik clipboardnya. Ia tenang, suara baritonnya jarang terdengar, tapi sekali berbicara, semua langsung diam. Ia lebih sering tersenyum sambil membantu menyusun urutan order.
“Kamu jaga tempo, Jongdae. Jangan terlalu kencang, nanti sore kamu tumbang,” ucapnya sambil menepuk bahu Jongdae singkat.
Jongdae hanya mengangguk, peluh sudah mengalir di pelipisnya, tapi semangatnya tidak surut.
Saat itu juga, pintu belakang dapur terbuka. Ayah Kinam masuk dengan gaya khasnya—topi tua miring di kepala, tas belanja berisi bahan segar di tangan, dan senyum yang langsung membuat semua kepala menoleh.
“Siapa yang bilang tadi kita kehabisan daun bawang? Nih, biar restoran kalian nggak gagal jadi legenda hari ini!”
“Bapak datang dengan aura penyelamat,” ucap Mira, menyambut dus itu sambil pura-pura sujud.
“Eh, jangan cuma sujud. Nanti kamu saya daftarin jadi menantu beneran,” sahut si bapak yang langsung disambut gelak tawa seisi dapur.
Restoran itu mungkin hanya tempat makan bagi banyak orang. Tapi bagi Jongdae, bagi Kinam, dan semua yang bekerja di balik dapur, Jeonghwa Ramen adalah pelabuhan. Tempat lelah ditambatkan. Tempat luka dibungkus tawa. Tempat hidup dibagi, bahkan lewat mangkuk-mangkuk panas yang tak pernah cukup lama di meja karena saking cepatnya mereka habis.
Tepat saat jarum jam di dinding dapur menunjuk pukul dua siang, suasana Jeonghwa Ramen mulai mereda. Kepulan uap dari kuah mendidih perlahan melembut, tak lagi riuh teriakan pesanan dari lantai atas. Beberapa crew dapur mulai bergerak ke ruang istirahat, menukar apron mereka dengan waktu sejenak untuk menghela napas.
Jongdae baru saja mencuci tangannya dan hendak mengisi botol air ketika matanya menangkap sosok itu—berdiri tenang di luar kaca pintu depan, tepat di balik sinar matahari yang menyaring lewat logo besar bertuliskan “Jeonghwa Ramen”.
Ryu Seowon.
Gadis itu datang dengan kaus putih tipis dan kardigan abu-abu yang membingkai tubuh kurusnya, ia tampak tak seharusnya berdiri di tempat sepadat ini. Hening, kontras dari seluruh keriuhan restoran yang masih menyisakan jejak.
Jongdae sontak mundur satu langkah. Udara di paru-parunya terasa terlalu penuh untuk dihela. Ia tidak masuk ke lantai depan, tidak membuka suara, tidak mengendap pelan seperti biasanya. Ia hanya menoleh cepat ke arah Kinam yang sedang memeriksa meja kasir.
"Hyung!" bisiknya pelan, cepat, "Di luar... ada orang yang harus kamu sambut."
Kinam yang mendongak kebingungan hanya menangguk dan segera melangkah keluar, menyambut Seowon dengan ramah, seperti tuan rumah menyambut tamu yang lama tidak datang.
Sementara itu, Jongdae memutar tubuhnya, meninggalkan suara-suara langkah di lantai depan, dan menyusup ke pintu belakang dapur.
Taman kecil di belakang restoran hanyalah sisa ruang antara bangunan, sekotak tanah mungil yang diisi batu kerikil dan dua pot tanaman tak terurus. Tangga beton kecil menuju pintu logistik menjadi tempat Jongdae duduk. Ia membuka botol susu pisang yang dinginnya mulai hilang, menatapnya sejenak seperti menatap pertanyaan yang tak punya jawaban.
Langit siang itu biru pucat dengan awan lepas seperti kapas. Tapi tak ada kedamaian dalam hati Jongdae. Ia mengangkat botol itu ke bibir, mencicipi rasa manis yang dikenalnya terlalu baik—rasa yang sering Seowon tinggalkan di dalam loker sekolah, atau di kantong jas hujan Jongdae setiap kali hujan turun tiba-tiba.
Dan entah kenapa, rasa itu kini terasa seperti beban.
Ada yang ganjil dari kehadiran Seowon. Sesuatu yang dulu terasa seperti rumah, kini menjelma seperti pintu yang hanya bisa dilihat dari luar, tak bisa lagi diketuk tanpa rasa asing. Setiap langkah Seowon membawa kenangan yang belum selesai, dan setiap tatapan diam itu membawa gugus rasa yang tak bisa Jongdae beri nama. Bukan marah, bukan rindu. Tapi kehilangan yang belum sempat diakui sepenuhnya.
Jongdae menggenggam botol susu pisang itu lebih erat. Ia tahu Seowon tak datang untuk membuat segalanya rumit. Tapi ketenangan yang sedang ia rawat, seperti benang tipis yang nyaris tak tampak, kembali bergoyang.
Seowon terlalu lembut untuk dibenci. Tapi kehadirannya juga terlalu dalam untuk diabaikan.
Dari balik celah pintu dapur yang tak sepenuhnya tertutup, suara Kinam yang ramah menyapa Seowon terdengar samar. Mereka berbicara tentang ramen, sekolah, tentang hal-hal ringan yang tak menyakitkan. Dan Jongdae memilih untuk tetap di sana—di tangga, di sela kerikil dan daun kering, mencoba mengatur napas sambil menunggu detak jantungnya kembali biasa.
Ia ingin hari itu berlalu cepat.
Ia ingin segalanya sederhana kembali.
Tapi mungkin, di hidup seperti ini, kesederhanaan bukan sesuatu yang bisa diminta.
Tak lama setelah suara pintu depan tertutup dan loncengnya berhenti bergoyang, Kinam masuk ke dapur dengan napas sedikit cepat. Ia melongok ke belakang—pintu logistik yang sedikit terbuka membuat cahaya siang menyelinap masuk, menggambar siluet Jongdae yang duduk menyendiri di anak tangga.
“Lho?” gumam Kinam sembari membuka pintu lebih lebar. “Ngapain kamu ngumpet di sini?”
Jongdae hanya menoleh sebentar, lalu kembali menunduk menatap botol susu pisang yang sudah dingin di tangannya.
“Panas di dalam,” jawabnya pendek.
Kinam mendekat, lalu ikut duduk dua anak tangga di atas Jongdae. Posisi mereka sejajar, tapi tidak saling menatap. Hanya diam yang mengendap sebentar, di antara suara spatula dari dapur dan cicit burung di atap seng belakang.
“Seowon cakep, ya,” kata Kinam tiba-tiba, dengan nada ringan. “Dia datang sendirian.”
Jongdae menelan ludah perlahan. “Iya.”
“Kamu baik-baik saja?”
“Hm,” gumam Jongdae. “Dikit.”
Kinam tertawa pendek. “'Dikit' kamu tuh biasanya setara sama ‘capek banget mau pergi ke Mars’.”
Jongdae tidak menanggapi. Matanya tetap jatuh pada botol di tangannya, menggulir nama yang diam-diam ia sembunyikan dari semua orang.
Ada sesuatu yang ganjil tiap kali Seowon hadir. Seolah ia datang bukan sebagai seseorang yang membawa jawaban, tapi sebagai pintu yang mengingatkan Jongdae bahwa pertanyaan-pertanyaan dalam dirinya belum selesai dijawab.
“Tumben kamu nggak nyamperin, dia ‘kan masih teman satu sekolah sama kita, anggota Student Council pula.” kata Kinam lagi, kali ini lebih pelan.
Jongdae menggoyangkan botol susu pisangnya pelan, lalu berkata dengan suara nyaris pelan seperti bisikan, “Aku cuma lagi nggak pengen ketemu siapa-siapa.”
Kinam mengangguk pelan, tidak menekan. Ia tahu betul saat Jongdae seperti ini: terlalu banyak yang dipikirkan, terlalu sedikit yang ingin dibagikan.
“Ya udah,” katanya sambil bangkit berdiri, “kalo kamu perlu diem, diem aja. Tapi jangan terlalu lama, ntar kamu keseret dramanya sendiri dan lupa caranya keluar.”
Jongdae menatap punggung Kinam sebentar. Ia tahu itu bukan kalimat bijak yang dikutip dari buku manapun—itu cuma Kinam, satu dari sedikit orang yang bisa membaca kesunyiannya dengan tenang, tanpa perlu tahu semua detailnya.
Saat pintu belakang menutup pelan, Jongdae mengembuskan napas panjang.
Seowon tadi datang cuma beberapa menit, tapi kenangannya terasa lebih lama dari waktu. Rasanya seperti membuka jendela hanya untuk mencium udara yang pernah tinggal di dalam kamar itu. Lalu menutupnya lagi, tanpa tahu kapan akan bisa bernapas normal.
Jongdae kembali ke dapur saat aroma rumput laut dan shoyu menyeruak lebih kuat dari sebelumnya. Seakan seluruh ruangan sedang mendidihkan tidak hanya kaldu, tapi juga waktu. Ia menyusuri lorong sempit antara rak bahan dan lemari pendingin, menyibak suara gelak tawa dan panggilan kerja yang masih hangat menyambut siang.
Salah satu staff dapur, Ahjussi Kwon, pria bertubuh besar dengan celetukan seperti stand-up comedian, menyapa dengan mulut masih mengunyah kimbap, “Wah, pangeran susu pisang kita akhirnya turun dari menara!”
“Lama-lama bukan pangeran, tapi jadi susu pisangnya sendiri,” sahut staff perempuan termuda, Nayoung, yang sedang sibuk mengiris narutomaki.
Tawa meletus. Jongdae hanya mengangkat tangan sebatas bahu, seolah mengatakan, iya, iya, aku dengar—tapi tak cukup kuat untuk menyangkal.
“Wah, hati-hati nanti kamu dibotolkan dan dijual bareng jajanan convenience store, Jong,” tambah Minseok, crew magang yang baru sebulan masuk tapi sudah akrab dengan kelakar dapur.
“Ya, asal jangan didiskon 1+1 terus kayak perasaanku akhir-akhir ini,” jawab Jongdae datar, membuat seluruh dapur bersorak, bahkan kepala staff yang biasanya serius pun terkekeh pelan.
Namun, di balik canda itu, masih ada sisa berat di ujung matanya. Ia menunduk sebentar, mengambil mangkuk besar dan mulai menakar mi untuk batch berikutnya. Tangannya otomatis bekerja, tetapi pikirannya terus berkeliaran seperti debu di cahaya matahari. Seowon duduk di dalam. Kenapa datang sekarang? Untuk apa susu pisang itu dibawa lagi, kalau rasanya seperti kenangan yang belum sembuh?
Kinam muncul dari balik tirai dapur dan menepuk bahunya. “Ayo, kita butuh kamu di station topping. Ada yang pesan ramen ekstra chashu. Dan aku tahu kamu satu-satunya yang potongannya bisa bikin pelanggan jatuh cinta.”
“Yah,” jawab Jongdae sambil mengambil talenan, “semoga yang jatuh cinta bukan chashunya sendiri.”
“Kalau itu bisa, kamu kita daftarin ikut acara TV. Ramen Enchanting Boy.” Kinam tertawa, lalu melenggang kembali ke service line.
Jongdae menghembuskan napas panjang, lalu fokus pada daging panggang di depannya. Setiap potongan ia susun rapi, setiap lapisan ia iris dengan presisi. Ia tahu tubuhnya masih bisa bekerja. Tapi hatinya... tidak. Hatinya tertinggal di botol susu pisang yang belum kosong.
Mungkin di dunia ini ada dua jenis kesibukan—yang membuatmu lupa, dan yang hanya membuatmu terlihat lupa padahal hatimu masih ingat segalanya.
Di luar, pelanggan masih berdatangan. Beberapa memotret interior restoran dengan kamera ponsel, terpukau oleh dinding kayu lapis bergaya modern-tradisional yang dihiasi poster ramen retro dan lampu gantung dari bambu. Musik jazz ringan mengalun dari speaker tersembunyi, menambah rasa nyaman di tengah keramaian. Meja kayu panjang berjajar, dengan pemisah kecil di antara kelompok, menciptakan nuansa hangat seperti rumah makan keluarga yang tak pernah kehilangan cerita.
Jeonghwa Ramen tetap hidup, tetap bergerak. Tapi Jongdae tahu, ada hal yang tidak bisa ia tuangkan ke dalam mangkuk. Hal-hal yang tidak bisa direbus, dikocok, atau dihias. Dan salah satunya baru saja duduk di restoran ini, diam-diam mengembalikan sesuatu yang dulu ia simpan—bukan hanya sebotol susu pisang, tapi juga sisa perasaan yang belum selesai mereka bicarakan.
Jongdae menunduk menatap botol susu pisang itu sejenak, lalu menghela napas panjang. Ia memiringkan kepalanya, menekankan sisi dahi ke lutut yang tertekuk, dan membiarkan ujung botol itu dingin menyentuh jari-jarinya. Manisnya susu itu tidak berubah, rasa yang ganjil—seperti sesuatu yang terlalu akrab namun asing dalam waktu yang sama.
Dari balik dinding dapur dan hiruk-pikuk restoran yang samar terdengar, Jongdae merasa seperti ditarik pelan-pelan ke masa lalu. Semua dimulai dari suara—suara Seowon tadi di dalam restoran. Lembut, jelas, tenang. Dan seperti gema di lorong kenangan, suara itu memanggilnya kembali ke halaman belakang gedung olahraga sekolah menengah pertama mereka.
Musim gugur minggu kedua. Daun-daun yang jatuh bukan sekadar simbol perubahan musim, tapi juga sesuatu yang mengawali kisah yang bahkan hingga kini tak pernah dimulai dengan benar.
Jongdae masih ingat bagaimana sore itu terasa terlalu tenang untuk seseorang yang hendak membuat pengakuan. Seowon berdiri dengan seragam Student Council-nya yang rapi, wajahnya pucat karena gugup, tapi matanya menyimpan nyala yang tak bisa Jongdae lupa. Mereka baru saja selesai rapat—divisi acara, tempat mereka paling sering bertemu dan bertukar ide.
Waktu itu Seowon sudah punya pacar. Semua orang tahu. Tapi entah mengapa, saat itu ia berdiri di hadapan Jongdae dengan tangan gemetar dan berkata tanpa berputar-putar:
“Aku tahu kamu ramah ke semua orang, tapi aku berharap kamu mau jadi seseorang yang lebih dari itu… untuk aku.”
Jongdae tidak menjawab seketika. Ia tak mengerti perasaan semacam itu. Dunia pacaran masih seperti bahasa asing yang belum ia pelajari. Tapi saat itu, melihat Seowon yang tidak menuntut, hanya menunggu dengan tenang dan jujur—ia berkata ya.
Mereka tidak pernah berpegangan tangan di koridor sekolah. Tidak pernah saling menyapa dengan nama panggilan. Seowon memintanya menjadi rahasia, dan Jongdae menurut. Bukan karena ia malu. Tapi karena saat itu, menyimpan sesuatu terasa lebih mudah daripada menjelaskannya. Dan Seowon... Seowon pun tidak pernah memberi alasan, selain satu kalimat yang Jongdae hafal di dalam kepalanya:
“Kita ini seperti kotak Pandora, Jongdae… yang kalau dibuka, bukan cuma rahasia yang keluar. Tapi semua yang nggak bisa kita kendalikan.”
Hari-hari berlalu, tahun pun berganti. Tapi kalimat itu menempel seperti debu di ujung rak hati Jongdae—tidak terlihat, tapi selalu ada.
Ia menyesap susu pisang itu pelan, lalu mengusap dahinya dengan lengan bajunya sendiri. Di dalam restoran, Seowon mungkin masih duduk, menunggu pesanannya diantar. Sementara Jongdae… tetap di anak tangga kecil ini, menatap langit Seoul yang berganti awan.
Ia ingin bertanya, sebenarnya hubungan itu masih hidup atau tidak. Tapi barangkali, seperti banyak hal dalam hidupnya, Jongdae sudah terlalu terbiasa membiarkan yang retak tetap menggantung tanpa diapa-apakan.
Ia hanya diam.
Karena sebagian dari dirinya masih anak kelas dua SMP yang tak tahu bagaimana mencintai, dan sisanya adalah remaja hampir dewasa yang terlalu mahir menyimpan.
Sore menjingga menyusup perlahan ke sela-sela kisi jendela dapur. Cahaya yang jatuh di lantai seperti lembutnya kelopak mawar yang gugur dari tangkai; sunyi, tapi tak bisa diabaikan. Jongdae kembali dari taman belakang, dengan botol susu pisang di tangannya—masih utuh, dinginnya mulai menghilang, tapi jejak kehadirannya tidak.
Kinam menghampirinya, menyeka tangannya dengan serbet. Ada gurat penasaran yang belum juga reda sejak siang.
“Ini...” Kinam menyodorkan botol kedua, suara rendah namun menahan keheranan. “Dari dia lagi.”
Jongdae menatap botol itu. Sama seperti sebelumnya, tidak ada catatan, tidak ada pesan, hanya diam yang dikirim dalam bentuk manis beraroma pisang. Ia mengulurkan tangan, menerimanya perlahan, seperti menyentuh kenangan yang belum siap dibuka.
“Dia tahu kamu di sini?” tanya Kinam akhirnya, kalimatnya nyaris setengah bisikan. “Padahal... kalian nggak pernah ngobrol, kan? Bahkan pas kita semua masih sekolah dulu... dia nggak pernah nyebut nama kamu.”
Ada jeda. Lalu Jongdae meletakkan botol itu di atas meja dapur yang mulai berembun oleh uap dari masakan sore.
“Kami kenal di SMP,” jawabnya lirih. “Waktu itu sama-sama di OSIS. Tapi... mungkin cuma aku yang mengingatnya.”
Ia tak menatap Kinam. Matanya justru jatuh pada titik kosong di dinding, seolah dari retakan kecil cat yang mengelupas, ia sedang mencari kunci untuk sebuah pintu lama—yang dulu pernah ia buka, diam-diam, sendirian.
Kinam tak menyela. Ia tahu ketika Jongdae berbicara begini, itu bukan undangan untuk berdiskusi. Itu semacam isyarat... bahwa di antara kata-katanya, ada cerita yang tak ingin ditemukan siapa pun.
“Aku cuma nggak nyangka,” gumam Kinam sambil menyandarkan tubuh ke meja. “Dia... perhatian banget, padahal kalian nggak kelihatan dekat. Bahkan nggak pernah satu lingkaran.”
Jongdae tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, lebih seperti refleks dari rasa lelah yang lama tertimbun.
“Kami memang nggak pernah kelihatan dekat.” Dan itu benar. Mereka adalah rahasia yang tidak pernah punya waktu untuk menjadi nyata. Mereka adalah cerita yang memilih bersembunyi, bahkan dari matahari.
Kinam mengangguk pelan, lalu berbalik tanpa bertanya lebih jauh. Tapi hatinya gelisah. Ia bukan tipe yang suka mencampuri, tapi Jongdae adalah satu-satunya orang yang ia pikir tak akan pernah menyembunyikan apapun. Hari ini membuktikan sebaliknya.
Sementara itu, Jongdae duduk di ujung bangku dapur. Di tangannya, dua botol susu pisang berdiri berdampingan. Seperti dua kalimat yang belum selesai. Dua kemungkinan yang tidak pernah dijelaskan. Ia memandangi botol itu dalam diam. Di benaknya, pertanyaan-pertanyaan kecil mulai tumbuh—diam-diam dan rapi seperti embun di jendela.
Kenapa Seowon masih mengiriminya ini?
Kenapa lewat Kinam?
Dan kenapa hatinya selalu bergetar dengan ganjil, setiap kali melihat warna kuning susu itu?
Hubungan mereka adalah benang yang tak pernah diikat, tapi tak juga dilepas. Ia tidak tahu di mana ujungnya. Ia bahkan tidak tahu kapan mereka mulai menenun simpul yang sekarang menggantung di dadanya.
Hari itu berlalu seperti biasa. Pelanggan mulai pulang, dapur kembali tenang. Tapi di dalam diri Jongdae dan Kinam, ada satu ruang yang tidak ikut sunyi. Kinam membawa pulang tanya yang ia tak berani ajukan dan Jongdae menyimpan jawab yang ia belum siap berikan—bahkan pada dirinya sendiri. Sementara malam Seoul kembali merangkak pelan, seperti biasa... menyimpan terlalu banyak hal yang tidak dikatakan siapa-siapa.
Malam turun perlahan di atas atap-atap kota, membawa aroma masakan rumah tangga dan suara televisi dari jendela yang terbuka. Jongdae baru saja membuka pintu apartemennya. Suara kecil dari engsel yang berderit seolah menyambutnya pulang seperti biasa, seperti tak ada yang berubah. Padahal, di dadanya, semuanya telah berubah begitu banyak.
Lampu ruang tengah menyala temaram. Naari duduk bersila di lantai, di depan meja kecil yang selalu dipenuhi tumpukan buku, pulpen warna-warni, dan cangkir susu yang belum habis. Rambutnya dikuncir asal, matanya masih terpaku pada buku catatannya, tapi saat mendengar suara pintu, ia menoleh dan tersenyum kecil.
“Kau pulang, Oppa.”
Jongdae mengangguk sambil meletakkan tasnya. “Sudah makan malam?”
“Sudah,” jawab Naari pelan. “Aku simpan bagianmu di rice cooker. Masih hangat.”
Tidak ada pelukan. Tidak ada sapaan berlebihan. Tapi dari suara Naari yang pelan dan ringan itu, Jongdae tahu ia sedang ditawarkan sesuatu yang lebih hangat dari sekadar nasi: tempat untuk merasa tenang.
Ia mengambil duduk di samping adiknya, membiarkan tubuhnya tenggelam sejenak dalam lantai dingin yang justru terasa menenangkan. Mereka tidak bicara selama beberapa menit. Hanya suara jarum jam dan kipas angin yang mengisi udara.
Naari sesekali melirik ke arah kakaknya. Ada sesuatu yang berbeda dari sorot mata Jongdae malam ini—bukan lelah karena bekerja, tapi lelah yang dalam dan rumit, seperti orang yang sedang menunggu jawaban dari dirinya sendiri.
“Apa hari ini sulit?” tanya Naari, akhirnya, lembut sekali. Ia tidak menanyakan hal-hal besar. Hanya membuka satu pintu kecil, agar Jongdae bisa masuk dengan tenang.
Jongdae menatap dinding, lalu melempar senyum yang nyaris tak terlihat. “Tidak tahu. Mungkin aku yang sedang terlalu... penuh.”
Naari tidak bertanya lebih lanjut. Ia hanya memindahkan sebotol susu pisang ke arah Jongdae. “Tadi aku beli dua. Kalau mau... yang ini untukmu.”
Jongdae menatap botol itu. Aneh sekali. Seharian ia dikelilingi botol yang sama—tapi baru kali ini, benda itu terasa netral, tidak menyimpan makna, tidak menyimpan kenangan. Hanya susu pisang biasa, dari seseorang yang tidak menuntut untuk dimengerti.
“Terima kasih, Naari.”
Naari mengangguk pelan, lalu kembali menatap catatannya. Tapi sebelum larut lagi dalam diam masing-masing, ia berkata pelan—seolah hanya ingin mengikat Jongdae pada kenyataan yang tidak menghakimi:
“Kau tahu, Oppa... waktu Seowon-sunbae sering datang ke rumah karena kerja kelompok dulu, aku sempat iri. Dia tenang sekali. Tapi sepertinya... dia juga menyimpan banyak hal.”
Jongdae menoleh. Suara Naari begitu pelan, hampir seperti gumaman. Ia tidak tahu harus membalas apa.
“Kalau kau ingin cerita, aku tidak tahu bisa bantu apa. Tapi... aku bisa duduk diam seperti ini. Kalau itu cukup.”
Dan bagi Jongdae, malam itu, itu memang lebih dari cukup.
Di dunia yang penuh kata-kata dan kebisingan, keheningan yang tidak menuntut bisa menjadi bentuk cinta yang paling lembut.
Malam merayap pelan ke sela-sela kamar Jongdae, membungkusnya dengan keheningan tipis seperti selimut yang tidak pernah benar-benar menghangatkan. Lampu kamarnya tidak dinyalakan malam ini. Ia duduk bersandar di pinggir ranjang, menatap jendela yang terbuka separuh, membiarkan angin masuk tanpa izin dan membelai gorden yang sudah mulai kusut.
Di dalam dadanya, sesuatu berisik. Bukan suara. Tapi sesuatu yang mendesak, mendidih, dan tidak tahu harus keluar dalam bentuk apa. Nama itu kembali datang: Seowon.
Jongdae tidak punya banyak kenangan dengan Seowon. Setidaknya tidak yang bisa ia kenang tanpa merasa tertusuk. Mereka adalah pasangan yang tidak pernah benar-benar menjadi pasangan. Tidak ada foto bersama, tidak ada panggilan manis, tidak ada tanggal jadi. Hanya ada janji samar di bawah pohon kering musim gugur, dan genggaman yang terasa lebih seperti permintaan maaf daripada cinta.
Mereka seperti dua orang yang berdiri dalam kabut, tahu bahwa yang satu ada di hadapan yang lain, tapi tak pernah benar-benar bisa melihat dengan jelas dan kini, setelah semua yang terjadi, Seowon hadir dengan cara yang ganjil: tidak datang, tapi selalu terasa. Tidak bicara, tapi meninggalkan pesan. Tidak menyentuh, tapi tetap membekas.
Jongdae menghela napas panjang. Lalu muncul bayangan lain: Jo Anna.
Ah, gadis itu. Gadis yang terang seperti pagi hari, yang tak pernah dijanjikan tapi selalu muncul dalam pikirannya. Kadang ia membencinya, karena kehadiran Jo Anna mengacaukan segalanya. Tapi lebih sering, Jongdae membenci dirinya sendiri, karena tidak bisa mengerti apa sebenarnya yang ia rasakan terhadap siapa pun.
Ia merasa seperti sedang menjalani transaksi. Hubungan tanpa bentuk, tanpa harga, tanpa nama. Ia menerima Seowon bukan karena cinta, tapi karena Seowon menawarkannya sesuatu yang tak bisa ia tolak. Sesuatu yang tidak berbentuk, tapi membelit. Seperti utang budi yang tidak pernah ia pahami dari mana mulainya dan sekarang, setiap kali Seowon muncul—lewat susu pisang, lewat Kinam, lewat sorot mata dari kejauhan—Jongdae merasa seperti sedang menagih kembali sesuatu yang tak pernah ia minta.
Ia menyandarkan kepala ke dinding. Matanya berat, pikirannya lebih berat. Tapi tidak ada kesimpulan malam ini. Tidak ada keputusan. Hanya kekosongan yang dingin, menyusup dari jendela yang terbuka.
Ia membiarkan angin masuk, membiarkan suara kota dari kejauhan bergema samar. Lalu perlahan, tanpa sadar, ia terlelap dalam gelap yang tidak menghukumnya, hanya membiarkannya diam.
Sampai pagi menemukan Jongdae dalam posisi yang sama, di kamar yang tetap dingin, dan hati yang tetap tidak mengerti apa-apa.
Daftar Chapter
Chapter 1: Prolog
173 kata
Chapter 2: Jeonsa – Pagi yang Setengah Di...
7,102 kata
Chapter 3: Di Bawah Langit Yang Terlalu B...
5,276 kata
Chapter 4: Langit Tak Pernah Menunggu
6,005 kata
Chapter 5: Rahasia yang Tak Pernah Dibagi
6,094 kata
Chapter 6: Seutas Benang yang Tak Pernah...
7,734 kata
Chapter 7: Rasa yang Tak Bernama
8,481 kata
Chapter 8: Dalbit dan Jam Pulang Sekolah
11,467 kata
Komentar Chapter (0)
Login untuk memberikan komentar
LoginBelum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan komentar!