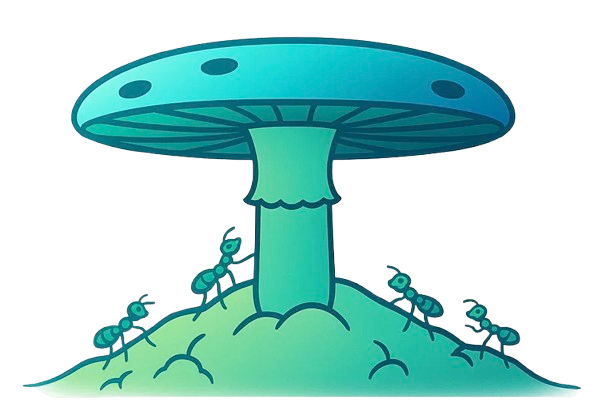Chapter 4: Langit Tak Pernah Menunggu
Ada hari-hari di mana langkah terasa lebih berat dari biasanya, meskipun jalan yang dilalui tetap sama. Jongdae tahu betul rasanya.
Pagi itu, tubuhnya bergerak seperti biasa—mengenakan seragam, memasukkan kotak makan ke dalam tas, menyapa Eomma dengan senyum kecil yang tetap hangat. Tapi ada sesuatu yang mengendap di balik matanya. Seperti lelah yang tak sempat istirahat, seperti sedih yang tak tahu caranya keluar.
Kelas 11-4 riuh oleh suara kursi ditarik dan percakapan tanpa jeda, tapi di tengah semua itu, Jongdae duduk tenang dengan mata menerawang, jari-jarinya memainkan ujung pulpen tanpa arah. Seakan tubuhnya hadir, tapi jiwanya tertinggal di tempat lain—di malam-malam yang tak pernah cukup tidur, di pikiran yang sibuk menenangkan semua orang tapi lupa merangkul dirinya sendiri.
Ia mendengar suara-suara di sekelilingnya, tapi tak satu pun menempel di benaknya. Kepalanya terasa penuh, namun kosong. Ada napas yang terus dihela dalam-dalam, tapi tidak juga meredakan sesak.
Di bangku seberangnya, Kinam memperhatikan dalam diam.
Bocah itu tak berkata apa-apa, tapi matanya menahan sesuatu. Ia tak bodoh, dan sudah cukup lama jadi sahabat Jongdae untuk tahu: Jongdae tidak sedang baik-baik saja.
Hanya saja, Jongdae pandai menyamarkan luka seperti menutup jendela yang retak dengan tirai tipis—cukup bagi dunia untuk mengira semuanya utuh.
Kinam menunduk pelan, mencoret sesuatu di pojok bukunya. Bukan catatan pelajaran, hanya satu baris:
"Kalau kamu capek, bilang."
Tapi ia tidak menyodorkannya. Tidak hari ini. Belum.
Lorong sekolah siang itu masih ramai, tapi waktu seolah melambat ketika mata Jongdae menangkap siluet yang begitu ia kenal.
Seowon.
Langkah gadis itu tenang, seperti biasa, tapi bagi Jongdae, itu cukup untuk membuat dunianya terhenti sejenak. Tak ada kata yang meluncur. Hanya sepasang tatapan yang saling tersangkut, kaku dan canggung—seolah keduanya sedang berdiri di antara dua dunia yang tak lagi bisa menyatu.
Jongdae menahan napas. Ada jeda tipis di dadanya, seperti debur halus yang menyakitkan.
“Jongdae!”
Suara Kinam memecah ketegangan, menyentaknya ke permukaan. Sahabatnya menunjuk ke arah lain, ke arah Jo Anna yang tengah berbelok di ujung lorong seberang. Hanya bahunya yang tampak, cepat sekali menghilang dari pandangan. Tapi Jongdae tidak bergerak. Tatapannya masih terpaku pada Seowon.
Gadis itu berjalan ke arah mereka. Rambutnya tergerai rapi, membingkai wajah yang tak berubah.
Masih lembut. Masih dingin.
Jongdae menatapnya dengan diam yang terlalu dalam—mencoba mengukir setiap garis wajah, mencoba mengingat bagaimana rasanya ketika jarak tak sejauh ini.
Seowon berhenti di depan mereka, membuka mulut pelan. Jongdae kira, ia akan dipanggil, diajak bicara, atau sekadar disentuh dengan suara yang dulu begitu Jongdae rindukan.
Tapi tidak.
“Ini titipan buku dari Bu Oh. Untuk Sejarah.”
Seowon menyodorkannya pada Kinam, suaranya hangat dan ramah.
Biasa.
Begitu biasa, hingga dada Jongdae terasa dicekam dingin yang asing.
“Terima kasih, Seowon.” Kinam membalas, mengerutkan kening sesaat saat melirik Jongdae yang masih tak bersuara.
Dalam hati, Jongdae nyaris berkata: Kenapa bukan aku? Kenapa bukan mataku yang kau tuju?
Tapi tidak ada yang ia ucapkan.
Seowon menoleh sejenak, menatapnya singkat—mata itu tetap indah, namun seperti berlapis kabut. Ada jarak yang jelas dan disengaja, seolah mereka tak pernah saling mengenal lebih dari orang-orang yang kebetulan lewat dalam hidup masing-masing.
Dan Jongdae hanya berdiri di sana. Beku.
“Yuk.”
Kinam menepuk lengannya pelan. Jongdae menoleh, langkahnya berat seperti baru saja meninggalkan sesuatu yang tidak bisa diambil kembali. Mereka pamit, dan Seowon hanya mengangguk kecil.
Dalam langkah menuju kelas, Jongdae tak banyak bicara. Tapi hatinya berisik.
Menyusun tanya yang tak ingin ia jawab—tentang cinta yang samar, pertemuan yang terasa seperti perpisahan, dan luka yang datang dari hal-hal tak diucapkan.
Langkah kaki Jongdae menapaki koridor sekolah seperti melintasi lorong kenangan yang tak lagi utuh. Kinam berjalan di sisinya, tenang seperti biasa, tetapi Jongdae merasa jauh. Ada sesuatu yang patah perlahan di dalam dirinya, retak yang tak berbunyi, namun cukup untuk membuat dadanya terasa sempit.
Ia menunduk, memandangi sepatu sekolahnya yang sedikit berdebu, seolah di sana tertulis jawaban atas kegelisahan yang baru saja mengendap. Ia mengingat mata Seowon—yang tidak menyapanya. Ia mengingat suara lembutnya—yang hanya ditujukan pada Kinam. Ia mengingat kehadirannya—yang terasa seperti absennya sesuatu yang dulu sangat berarti.
"Apakah selama ini aku yang terlalu banyak berharap?"
Pertanyaan itu menggantung seperti kabut tipis yang tak bisa dihalau. Ia menggali memori mereka—pertemuan singkat di pojok sekolah, pesan-pesan yang tidak selalu sempat dibalas, janji bertemu yang sering tertunda karena waktu yang tak pernah berpihak. Mereka tidak pernah benar-benar punya cukup ruang untuk tumbuh. Cinta itu ada, iya, tapi seperti tanaman dalam pot kecil yang tak pernah diberi matahari—menguning pelan, lalu diam-diam layu.
Jongdae menghela napas.
Di balik senyap yang ia peluk, hatinya menyesap pahit.
Hubungan ini... apakah hanya bertahan karena diam-diam ingin dipercaya? Atau karena mereka terlalu sibuk menjaga kesepian masing-masing, hingga lupa bahwa cinta butuh diperjuangkan dari dua sisi?
Ia tidak marah. Tidak kecewa juga.
Hanya... lelah.
Lelah menjadi satu-satunya orang yang mencoba mengisi ruang yang tak pernah diminta untuk diisi. Lelah merasa harus kuat setiap waktu, sementara hatinya perlahan kehilangan bentuk. Ada bagian dari dirinya yang ingin menyerah—bukan pada Seowon, tapi pada bayangan yang ia simpan tentang Seowon. Bayangan yang begitu ia jaga, padahal mungkin kenyataannya tak lagi sama.
Mungkin Seowon sudah berjalan lebih jauh dari yang ia tahu.
Atau mungkin... Seowon hanya tidak pernah benar-benar berada di tempat yang sama dengannya dan anehnya, dari semua itu, yang paling menyakitkan adalah betapa Jongdae tidak bisa menyalahkan siapa-siapa.
Ia menatap langit yang mulai memutih di ujung jendela lorong, seolah meminta petunjuk. Tapi langit pun diam. Seperti Seowon. Seperti dirinya sendiri.
Dengan senyum kecil yang hanya tersirat di sudut bibirnya, Kinam menoleh. Ia tidak langsung bicara—tidak ingin menerobos keheningan Jongdae yang terasa seperti dinding kaca: transparan, tetapi rapuh. Ia memperhatikan, mempelajari gurat lesu di wajah sahabatnya. Gerak langkah Jongdae yang biasanya teguh, kini terdengar lebih lambat, seperti terseret oleh beban yang tidak terlihat.
“Capek, ya?” tanya Kinam akhirnya, ringan, seolah hanya sekadar basa-basi. Tapi sorot matanya menelisik, mencari jawaban di sela napas Jongdae yang tak seirama.
Jongdae tersenyum sekilas. Tipis sekali, seperti hujan yang jatuh tanpa suara.
“Sedikit.”
Kinam tidak menanggapi dengan kata-kata. Ia hanya mengangguk, lalu berjalan lebih lambat, menyesuaikan irama langkah mereka. Ia tahu, Jongdae bukan tipe yang langsung membuka luka. Biasanya perlu waktu, perlu tenang yang tidak menghakimi.
Dan saat itu, Kinam memilih menjadi tenang itu.
Langkah mereka kembali menyusuri lorong, sunyi. Tapi Kinam merasakannya—ada sesuatu yang bergolak dalam diri Jongdae, seperti gelas yang penuh dan tinggal menetes. Mungkin bukan karena hari ini saja. Mungkin ini sisa dari hari-hari sebelumnya yang tidak sempat diceritakan.
Dan kini, semua sisa itu menumpuk jadi diam.
“Kalau nanti kamu butuh tempat buat diem, tapi enggak sendirian,” ucap Kinam, tanpa menoleh, “aku ada, ya.”
Suaranya lembut, tidak dramatis. Tidak pula menuntut penjelasan. Hanya kehadiran yang tidak meminta syarat.
Jongdae menoleh padanya—hanya sejenak. Lalu kembali menunduk. Tapi ia mengangguk. Tak berkata apa-apa, tapi di balik anggukan itu ada rasa terima kasih yang tidak sempat diucapkan dan Kinam mengerti. Ia tak butuh penjelasan lebih. Kadang, menjadi teman terbaik bukan tentang tahu semuanya, tapi tentang tetap tinggal, bahkan saat tak ada apapun yang bisa dikatakan.
Langit jam tiga sore menggantung rendah di atas Jeonsa, menyisakan sinar yang menyusup di antara dedaunan yang bergerak pelan tertiup angin. Suasana sekolah mulai lengang. Di gerbang, hanya tersisa bayang-bayang para siswa yang melangkah pulang dalam kelompok kecil, atau sendiri-sendiri seperti Jongdae.
Ia baru saja berpisah dari Kinam saat matanya menangkap sosok yang sangat ia kenali. Jo Anna.
Gadis itu berjalan sendiri, sesekali menunduk untuk mengecek layar ponselnya, lalu tersenyum kecil pada sesuatu yang tak terdengar oleh dunia luar. Ada cahaya yang berpendar di wajahnya—entah karena sinar sore atau semata karena ia sedang bahagia. Tapi saat Jongdae menyamakan langkah dan menyapanya dengan pelan, ekspresi itu mengendap pelan. Tak menghilang, hanya berganti rupa menjadi kikuk yang membeku di antara mereka.
“Hai, Jo Anna,” sapa Jongdae, suaranya rendah tapi terdengar cukup jelas.
Jo Anna menoleh dengan sedikit terkejut, lalu mengangguk pelan. “Hai,” balasnya.
Langkah mereka jadi seiring. Jalanan kecil di luar pagar sekolah masih dipenuhi siswa yang pulang, tawa dan percakapan menyusup seperti angin lalu. Tapi di antara mereka berdua, udara terasa berbeda—lebih padat, lebih sunyi. Seperti dua orang asing yang sedang belajar menjadi akrab.
“Mau ke mana?” tanya Jongdae, berusaha terdengar biasa.
Jo Anna mengangkat sedikit tasnya. “Mau beli hadiah. Teman sekelasku ulang tahun minggu ini. Aku belum sempat cari apa-apa kemarin.”
“Oh, begitu…” Jongdae tersenyum kecil. Ia tidak tahu harus merespons apa selain itu. Tapi ia senang. Bahkan jika hanya sebagai pendengar, ia merasa cukup.
Ia memperhatikan Jo Anna saat gadis itu bercerita—tentang bingungnya memilih hadiah yang cocok, tentang toko kecil yang baru buka di dekat halte. Suaranya ringan, matanya sesekali berkilat saat menyebutkan hal-hal kecil yang membuatnya antusias dan di saat-saat itu, Jongdae merasa seperti sedang menghafal langit—indah, jauh, dan mustahil dimiliki.
Ada jeda.
Hening yang tidak memaksa, tapi menggantung.
Jo Anna melirik ke arah Jongdae, lalu memberanikan diri bertanya, “Kalau kamu? Mau ke mana?”
Jongdae mengusap belakang lehernya, lalu menatap ke depan. “Ke Chenchun Dak,” katanya ringan. “Kerja paruh waktu, seperti biasa.”
Jo Anna tidak langsung menjawab. Ia menunduk sedikit, mengangguk sekali. Tapi diamnya terasa menekan, dan Jongdae menyadarinya.
“Kenapa?” tanyanya, mencoba tersenyum. “Kau diam saja.”
Jo Anna menggigit bibir bawahnya, lalu menggeleng. “Bukan apa-apa.”
Namun Jongdae tahu… bukan berarti tidak ada apa-apa.
Dalam benaknya, muncul lagi bayangan tentang mereka berdua—ia dan Jo Anna—berjalan berdampingan di jalanan yang sama, tapi mungkin dengan pijakan berbeda. Ia tidak pintar, tidak populer, dan tidak punya apa-apa selain keberanian untuk terus berjalan.
Ia selalu bertanya dalam hati, seperti hari itu:
Apakah Jo Anna pernah menganggapnya cukup? Atau ia hanya seperti pejalan kaki yang tak sengaja menyamakan langkah dengan seseorang yang berjalan menuju arah lain?
Langit berubah warna perlahan, dan bayangan mereka menjalar panjang di aspal. Tapi waktu terasa diam, seolah memberi ruang bagi dua hati yang sama-sama mencari tahu—tentang jarak yang tidak bisa diukur dengan meter, tapi dengan keberanian dan luka yang tak diucapkan.
Langkah mereka masih seirama, menyusuri trotoar yang perlahan ditinggalkan sisa-sisa pulang sekolah. Cahaya matahari mulai condong ke barat, membias lembut pada wajah Jo Anna yang separuh tertutup bayangan rambutnya yang tergerai. Jongdae mencuri pandang. Ia tidak bisa tidak mengakui bahwa ada sesuatu dari sosok gadis itu yang selalu membuat hatinya melambat. Seperti ingin berhenti sejenak di dunia yang terus bergerak.
Jo Anna tampak memeluk tasnya lebih erat, jarak di antara mereka hanya satu langkah, tapi rasanya tetap berjeda.
“Eh… kamu kerja tiap hari?” tanyanya pelan, menoleh sekilas tanpa benar-benar berani menatap mata Jongdae.
Pertanyaan itu sederhana, tapi nada suaranya mengandung sesuatu yang membuat dada Jongdae sedikit menghangat.
“Iya,” jawabnya, santai. “Tiap sore. Kadang malam juga. Tergantung giliran.”
Jo Anna mengangguk kecil. Ia menunduk, lalu menghembus napas pelan. Gerakan tangannya yang merapikan anak rambut di pelipis seperti upaya menyembunyikan kegelisahan kecil yang muncul entah dari mana.
“Pasti capek, ya…”
Jongdae hanya tersenyum. “Ya… lumayan. Tapi sudah biasa.”
Mereka tiba di perempatan. Di sisi kanan, jalan menuju halte dan toko yang Jo Anna maksud. Sementara lurus ke depan, adalah jalur Jongdae menuju Chenchun Dak.
Mereka melambat, seperti tidak ingin waktu menggiring mereka ke arah berbeda.
“Terima kasih ya… udah nemenin jalan,” ucap Jo Anna sambil menoleh. Senyumnya muncul ragu, tapi tetap hangat.
Jongdae mengangguk. “Sama-sama. Hati-hati, ya.”
Jo Anna hendak melangkah, tapi menoleh sekali lagi, suaranya nyaris seperti bisikan, “Jongdae…”
Jongdae menoleh, sedikit terkejut dipanggil namanya dengan begitu lembut.
“Aku… semoga kerjanya nggak terlalu berat hari ini.”
Ia lalu tersenyum, manis, seperti matahari yang muncul sebentar sebelum sore jadi malam. Tanpa menunggu jawaban, ia membungkukkan sedikit badannya, lalu berbalik—langkahnya cepat, tapi ragu. Seolah ingin pergi dan tetap tinggal dalam waktu yang sama.
Jongdae berdiri mematung sejenak, melihat punggung Jo Anna menjauh di antara keramaian yang mulai menipis. Ada sesuatu dalam langkah gadis itu yang membuatnya ingin percaya. Bahwa tidak semua kehangatan harus memiliki tempat. Kadang, cukup tahu bahwa seseorang memperhatikan, walau sebatas “semoga tidak terlalu berat hari ini.”
Kalimat itu… cukup untuk membawanya berjalan lagi.
Meski pelan.
Meski sendirian.
Sore hari di Jeonsa menggantung redup seperti selembar kain tua yang kehilangan warna. Langit kelabu, tetapi belum hujan. Awan-awan menggembung rendah, menyapu pucuk gedung dan merayap di antara kabel listrik yang membentang seperti garis luka di angkasa. Udara lembap dan hangat, memeluk kulit tanpa ampun. Jalanan utama mulai dipenuhi kendaraan yang beringsut pelan, membunyikan klakson dengan kesabaran yang sudah menipis.
Chenchun Dak, restoran ayam goreng yang tak pernah benar-benar sepi, berdiri dengan jendela besar yang memantulkan cahaya redup langit. Lampu gantung berwarna kuning pastel menggantung rendah dari langit-langit bercat krem. Dindingnya dipenuhi pigura-pigura kayu berisi tulisan tangan pelanggan tetap, beberapa sudah mulai pudar, tapi tetap dibiarkan di sana seolah waktu sendiri tak diizinkan menghapusnya. Aroma bawang putih, lada hitam, dan minyak panas menggantung pekat di udara. Lantai keramik sudah mulai lengket meski baru saja dipel—tanda sore ini akan berat.
Di dapur, panci-panci besar mendidih, penggorengan menjerit dalam gelegak minyak yang terus dipaksa bekerja. Api menyala tanpa jeda. Suara-suara kasar melayang: panggilan pesanan, suara piring yang beradu, dan langkah cepat para pelayan yang nyaris seperti gerak tentara di medan perang.
Jongdae berdiri di ruang ganti kecil yang sempit, merapikan apron hitamnya. Langkahnya berat, tapi wajahnya datar. Ia berjalan melewati dapur yang sempit, mencari sosok yang biasa menyambutnya dengan candaan ringan: Areum. Tapi hari ini, hanya wajah lelah Honyun yang menyambutnya—pucat, berkeringat, dan gusar.
“Areum belum datang?” tanya Jongdae pelan, tapi kalimatnya tertelan oleh kegaduhan.
Honyun menoleh secepat kilat, napasnya memburu.
“Kalau dia datang, aku nggak akan sekarat begini, kan?!” Honyun mengibas apron yang sudah kotor, kemudian berteriak ke arah dapur, “Yang take-away meja tujuh mana?! Udah sepuluh menit, bodoh!”
Jongdae mengangguk kecil, menelan kekesalannya. Ia tak bertanya lebih lanjut. Sorot matanya menajam sesaat, tapi segera padam oleh tanggung jawab yang membebani langkahnya. Ia mengambil alih stasiun konter, mencetak bon pesanan, mengatur piring, dan menjawab keluhan pelanggan dengan senyum tipis yang ia paksa bertahan di wajah.
Lima menit berlalu seperti lima tahun. Pelanggan mulai mengetukkan jari di meja. Seorang pria paruh baya bersuara keras, “Ini pelayanan atau tes kesabaran?!”
Saat itulah pintu restoran terbuka perlahan, dan Areum muncul.
Langkahnya gontai, seperti tubuhnya kehilangan sumbu. Rambutnya acak-acakan, jatuh di sisi wajah yang basah oleh keringat atau air mata—Jongdae tidak bisa memastikan. Bajunya lusuh, lecek seperti baru digulung dari lantai. Matanya sembap, merah di sudut-sudutnya. Sejenak, waktu seperti enggan bergerak.
Honyun menatap tajam. Napasnya mendesis seperti akan menyemburkan api.
Areum tidak bicara banyak. Ia berjalan ke balik konter, berdiri di samping Jongdae, dan hanya bisa berulang kali menggumam, “Maaf… maaf, aku—maaf.”
Jongdae tidak menoleh. Tangannya sibuk menyusun minuman di baki, suaranya datar tapi lembut. “Ambil bon meja sembilan dan sebelas. Take-away. Susun urutannya.”
Areum mengangguk cepat, tangannya gemetar saat menyentuh kertas bon.
Di tengah kekacauan itu, seorang pelayan lelaki ikut turun tangan. Namanya Taeyoon—pemuda tanggung dengan tubuh ramping dan gerak lincah, rambut kecokelatan yang diikat asal di belakang kepala. Ia sudah lama bekerja di Chenchun Dak, lebih pendiam dari yang lain, tapi selalu cekatan. Ia menepuk pelan bahu Areum dan berkata, “Aku bantu bawa ke dapur. Kamu rapikan bonnya aja dulu.”
Areum tersentak, seperti ingin menangis, tapi menahan.
Sementara itu, Honyun menggebrak meja dapur. “Satu lagi ayam bakar pakai bawang, aku gak mau lihat ada yang gosong lagi atau kita semua mati bareng!”
Sore itu di Chenchun Dak, setiap orang bergerak seperti dalam sebuah simfoni kacau—masing-masing nadanya keras, nada dasarnya marah, dan melodi yang tak selesai. Tapi di antara semua kekacauan itu, ada satu irama lirih yang berdenyut diam-diam: kekhawatiran Jongdae yang belum punya bentuk, tentang Areum—tentang apa yang terjadi padanya sebelum pintu itu terbuka.
Jongdae berdiri di balik konter seperti akar yang dipaksa tumbuh di tanah retak. Tangannya sibuk, tubuhnya bergerak, tapi benaknya melayang tak tentu arah. Waktu mengalir seperti minyak panas—mendidih, menggeliat, dan menyisakan luka bakar di dalam hati. Sorot matanya sesekali mencuri pandang ke arah Areum, yang kini sibuk menyusun bon pesanan dengan tangan gemetar. Gadis itu seperti daun kering yang tertiup paksa ke musim yang tak diinginkannya.
Ada perasaan aneh yang bersarang di dada Jongdae. Bukan semata kekhawatiran, bukan juga amarah. Lebih dalam, lebih sunyi, seperti ruang kosong di balik dada yang tak mampu diisi oleh apapun. Ia ingin bertanya. Ingin tahu kenapa mata Areum sembab, kenapa napasnya berat seperti habis berlari dari sesuatu yang menakutkan. Tapi Jongdae tahu, sore itu bukan waktu yang tepat untuk jadi penyelamat. Ada pelanggan yang marah. Ada minyak yang harus diganti. Ada dunia yang tetap berjalan meski satu orang nyaris rubuh.
Suasana dapur semakin panas, secara harfiah dan emosional. Suara desis minyak menjerit nyaring bersamaan dengan suara teriakan Honyun.
“Aku bilang jangan terlalu asin! Kalian bikin restoran atau rumah sakit darah tinggi, hah?!”
Jaewoo, salah satu staff dapur, seorang pria bertubuh besar dengan celemek penuh noda tepung, menghentikan kegiatannya seketika. Ia meletakkan sutil ke meja dengan suara tak yang tajam, lalu menatap Honyun dengan pandangan setajam pisau daging.
“Aku sumpah, kalau kau ngomong lagi soal asin, aku lempar sutil ini ke kepalamu, Honyun!”
Ketegangan mengunci ruangan, udara seolah mendadak berhenti mengalir.
Taeyoon yang baru kembali dari membawa pesanan pelanggan, segera menepuk dada Jaewoo pelan. “Hyung, sabar. Nanti pelanggan lihat.”
Honyun mendengus, tapi ekspresinya jelas bergeser. Takut. Ia melirik sutil yang masih menganggur di meja, lalu berpaling pura-pura sibuk menata saus. Perlahan, satu per satu pesanan mulai keluar dari dapur. Suara kemarahan pelanggan berganti dengan bunyi sendok dan gelas. Seperti badai yang mulai menjauh, ketegangan perlahan mencair, meski belum benar-benar hilang.
Honyun mulai melunak. Ia bahkan menawarkan teh botol ke seorang pelanggan dengan suara yang hampir… sopan. Nyaris terdengar manusiawi.
Namun ketenangan luar itu tidak berlaku bagi Jongdae. Di dalam dirinya, laut masih bergelora.
Jongdae menarik napas panjang dan melirik jam dinding. Sudah pukul lima lewat. Cahaya sore yang masuk dari jendela makin keemasan, menciptakan siluet panjang di lantai. Tapi Jongdae tidak melihat keindahannya. Matanya sibuk menatap bayangan Areum yang bergetar.
‘Kenapa dia datang dalam keadaan begitu?’
Jongdae menunduk, membasahi lap kain dengan air dingin. Ia mengusap meja konter berulang kali, bukan karena kotor, tapi karena pikirannya butuh sesuatu untuk digenggam.
‘Aku tahu perasaan hancur saat harus bekerja seolah dunia tidak sedang meremukkanmu. Aku tahu rasanya berdiri tegak saat dalamnya sudah remuk. Tapi... entah mengapa, rasanya lebih berat melihat orang lain yang memikul beban itu sekarang. Apalagi Areum.’
Ia menggigit bibir bawahnya. Ingatan tentang Seowon tadi pagi tiba-tiba muncul, memercik seperti bara di dalam hujan.
Jongdae memejamkan mata sejenak. Dunia seperti terlalu cepat untuknya hari ini. Seperti semua orang punya arah, punya alasan, sementara dirinya hanya menumpang. Menumpang waktu, menumpang harapan, menumpang napas.
Areum di sisinya, Honyun berteriak di belakang, Jaewoo bersiul kesal sambil menggoreng, dan Taeyoon kembali berlalu membawa nampan. Tapi hati Jongdae tetap kosong. Ia merasa seperti tengah berdiri di tengah pusaran, dan tak ada yang tahu.
Antrean mulai menipis. Suara denting sendok di mangkuk yang beradu dengan waktu menggantikan gelegar protes pelanggan tadi. Udara masih panas, namun tidak sepadat sebelumnya. Jongdae dan Areum berdiri berdampingan di balik konter, tangan mereka sibuk menyusun pesanan terakhir yang akan dikirimkan ke pelanggan yang duduk di meja paling pojok.
Areum masih terlihat lelah, tapi ada sedikit warna kembali di pipinya. Jemarinya mulai tenang saat menyusun saus dan tisu ke dalam kantong. Jongdae melirik sekilas ke arah gadis itu, melihat rambutnya yang awut-awutan dan matanya yang masih sayu. Tapi dari wajah itu, tawa kecil seperti embun mulai turun perlahan, menyapu sisa-sisa kegelisahan.
Mereka tidak banyak bicara. Hanya sepotong kalimat pendek di antara kerja mereka.
“Aku susun yang take away ya,” bisik Areum.
Jongdae mengangguk. “Oke, aku bantu tutup box-nya.”
Lalu hening lagi. Tapi bukan hening yang canggung. Ini hening yang menghangatkan, seperti dua orang yang sama-sama lelah, tapi bersedia berdiri di sisi yang sama dari kekacauan. Mereka mulai bekerja seperti dua tangan dari tubuh yang satu.
Dari arah dapur, Jaewoo masih bergumam kesal.
“Sumpah ya, Taeyoon… pulang nanti, kalau dia buka mulut satu kali lagi, aku giles pakai wajan panas.”
Taeyoon hanya tertawa pelan. “Hyung, jangan, nanti masuk berita. ‘Staff restoran ayam goreng ditahan karena spontanitas emosional’, gimana?”
“Aku nggak bercanda, Taeyoon. Ini bukan ayam goreng. Ini jebakan stres.”
Honyun yang masih mondar-mandir seperti seekor anjing kecil kehilangan tulang, pura-pura tidak mendengar, meskipun jelas ia menelan ludahnya sendiri. Ia bergidik ngeri saat Jaewoo menatapnya seperti singa menimbang mangsa, apalagi ketika pria bertubuh besar itu menyelesaikan pesanannya dan berjalan melewati Honyun dan saat lewat, Jaewoo sedikit—sangat sedikit—meludah ke lantai, hanya beberapa inci dari sepatu Honyun.
Honyun langsung mematung, wajahnya pucat. Tapi ia mencoba bersikap sok tangguh, menegakkan bahu dan mengangkat dagunya. Sayangnya, tak ada yang percaya. Jongdae dan Areum sama-sama melihat kejadian itu. Tanpa bicara, mata mereka saling bertemu. Lalu… tawa kecil meledak seperti letusan balon sabun. Tawa yang pelan, tapi murni. Ringan seperti angin sore yang akhirnya berani masuk ke dalam ruang panas itu. Areum menutup mulutnya dengan punggung tangan, tapi matanya berkilau geli. Jongdae ikut tertawa, tak berusaha menahannya. Untuk pertama kalinya hari itu, dadanya terasa lapang.
Di antara panasnya dapur, letihnya pekerjaan, dan semua yang belum sempat dipertanyakan tentang hari ini—ada detik yang menyejukkan. Detik yang terasa seperti jeda, seperti dunia berhenti memukul mereka, bahkan hanya sebentar. Jongdae mencatat dalam benaknya: tawa Areum, meski pendek, terasa seperti halaman baru yang belum ditulisi apa-apa dan saat Honyun mulai mendekat dengan wajah masam, terdengarlah suara berat Jaewoo dari dalam dapur:
“Hey! Jangan ganggu mereka! Biarin aja, siapa tahu restoran ini bisa jualan tawa juga!”
Areum membalikkan badan, pura-pura sibuk. Jongdae menatap lantai sambil tersenyum.
Sore itu, meski Chenchun Dak tetap gaduh dan berminyak, setidaknya ada satu sudut yang sunyi dan hangat. Sudut tempat dua remaja saling memahami tanpa banyak kata, di antara gemuruh dunia yang tak pernah benar-benar reda.
Ruang staff Chenchun Dak berada tepat di balik dapur, tapi syukurlah ada pendingin ruangan yang membuat udara di dalamnya terasa lega, meski samar-samar masih terdengar teriakan dari dapur dan derak wajan bertemu minyak. Dindingnya dipenuhi rak-rak berisi alat tulis, tisu, dan kotak P3K yang nyaris habis isinya. Sebuah kalender berwarna pudar tergantung miring, jarumnya berhenti di hari yang sudah lewat. Meja kecil di sudut ruangan dijejali kotak makan dan botol minum milik karyawan, sementara dua kursi lipat berwarna biru kusam menjadi tempat paling nyaman bagi siapa pun yang ingin sekadar meletakkan tubuhnya sejenak dari hiruk pikuk.
Jongdae dan Areum duduk di sana, masing-masing dengan seporsi ayam goreng hangat dan nasi bungkus dari dapur—bonus yang Jaewoo siapkan untuk semua staff sore itu, kecuali satu orang: Honyun.
Sebelum masuk ke ruang staff, Jongdae sempat menyapa Jaewoo yang sedang mengguyur tangan dengan air di wastafel dapur. Wajah Jaewoo terlihat kesal seperti tadi, meski sudah tidak berteriak. “Kalau dia gangguin Areum dan Jongdae lagi, aku sumpah, aku yang turun tangan. Nggak peduli seberapa manja dia ke bos,” gumamnya sambil menyeka tangannya dengan apron yang sudah belepotan tepung.
Jongdae menoleh, mencoba menahan senyum.
“Aku udah kerja dari jam sepuluh pagi, belum sempat duduk, dan dia—dia malah ribut soal siapa yang lupa kasih irisan lobak!” Jaewoo mengerang, lebih pada dirinya sendiri. Areum yang mendengar dari balik pintu dapur menunduk, menahan tawa di balik masker. Jongdae menepuk pelan bahu Jaewoo, lalu berdua masuk ke ruang staff.
Di dalam, Areum menyingkap masker dari wajahnya dan mengambil napas dalam-dalam. Wajahnya masih terlihat lelah, matanya sembab, tapi ada sedikit rona malu di pipinya saat Jongdae duduk di sebelahnya.
Untuk beberapa menit pertama, mereka hanya makan dalam diam. Hanya suara sendok menyentuh kotak nasi dan dengung lembut AC yang mengisi udara. Jongdae mencuri pandang ke arah Areum. Ia melihat gadis itu berusaha keras terlihat biasa, memunguti sisa remah ayam dengan hati-hati seperti sedang menata kembali hidup yang baru saja hancur sebagian.
Ia tidak mengatakan apapun, tapi tubuhnya berkata lebih dari cukup, pikir Jongdae. Tangan yang sedikit gemetar. Wajah yang berusaha tenang. Dan senyuman kecil yang lebih mirip permintaan maaf daripada sapaan hangat.
Areum membuka mulutnya perlahan, “Maaf, Jongdae… sekali lagi, maaf.”
Jongdae meletakkan sendoknya, menoleh. “Areum, kamu kenapa terus-terusan minta maaf?”
Gadis itu terdiam. Seperti sedang menimbang: apakah rasa takutnya cukup besar untuk tetap membungkam atau sudah cukup sesak untuk akhirnya bicara.
“Aku…,” suaranya nyaris tak terdengar, “aku habis lihat Ayah mengambil uang Ibu tadi siang.”
Jongdae mengerjapkan mata, menahan detak jantung yang melambat.
Areum menunduk, tangannya mencengkram celana kerjanya yang sudah kusut. “Aku nggak tahu harus ngapain. Aku takut, Jongdae. Dia tahu aku lihat… dia tarik aku masuk ke kamar dan kunci dari luar. Aku—aku panik banget. Aku nekat keluar lewat jendela kamar. Untung jendelanya kecil dan bisa dibuka…”
Air mata itu akhirnya menetes, jatuh ke punggung tangannya. Suaranya patah.
“Aku cuma pakai baju yang tadi aku cuci. Aku bahkan nggak sempat keringin rambut…”
Jongdae tak tahu harus berkata apa. Yang bisa ia lakukan hanyalah menatap gadis di sebelahnya itu dengan perasaan yang remuk. Di benaknya, Areum adalah gadis yang selalu tangguh di balik canggungnya, tapi malam ini… malam ini ia hanya seorang anak perempuan yang ketakutan.
Ia tak butuh saran. Tak butuh kalimat heroik. Ia hanya butuh ruang, dan Jongdae ada di sana—menjadi ruang itu.
Areum mengusap ujung matanya dengan punggung tangan, cepat-cepat, seolah berharap air matanya tidak sempat dilihat utuh. Tapi Jongdae melihatnya. Ia melihat semuanya—ketakutan yang dibalut dengan permintaan maaf, luka yang dibiarkan membusuk dalam diam. Hatinya mencelup ke dalam perasaan yang belum sempat ia beri nama.
Ia merendahkan nada suaranya. Lembut, tetapi bulat.
“Kamu nggak sendiri, Areum.”
Areum menoleh perlahan. Di matanya masih ada sisa ragu, juga nyeri yang belum sempat reda. Tapi ucapan Jongdae—singkat dan tenang itu—seperti secercah napas di tengah air yang nyaris menenggelamkannya.
“Kalau kamu nggak bisa cerita ke siapa-siapa… kamu bisa cerita ke aku,” lanjut Jongdae, menatapnya dengan sorot mata yang tidak menuntut, tidak memaksa. Hanya menawarkan ruang.
Areum menggigit bibir bawahnya. Jemarinya mengepal di atas paha, menahan guncang.
“Aku takut, Jongdae…” bisiknya, “…kalau aku cerita ke Ibu, dia nggak akan percaya. Dia terlalu sayang sama Ayah. Dia selalu bilang Ayah itu ‘lelah, bukan jahat’. Tapi aku lihat sendiri…”
Jongdae hanya diam. Ia tahu, kadang keheningan adalah bahasa yang paling lembut untuk menemani seseorang hancur.
Areum menarik napas dalam-dalam. “Aku cuma pengin sekolah kayak biasa. Kerja kayak biasa. Nggak harus lari dari rumah cuma karena aku tahu sesuatu yang nggak seharusnya aku tahu.”
Kali ini, Jongdae menunduk. Ia mengerti. Lebih dari yang Areum bayangkan.
“Kadang,” gumamnya pelan, “yang paling menyakitkan itu bukan saat kita disakiti… tapi saat kita ngerasa salah karena tahu kebenaran.”
Areum memejamkan mata. Kalimat itu menusuk terlalu tepat. “Iya,” ia mengangguk kecil. “Itu rasanya.”
Beberapa detik berlalu tanpa suara, kecuali desahan lembut AC dan suara spatula dari dapur yang terdengar sayup. Areum akhirnya menyandarkan punggungnya ke dinding, menghela napas panjang seolah baru saja menyusuri setengah gunung dari dalam dadanya.
“Terima kasih,” ucapnya kemudian. “Udah dengerin aku.”
Jongdae tersenyum samar. “Aku nggak bisa ngasih solusi… tapi aku bisa tetap duduk di sini.”
Areum menoleh ke arahnya, menatap dengan mata yang mulai tenang.
Untuk pertama kalinya hari itu, dalam ruang staff kecil yang pengap dan sederhana, dua orang remaja yang sama-sama menyimpan luka akhirnya bisa merasa tidak terlalu sendiri.
Pintu ruang staff terbuka dengan bunyi yang terlalu keras. Seolah dunia yang sempat teduh itu harus kembali diganggu oleh kenyataan yang enggan memberi jeda. Honyun berdiri di ambang pintu, menyandarkan tubuhnya dengan posisi sok santai, tangan menyilang dan senyum tipis yang tidak ramah menghiasi bibirnya.
“Wah, wah…” ucapnya, suaranya seolah ditaburi gula yang busuk. “Kalian berdua betah banget ya di sini. Kayak lagi piknik.”
Areum menoleh pelan, tapi tak berkata apa-apa. Ekspresinya tenang, nyaris datar. Matanya memandangi Honyun seolah lelaki itu hanyalah riak di atas permukaan air yang sebentar lagi akan tenang kembali.
Jongdae melirik sekilas, tidak tergesa, lalu kembali menunduk ke sisa makanannya yang sudah mulai dingin. “Ada perlu?”
“Perlu? Wah, ini restoran bukan rumah singgah buat trauma, Dae.” Nada Honyun menggantung di udara. “Tapi ya, aku ngerti sih. Kalau kamu disayangin sama Jaewoo dan teman-teman dapur. Mungkin karena kamu pintar bermanis-manis kayak Areum juga.”
Jongdae meletakkan sendoknya dengan tenang. Tangannya tak bergetar, tetapi matanya mulai memicing, tajam namun tidak marah.
Ia menatap Honyun dalam-dalam, dan untuk sesaat, tak ada Jongdae si pekerja yang tenang—yang duduk di sana adalah seseorang yang bisa membaca luka orang lain bahkan lewat kebisingan yang dibuatnya sendiri.
“Lucu juga kamu, Honyun. Nyinyir, sinis, suka nyindir… tapi masih berdiri di tempat yang sama sejak dua tahun lalu.” Jongdae tersenyum tipis. “Aku nggak tahu siapa yang bikin kamu sepahit ini. Tapi kamu nggak harus ngeludahin semua orang biar rasa pahitnya hilang.”
Honyun mendesis. “Tapi kamu selalu bela dia, kan? Selalu pasang badan buat Areum. Kamu kira kami semua nggak lihat?”
Areum mengangkat kepala. Sorot matanya dingin tapi mantap. Namun Jongdae lebih dulu menanggapi—tenang, datar, tanpa perlu suara meninggi.
“Kalau kamu lihat aku membela Areum, itu karena aku manusia. Dan karena dia pantas dibela,” ujarnya. “Aku kerja di sini bukan cuma buat ikut peraturan. Tapi juga buat kerja bareng orang-orang yang lelah, tapi masih bisa senyum. Aku nggak akan tinggal diam kalau ada yang diinjak cuma karena lagi jatuh.”
Diam sesaat. Honyun tampak hendak menimpali, tapi Jongdae menatapnya lagi, kali ini lebih dalam, lebih jujur.
“Dan kalau kamu nanya aku punya perasaan apa ke Areum… dia adik buatku. Teman seperjuangan. Dan nggak semua kedekatan harus kamu tafsirkan pakai otak penuh prasangka.”
Areum menghela napas panjang. Ia bangkit dari duduknya perlahan, berdiri tegap meski tubuhnya masih menyimpan lelah dan sisa gemetar. Tapi matanya… matanya kini menyala.
“Aku nggak tahu apa yang kamu pikirin soal aku, Honyun. Tapi aku tahu kamu nggak suka aku dari dulu. Kamu bisa terus bilang apa aja sesukamu,” katanya lirih, namun tegas. “Tapi aku nggak akan minta maaf karena jadi seseorang yang nggak sesuai ekspektasimu.”
Honyun terdiam. Ada keraguan di balik wajahnya yang biasa pongah. Matanya menghindar dari tatapan Areum dan Jongdae, lalu ia menyeringai kaku, setengah tertawa sinis, sebelum membalikkan badan dan meninggalkan ruangan tanpa suara.
Pintu menutup. Hening menggantung.
Jongdae mengembuskan napas berat, lalu menoleh ke arah Areum yang masih berdiri.
“Areum…”
Gadis itu perlahan duduk kembali. Wajahnya masih tegang, tapi bahunya turun sedikit. Ia menunduk.
“Maaf kalau aku tadi terlalu emosi,” katanya pelan.
Jongdae menggeleng lembut. “Kamu nggak salah. Kadang yang paling perlu dilawan bukan orangnya… tapi luka yang kita simpan terlalu lama.”
Areum menatapnya, dan di antara keheningan itu, ada rasa yang tumbuh pelan-pelan—bukan cinta yang meledak, tapi kasih yang memahami.
Pintu ruang staff kembali terbuka. Tapi kali ini bukan dengan aura penuh drama. Justru bau harum ayam goreng crispy yang menyeruak lebih dulu, lalu muncul kepala Jaewoo yang menengok seperti kura-kura penasaran dari balik daun pintu.
“Hey! Dua sejoli tukang makan! Mau nunggu ayamnya tumbuh bulu lagi baru keluar?”
Areum sontak menoleh, pipinya sedikit memerah. “Bukan... kami cuma—”
“Aku bercanda, anak ayam,” potong Jaewoo sambil menyeringai, lalu mendorong pintu dan masuk sambil membawa nampan berisi es jeruk dan beberapa potong nugget sisa dapur. “Tenang aja. Cuma mau pastikan kalian belum kabur bareng bawa rice cooker restoran.”
Jongdae mengangkat alis. “Rice cooker-nya seberat anak SD, Jaewoo.”
Jaewoo mendudukkan dirinya sembarangan di kursi lipat yang mengeluh karena beban badannya. Ia menyesap es jeruknya dengan gaya santai dan angkuh, lalu menatap mereka berdua dengan ekspresi sok bijak.
“Kalian tahu nggak, dari semua orang yang kerja di sini, kalian berdua yang paling bikin aku curiga,” katanya. “Soalnya biasanya, kalau dua orang ketahuan duduk bareng dengan ekspresi bingung dan mata sembap... mereka entah baru putus, baru jadian, atau baru ketahuan maling sambal.”
Areum menahan tawa sambil menutup mulutnya. Jongdae tak bisa menahan senyumnya juga. “Kita cuma capek.”
Jaewoo menatap mereka berdua, lalu pura-pura menghela napas berat. “Capek? Huh, jangan mulai. Aku kerja dari jam dua belas, sempat hampir dilempar pisau dapur sama Honyun, dan masih sempat cuci wajan segede drum air. Kalian cuma capek?”
Ia meneguk lagi minumannya. “Kukira kalian habis perang.”
“Kami juga sempat berperang. Tapi bukan pakai pisau dapur,” gumam Jongdae setengah geli.
“Oh ya?” Jaewoo menepuk pahanya, lalu berdiri. “Kalau begitu... istirahat kalian resmi selesai. Dapur kembali memanggil, dan ingat—jangan jatuh cinta di area kerja. Kaldu ayam bisa jadi saksi bisu yang kejam.”
Saat hendak keluar ruangan, Jaewoo menoleh lagi dan menambahkan dengan wajah serius—yang hanya bertahan satu detik.
“Dan satu lagi. Jangan pernah makan nugget terakhir tanpa bilang ke aku. Itu sabotase.”
Pintu tertutup pelan di belakangnya. Hening sebentar, lalu tawa Areum dan Jongdae meledak bersamaan—tawa kecil yang ringan, lega, seolah dunia kembali sedikit lebih baik dari sebelumnya.
Sisa malam menguar perlahan dari sela-sela atap tua Chenchun Dak, seperti uap tipis dari sup ayam yang tinggal ampasnya. Restoran itu telah sunyi. Kursi-kursi dibalik, meja dilap basah, dan lampu gantung redup menggantung seperti mata yang mulai mengantuk. Jam hampir menunjukkan pukul sebelas lewat sepuluh. Di luar, langit kota masih bernafas lembut—hangat dari siang yang panjang, tapi menyisakan hembusan angin yang membawa sisa bau minyak, debu, dan kesibukan yang baru saja dibungkus oleh malam.
Jongdae menghela napas saat ia menarik rolling door besi berkarat hingga hampir turun penuh. Suaranya menderit seperti batuk orang tua. Di belakangnya, Areum berdiri memeluk tas kecil lusuhnya, menanti, menatap jalanan yang perlahan sepi.
“Aku takut pulang,” bisiknya tadi, suara yang kecil, hampir tenggelam oleh derit pintu besi.
Jongdae hanya mengangguk. “Nginap aja di tempatku malam ini. Nanti kamu bisa tidur bareng Naari. Nggak apa-apa, cuma malam ini.”
Areum sempat diam, lalu menunduk dengan suara pelan, “Terima kasih…”
Namun, sebelum langkah mereka benar-benar menjauh dari tempat itu, suara samar menyeruak—patah-patah seperti gelas yang tak sengaja tergeser. Datang dari sisi bangunan, dari celah sempit di antara Chenchun Dak dan toko jjangmyeong yang sudah lama tutup. Sebuah gang yang hanya cukup untuk satu orang berjalan menyamping.
Areum menegang. Matanya membelalak tipis, dan ia menoleh cepat ke arah celah gelap itu. “Tunggu… itu suara Honyun?” bisiknya.
Jongdae diam sejenak, mencoba menangkap apa yang Areum dengar.
“Aku yakin. Itu suara dia… ada orang lain juga.” Nafas Areum terdengar lebih pendek. Ada ketakutan lama yang mendadak muncul, seperti lembaran kenangan yang tidak ingin disentuh.
Tanpa kata, mereka melangkah pelan, menahan suara tapak sepatu seperti menyelinap di antara rahasia yang seharusnya tidak didengar. Jongdae lebih dulu mengintip. Dari balik tumpukan kardus dan drum plastik, ia melihatnya.
Empat siluet berdiri dalam bayang lampu neon yang berkelip. Salah satunya Honyun. Wajahnya pucat, seperti kain yang baru direndam seharian. Sementara tiga pria lain berdiri mengurungnya. Setelan jas mereka licin, rapi—tetapi wajah mereka tidak seperti pegawai perusahaan. Mereka seperti batu yang diasah dengan dendam dan tekanan hidup.
“Hei, aku bilang minggu lalu, kan?!” suara salah satu pria terdengar, dalam dan berat, seperti lemparan batu ke dalam sumur.
“Aku udah ngasih waktu. Sekarang mana duitnya?”
“A-aku cuma butuh waktu dikit lagi… cuman dikit… kumohon…”
“Kau pikir kami pengen denger permohonanmu?!” suara kedua ikut menyambar. Nada tajam, penuh ancaman.
“Aku nggak peduli kau punya restoran, warung, atau hidup di selokan. Duit tetep duit.”
“Aku udah jual motor, aku… aku bahkan minjem sama ayah aku…” Honyun nyaris berbisik. Ia mencengkram lengannya sendiri, seperti menahan tubuhnya agar tidak runtuh.
Areum menutup mulutnya dengan satu tangan, matanya membulat. Jongdae hanya menatap, tubuhnya kaku. Ada desir tak nyaman dalam dadanya—ia benci pada Honyun, seringkali. Tapi tidak pernah ia bayangkan melihat cowok itu gemetar begitu rupa, tubuhnya nyaris membungkuk di depan para pria asing itu.
“Besok sore, jam yang sama. Kami balik lagi.” Suara ketiga terdengar pelan, tapi lebih mengancam dari yang lain. “Kalau gak ada uangnya… kami ambil satu tanganmu.”
Salah satu dari mereka menepuk pipi Honyun keras—bukan pukulan, tapi cukup untuk membuatnya terperanjat.
Langkah mereka mulai menjauh. Areum mundur cepat ke balik tembok, Jongdae menarik bahunya perlahan agar tidak bersuara. Dunia terasa sunyi saat itu. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada orang lewat. Hanya mereka berdua yang bersembunyi di antara tumpukan rahasia orang lain.
Areum berbisik nyaris tanpa suara, “Mereka… itu…”
“Penagih,” gumam Jongdae, matanya tak lepas dari kegelapan gang yang baru saja menelan mereka pergi.
Desiran angin menyusup dari celah dinding. Di udara, bau besi tua dan minyak goreng seolah bergabung dengan rasa yang tak bisa disebutkan—takut, cemas, penasaran, simpati yang terselubung. Untuk pertama kalinya malam itu, Jongdae tidak tahu harus memikirkan siapa dulu: Areum yang ketakutan, atau Honyun yang sedang jatuh dari tempat tertingginya dengan cara paling diam-diam.
Daftar Chapter
Chapter 1: Prolog
173 kata
Chapter 2: Jeonsa – Pagi yang Setengah Di...
7,102 kata
Chapter 3: Di Bawah Langit Yang Terlalu B...
5,276 kata
Chapter 4: Langit Tak Pernah Menunggu
6,005 kata
Chapter 5: Rahasia yang Tak Pernah Dibagi
6,094 kata
Chapter 6: Seutas Benang yang Tak Pernah...
7,734 kata
Chapter 7: Rasa yang Tak Bernama
8,481 kata
Chapter 8: Dalbit dan Jam Pulang Sekolah
11,467 kata
Komentar Chapter (0)
Login untuk memberikan komentar
LoginBelum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan komentar!