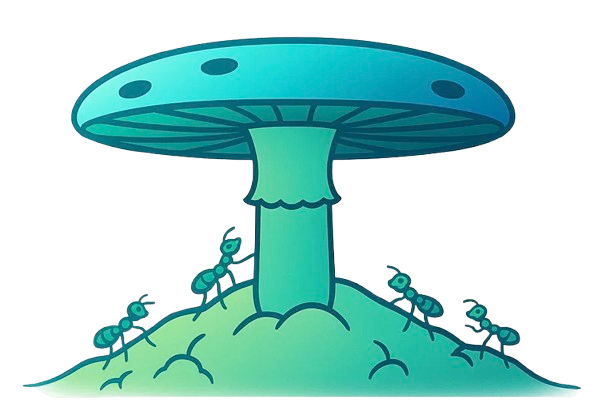Chapter 2: Bau asing Bantal kapuk
Ketukan pintu itu kembali terdengar, lebih berani, seolah tidak mau dibantah. Aku terlonjak, menatap daun pintu cokelat di depanku dengan napas tertahan. Keringat dingin membasahi telapak tanganku. Siapa? Apa aku sudah salah bertingkah?
Aku memberanikan diri melangkah, jantungku berdetak tak keruan. Perlahan, tanganku meraih gagang pintu yang dingin. Aku menariknya sedikit, mengintip.
“Hai, Dens!” Suara ceria itu milik Mei Lin, gadis yang menyapaku sebelumnya. Rambut sebahu miliknya yang hitam legam terlihat berkilau di bawah lampu koridor. Ia berdiri di ambang pintu, tersenyum lebar hingga matanya menyipit. Di tangannya, ia memegang sepiring kecil kue lapis legit. Wanginya samar-samar tercium, manis dan menggoda.
Aku hanya bisa terdiam, terlalu canggung untuk membalas sapaannya. Pipi ini terasa panas.
“Kok melamun? Ayo, dibuka saja pintunya. Aku bawakan kue, barusan Ibu Ratih buat. Enak banget, lho!” Ia menggerak-gerakkan piring di tangannya, seolah merayuku. “Masak kamu mau terus sembunyi di kamar? Nanti dikira patung, lho!”
Aku tersenyum tipis, kali ini sedikit lebih tulus. Akhirnya, aku membuka pintu lebih lebar. “Eh… iya, Mei Lin. Makasih.”
Mei Lin melangkah masuk sedikit, lalu meletakkan piring kue itu di meja belajarku yang kosong. “Santai saja, Dens. Jangan tegang begitu. Aku Mei Lin, tetangga kamarmu yang paling berisik. Itu, kamar sebelahnya Li Hua.” Ia menunjuk ke arah pintu sebelah, lalu kembali padaku. “Kamu dari Jawa Timur, ya? Jauh juga merantau ke Solo. Pasti kaget, kan?”
Aku mengangguk pelan. “Iya. Baru pertama kali ini jauh dari rumah.”
“Wah, sama dong! Aku sama Li Hua juga dari luar kota, tapi masih di Jawa Tengah. Tapi kamu jangan khawatir. Di sini Bu Ratih baik banget kok, galaknya cuma buat biar kita disiplin. Anggap saja ini rumah keduamu,” ucapnya riang. Ia kemudian mengedarkan pandangan ke sekeliling kamarku yang masih kosong melompong. “Kamar nomor tujuh ini memang agak di ujung, jadi lebih tenang. Tapi jangan sampai jadi antisosial, ya! Kalau ada apa-apa, jangan sungkan tanya aku.”
“Oh, iya. Makasih, Mei Lin,” ujarku, berusaha menyusun kata-kata.
“Sama-sama. Oh ya, nanti malam ada Fajar sama Mas Arya mau nobar bola di ruang tengah. Kamu mau ikut? Lumayan, biar nggak kesepian sendirian di kamar.” Mei Lin menatapku penuh harap, matanya berbinar.
Nobar bola? Dengan orang-orang asing? Aku menggeleng pelan. “M-maaf, Mei Lin. Aku… aku capek banget. Mau istirahat saja.”
Wajah Mei Lin sedikit berubah, namun senyumnya segera kembali. “Oh, begitu. Ya sudah kalau begitu. Tidak apa-apa. Tapi kalau berubah pikiran, langsung saja ke ruang tengah, ya! Ramai kok. Jangan sungkan!”
Ia berbalik, hendak keluar dari kamarku. “Aku balik ke kamar dulu, ya. Kalau butuh apa-apa, teriak saja. Kamarku cuma beberapa pintu dari sini.”
“Iya,” jawabku singkat.
Mei Lin melambaikan tangan, lalu keluar dan menutup pintu kamarku. Aku mendengar langkah kakinya yang riang menjauh, lalu suara pintu tertutup pelan. Aku kembali sendiri, dan keheningan mendadak terasa lebih pekat dari sebelumnya. Kue lapis legit di meja itu seolah menjadi satu-satunya tanda bahwa interaksi tadi benar-benar terjadi.
Aku kembali ke tempat tidur, duduk di tepi kasur busa yang terasa asing. Kehangatan Mei Lin tadi hanya sesaat, kini digantikan oleh gelombang kesepian yang lebih dalam. Apakah aku sudah membuat keputusan yang salah? Meninggalkan kehangatan rumah, kenyamanan kota kecil, untuk terdampar di tempat asing ini?
Malam menjelang. Langit Solo di luar jendela berubah menjadi hitam pekat, dihiasi bintang-bintang yang tampak enggan bersinar terang. Aku mencoba memejamkan mata, memaksakan diri untuk tidur, tetapi pikiran-pikiran yang kalut terus berputar di kepalaku. Bau bantal kapuk yang sudah usang itu terasa asing, tidak seperti bantal di rumah yang beraroma sabun dan kehangatan ibu.
Tak lama, suara-suara mulai bermunculan. Dari kejauhan, klakson kendaraan masih terdengar, disusul suara anjing menggonggong. Lebih dekat lagi, aku bisa mendengar suara air mengalir dari kamar mandi, lalu dengungan musik samar dari kamar yang lain. Suara orang berbicara, tawa renyah, seperti sebuah orkestra asing yang sedang memainkan simfoni malam. Aku menghela napas panjang, membenamkan wajah ke bantal.
Kemudian, terdengar suara tawa yang lebih keras dan obrolan yang riuh dari kamar sebelah, tepat di samping kamarku. Sepertinya itu kamar Fajar, atau mungkin Mas Arya? Entahlah. Yang jelas, mereka sedang nobar bola yang Mei Lin ceritakan tadi.
“Wah, itu pelanggaran jelas banget, wasitnya buta apa gimana sih?” Suara seorang pemuda terdengar kesal, disusul tawa renyah. Aku yakin itu Fajar, dari intonasinya yang terdengar ‘sok asik’ seperti yang Mei Lin bilang.
“Santai, Jar, masih awal kok. Jangan emosi duluan!” sahut suara lain, lebih berat dan kalem. Mungkin Mas Arya.
“Gimana mau santai, Mas? Ini kan pertandingan penentu! Kalau kalah, kita cuma bisa gigit jari!” Fajar menyahut lagi, nadanya sedikit meninggi. “Eh, kamu tahu enggak, yang di tim sebelah itu kan pernah jadi bintangnya liga amatir waktu itu? Kenapa sekarang jadi loyo begini mainnya?”
“Mungkin lagi ada masalah pribadi kali, Jar. Kita kan enggak pernah tahu beban hidup orang,” timpal suara ketiga, lebih pelan dan cenderung seperti bisikan, tapi masih bisa kudengar samar-samar. Sepertinya suara Li Hua, adik Mei Lin.
“Ah, masa sih? Kalau masalah pribadi sampai mempengaruhi performa di lapangan, berarti kurang profesional dong! Kan harusnya bisa dipisahkan,” Fajar berkata dengan nada sinis. “Kayak si Budi itu lho, dulu dia kan pernah pacaran sama mantannya si Anu, terus pas tanding jadi musuhan. Kan lucu!” Tawanya meledak, diikuti oleh tawa Mas Arya dan Mei Lin. Aku yakin Mei Lin ada di sana juga, karena tawanya yang khas itu tak bisa salah dengar.
“Itu kan drama sinetron, Jar! Beda sama bola,” Mei Lin menimpali, suaranya terdengar ceria. “Lagian, si Budi sama si Anu kan memang udah putus dari lama. Kamu ini gosipnya kok sampai ke situ-situ!”
“Justru itu, Lin! Kan seru kalau ada bumbu-bumbu begitu. Jadi enggak cuma nonton bola doang, tapi ada hiburan ekstra!” Fajar tertawa lagi, lebih keras. “Eh, Mas Arya, menurutmu gimana? Profesionalisme dan masalah pribadi, bisa dipisahkan enggak sih?”
Mas Arya hanya berdeham. “Tergantung orangnya. Ada yang kuat mental, ada yang gampang terpengaruh. Setiap orang kan beda-beda.”
“Nah, kan! Betul juga kata Mas Arya. Makanya aku bilang, si Budi itu memang mentalnya tempe!” Fajar kembali mengejek. “Coba kalau dia jadi aku, pasti udah jadi pahlawan lapangan!”
“Halah, paling juga baru sepuluh menit udah ngos-ngosan!” Mei Lin mengejek balik, diikuti gelak tawa mereka yang semakin membahana.
Obrolan mereka terus berlanjut, berputar dari pertandingan bola, gosip pemain, sampai candaan-candaan ringan yang hanya dimengerti oleh mereka. Aku berbaring di kasur, telingaku mau tak mau menangkap setiap kata. Aku mencoba memejamkan mata lagi, berharap suara-suara itu akan mereda, namun obrolan mereka justru semakin hidup, seolah tak peduli dengan orang yang mencoba tidur di kamar sebelah.
Setiap tawa, setiap candaan, terasa seperti pukulan langsung ke ulu hatiku. Mereka punya teman, mereka punya obrolan, mereka punya tawa. Sementara aku? Aku hanya berbaring di sini, sendirian, mendengarkan. Rasa kesepian memuncak, menusuk-nusuk hingga ke sudut hati.
Bagaimana aku bisa bertahan di tempat seperti ini? Aku yang canggung dan pendiam, bisakah aku menemukan tempat di antara mereka yang begitu ramah dan riuh? Aku meragukan segalanya. Keputusan ini, apakah benar? Apakah aku akan berakhir sebagai bayangan di antara keramaian ini?
Air mataku menetes, membasahi bantal kapuk yang berbau asing itu. Aku ingin pulang. Aku ingin berteriak.
Tiba-tiba, suara ketukan di dinding kamarku terdengar. Dua kali, pelan tapi tegas. Ketukan itu berasal dari kamar sebelah, kamar Fajar dan yang lain. Suara obrolan mereka mendadak hening. Mereka pasti menyadari aku terganggu.
Aku tersentak. Apakah aku sudah membuat keributan dengan tangisanku? Ataukah mereka memang sengaja menghentikan obrolan mereka, karena menyadari aku ada? Aku tahu mereka mendengarku, atau setidaknya merasakan kehadiranku yang sendirian di balik dinding.
Keheningan itu berlangsung lama, terasa begitu berat dan canggung. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas. Sampai akhirnya, suara pintu terbuka pelan dari kamar sebelah. Jantungku berdebar semakin kencang. Apakah mereka akan menghampiriku? Memarahiku? Atau justru...
Daftar Chapter
Chapter 1: Pintu coklat nomer tujuh
1,187 kata
Chapter 2: Bau asing Bantal kapuk
1,261 kata
Chapter 3: Sarapan omelan
1,020 kata
Chapter 4: Gula Jawa dan sapaan
1,198 kata
Chapter 5: Suara yang tak pulang
1,230 kata
Chapter 6: Kilas balik: nasehat ibu
881 kata
Chapter 7: Anak jakarta
981 kata
Chapter 8: Sketsa di teras belakang
1,180 kata
Chapter 9: Mesin cuci berulah
1,598 kata
Komentar Chapter (0)
Login untuk memberikan komentar
LoginBelum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan komentar!