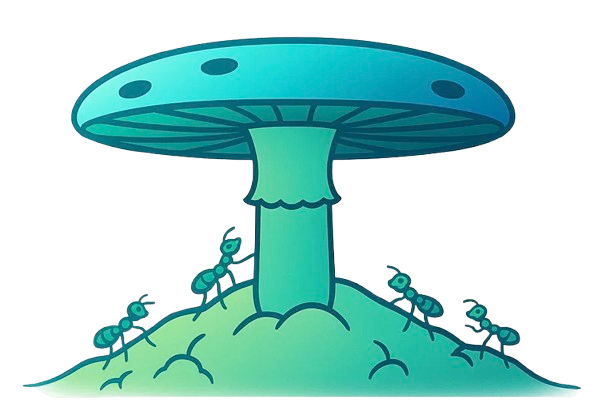Chapter 3: Sarapan omelan
Malam itu, aku tidak bisa tidur. Suara ketukan di dinding yang mengakhiri riuhnya obrolan dari kamar sebelah masih terngiang. Aku tidak tahu apakah aku harus berterima kasih atau justru merasa lebih malu. Keheningan yang menyusul terasa lebih berat daripada segala tawa mereka sebelumnya. Aku membalikkan badan, mencoba mencari posisi yang nyaman di atas kasur busa yang masih terasa asing, namun pikiranku terus berputar. Apakah mereka mendengarku menangis? Apakah mereka mengejekku dalam hati? Beban di dadaku terasa begitu nyata, seperti batu besar yang menghimpit.
Pagi menjelang dengan cepat, membawa serta aroma masakan dari dapur. Bau bawang goreng dan tumisan sayur menyeruak masuk ke celah-celah pintu, perlahan mengusir sisa-sisa kesedihan malam. Perutku yang kosong mendadak bereaksi. Aku belum makan sejak tiba kemarin sore, dan bau sedap itu sungguh menggoda. Dengan langkah ragu, aku keluar dari kamar, mengikuti aroma.
Lorong kos masih sepi. Beberapa pintu kamar tertutup rapat, yang lain sedikit terbuka, menampakkan kegelapan di dalamnya. Aku melangkah pelan, seperti pencuri, sampai akhirnya tiba di ruang tengah yang sekaligus berfungsi sebagai dapur dan ruang makan. Di sanalah, berdiri tegap di depan kompor dengan wajan besar mengepul, ada seorang perempuan paruh baya. Rambutnya diikat rapi, mengenakan daster batik motif parang. Itulah Bu Ratih, pemilik kos.
Ia sedang membalik nasi goreng dengan cekatan. Aroma rempah dan kecap manis langsung menyergap indra penciumanku. Aku berhenti di ambang pintu, terlalu segan untuk melangkah lebih jauh.
“Nah, akhirnya muncul juga penghuni nomor tujuh!” Suaranya renyah tapi ada intonasi ketegasan yang tak terbantahkan. Ia menoleh, menatapku dengan mata tajam yang seolah bisa membaca seluruh isi pikiranku. “Dens Bagus, kan? Ayo sini, jangan cuma melongok di pintu. Sarapan sudah siap.”
Aku tergagap. “E-eh, iya, Bu. Selamat pagi.”
“Pagi. Ayo, duduk. Jangan sungkan,” katanya, tapi nada suaranya tidak mengundang kesantaian. Aku melangkah masuk, menarik salah satu kursi kayu di meja makan yang panjang. Di atas meja, sudah tersaji piring-piring berisi nasi goreng, telur ceplok, dan kerupuk. Sebuah teko berisi teh hangat juga mengepul di tengahnya.
Bu Ratih menyendokkan nasi goreng ke piringku, porsi yang cukup besar untuk perutku yang lapar. “Ini khusus untuk kamu, anak baru. Biar kuat nanti dengerin ceramah saya,” ucapnya, sambil tersenyum tipis yang entah mengapa terasa seperti peringatan. Aku hanya bisa menunduk, menerima piring itu dengan kikuk.
“Jadi begini, Dens,” Bu Ratih memulai, suaranya kini sedikit melambat, penuh penekanan. “Kamu di sini itu kan merantau. Jauh dari orang tua. Nah, saya di sini fungsinya seperti orang tua kedua. Jadi, kalau ada aturan, ya harus diikuti. Jangan sampai bikin masalah.”
Aku mengangguk cepat, menyuap sesendok nasi goreng yang langsung terasa nikmat di lidah.
“Pertama, kebersihan. Kamar masing-masing itu tanggung jawab sendiri. Jangan sampai saya lihat ada sampah numpuk atau baju kotor berserakan. Saya ini anti sekali sama kotor. Kalau kamar mandi dan dapur, itu tanggung jawab bersama. Kalau sudah pakai, ya dibersihkan. Jangan cuma numpang lewat.” Ia menunjuk ke arah kamar mandi dan dapur dengan sendok nasi gorengnya, seolah sedang memberikan komando militer.
“Kedua, jam malam. Pintu gerbang itu saya kunci jam sepuluh malam. Kalau mau pulang lewat dari itu, ya izin dulu. Jangan main nyelonong masuk saja. Apalagi kalau bawa teman menginap, wah, itu saya tidak suka sama sekali. Ini kos putra-putri, tidak bisa sembarangan.”
Pipi dan telingaku terasa panas mendengar penekanan pada “kos putra-putri”. Aku membayangkan kejadian semalam, saat mereka semua riuh nonton bola. Apakah aku melanggar aturan dengan menangis? Atau justru mereka yang melanggar jam malam? Aku mengamati ekspresi Bu Ratih, mencari petunjuk, tapi wajahnya tetap serius.
“Ketiga, listrik dan air. Pakai secukupnya. Jangan boros. Ingat, ini bukan rumahmu sendiri. Apalagi kalau malam-malam pakai AC sampai pagi, padahal cuaca tidak terlalu panas. Itu namanya buang-buang uang.”
Bu Ratih melanjutkan, rentetan aturannya mengalir bagai air bah. Mulai dari larangan memelihara hewan, kewajiban membayar uang kos tepat waktu, sampai himbauan untuk bersosialisasi tapi tetap menjaga privasi. Aku hanya bisa mengangguk, sesekali bergumam “iya, Bu” saat ia memberi jeda untuk menarik napas.
“Intinya, saya di sini cuma mau anak-anak kos nyaman dan aman. Kalau ada masalah, jangan sungkan cerita. Tapi jangan sampai masalah kecil jadi besar gara-gara tidak mau terbuka. Paham?” Ia menatapku intens, menunggu jawabanku.
“Paham, Bu,” jawabku pelan.
“Bagus. Nah, sekarang makan yang banyak. Habiskan itu nasi gorengnya. Kamu kelihatan kurang gizi.”
Baru saja aku hendak menyuap lagi, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki riang dari lorong. Mei Lin muncul, rambut hitamnya diikat ekor kuda, mengenakan kaus oblong bergambar kartun dan celana pendek. Di belakangnya, adiknya, Li Hua, berjalan lebih tenang, memegang buku sketsa.
“Selamat pagi, Bu Ratih!” sapa Mei Lin ceria, langsung menuju meja makan dan mengambil piring. “Wah, nasi gorengnya sudah habis banyak, ya? Dens, kamu sudah sarapan?”
Aku mengangguk canggung, menatap Mei Lin yang sudah terlihat segar bugar, seolah tidak pernah bergadang semalam. Li Hua hanya tersenyum tipis padaku, lalu duduk di pojok, membuka buku sketsanya.
“Tentu saja sudah sarapan, Mei Lin. Bu Ratih kan sudah bilang, anak baru harus sarapan banyak biar kuat dengerin ceramah saya,” Bu Ratih menimpali, melirikku dengan senyum tipis. Aku merasa pipiku kembali memanas.
“Hahaha, betul itu, Bu!” Mei Lin tertawa. “Dens, nanti kamu pasti cepat akrab kok sama Bu Ratih. Galaknya cuma di depan saja. Kalau sudah kenal, nanti malah dikira anak sendiri.” Ia mengedipkan mata padaku, seolah ingin memberi kode bahwa semua akan baik-baik saja.
Aku tidak tahu harus membalas apa. Aku hanya menunduk, melanjutkan sarapan. Mendengar Mei Lin berbicara, aku merasakan sedikit kelegaan. Tapi omelan Bu Ratih tadi, meski diiringi nasi goreng lezat dan senyum tipis, tetap meninggalkan kesan mendalam. Aku merasa seperti baru saja menjalani ujian masuk yang ketat. Di tempat baru ini, bahkan untuk sekadar sarapan pun aku harus melewati serangkaian aturan dan omelan. Bagaimana aku bisa bertahan jika setiap hari akan seperti ini?
Bu Ratih mengambil secangkir teh, menyesapnya perlahan. Matanya menyapu sekeliling, lalu kembali padaku. “Oh ya, Dens. Karena kamu anak baru dan kamar nomor tujuh itu jarang sekali ada penghuninya, saya ada satu tugas khusus untukmu.”
Jantungku berdebar. Tugas khusus? Apa lagi? Aku menatap Bu Ratih, menunggu dengan napas tertahan. Kali ini, ekspresinya tidak bisa kubaca. Apa yang akan datang setelah ini? Sebuah tantangan baru yang akan semakin menguji batasku di tempat asing ini? Atau justru… sesuatu yang jauh lebih berat?
Daftar Chapter
Chapter 1: Pintu coklat nomer tujuh
1,187 kata
Chapter 2: Bau asing Bantal kapuk
1,261 kata
Chapter 3: Sarapan omelan
1,020 kata
Chapter 4: Gula Jawa dan sapaan
1,198 kata
Chapter 5: Suara yang tak pulang
1,230 kata
Chapter 6: Kilas balik: nasehat ibu
881 kata
Chapter 7: Anak jakarta
981 kata
Chapter 8: Sketsa di teras belakang
1,180 kata
Chapter 9: Mesin cuci berulah
1,598 kata
Komentar Chapter (0)
Login untuk memberikan komentar
LoginBelum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan komentar!