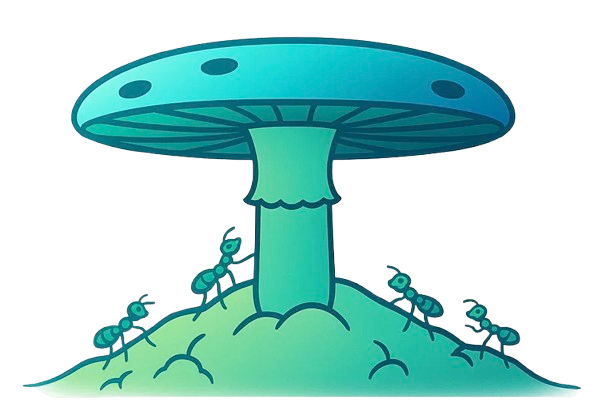Chapter 5: Suara yang tak pulang
Malam hari, setelah mendengar cerita Mei Lin tentang pintu terkunci di balik kamarku, rasanya seperti ada beban tak kasat mata yang menimpaku. Setiap hembusan angin yang menyelinap dari celah jendela pun terasa seperti bisikan rahasia, membuatku semakin gelisah. Aku mencoba untuk membaca buku pelajaran, tapi mataku hanya menelusuri barisan kata tanpa benar-benar mencerna maknanya. Pikiranku terus-menerus kembali pada Mas Arya, pada cerita aneh penghuni kamar nomor tujuh sebelumnya, dan pada pintu misterius di belakang sana.
Lewat tengah malam, saat keheningan kos telah mencapai puncaknya, sebuah suara mengusikku. Langkah kaki yang berat dan gontai, disusul suara gesekan sandal yang diseret. Langkah-langkah itu terdengar tidak stabil, seperti seseorang yang sedang kelelahan, atau mungkin sedang mabuk. Aku menahan napas, menajamkan pendengaranku. Suara langkah itu semakin mendekat, melewati kamar-kamar lain, dan akhirnya berhenti di depan kamar Mas Arya. Kudengar bunyi kunci diputar dengan terburu-buru, lalu pintu dibanting pelan, seolah pemiliknya tidak ingin membuat keributan, namun gagal. Setelah itu, senyap kembali. Aku berbaring kaku, jantung berdegup kencang. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan Mas Arya. Keheningan setelah suara itu justru terasa lebih mencekam daripada suara-suara itu sendiri.
Pagi harinya, saat aku turun untuk sarapan, suasana di dapur terasa lebih tenang dari biasanya. Hanya ada Bu Ratih yang sedang sibuk meracik bumbu di dekat kompor, dan Li Hua yang duduk di meja sudut, dengan sketsa buku terbuka di depannya. Aroma masakan Bu Ratih yang gurih samar-samar tercium, tapi tidak cukup untuk membuat perutku bergejolak seperti biasa.
Aku mengambil tempat duduk di dekat Li Hua, mencoba terlihat santai, meskipun pikiranku masih dipenuhi pertanyaan. Beberapa menit kemudian, Mas Arya muncul dari kamarnya. Matanya terlihat merah dan bengkak, dengan lingkaran hitam pekat di bawahnya, seperti panda yang baru bangun dari hibernasi panjang. Di pipi kanannya, sebuah memar ungu kebiruan terlihat jelas, kontras dengan kulitnya yang pucat. Ia berjalan perlahan, ekspresinya datar, seolah memar itu bukan apa-apa. Ia hanya mengambil sepotong roti tawar, menuangkan teh tawar ke gelas, lalu duduk di pojok, diam-diam melahap sarapannya tanpa menatap siapa pun.
Aku melirik Li Hua, yang sepertinya juga menyadari perubahan pada Mas Arya, tapi ia hanya mengerutkan kening dan kembali ke sketsanya. Bu Ratih, yang biasanya sangat cerewet dan peka terhadap perubahan kecil di kos, tampak tidak berkomentar apa-apa. Seolah pemandangan wajah memar Mas Arya adalah hal yang lumrah.
Aku memberanikan diri mendekati Li Hua.
“Li Hua, Mas Arya kenapa ya?” bisikku pelan, takut Bu Ratih mendengar.
Li Hua mendongak dari sketsanya, tatapannya tenang. “Aku juga tidak tahu, Dens. Tapi sepertinya ia sering begitu.”
“Sering begitu?” Aku mengerutkan kening. “Maksudnya… sering pulang larut dan mukanya lebam?”
Li Hua mengangguk pelan. “Ya. Dulu aku pernah dengar ia bilang, ia kerja paruh waktu di tempat yang agak… keras. Katanya, untuk biaya kuliah dan kirim uang ke kampung.”
Mendengar penjelasannya, dadaku terasa sesak. Aku tahu perjuangan merantau itu berat, tapi tidak menyangka sampai sekeras itu. “Kerja apa, memangnya?”
Li Hua mengangkat bahu. “Ia tidak pernah cerita detail. Cuma bilang di daerah kota lama, sering angkat-angkat barang. Tempatnya agak remang-remang, begitu.”
“Remang-remang?” gumamku. Rasa ngeri mulai menjalari tulang punggungku. Aku membayangkan Mas Arya bekerja di tempat-tempat gelap, penuh bahaya.
Tiba-tiba, Mei Lin muncul dari kamarnya, bersemangat seperti biasa. Ia langsung menuju meja makan, mengambil piring dan menyendok nasi goreng. Ia tidak langsung menyadari kehadiran Mas Arya yang duduk diam di pojok.
“Pagi semua! Wah, Bu Ratih sudah masak nasi goreng, nih. Pasti enak banget!” serunya ceria, membuat suasana yang tadinya hening menjadi hidup. Kemudian, matanya menangkap Mas Arya. Senyumnya sedikit memudar, tapi ia cepat menguasainya. “Eh, Mas Arya juga sudah bangun. Wah, semangat ya Mas, pagi-pagi begini.”
Mas Arya hanya mengangguk kecil sebagai jawaban, tanpa mengangkat pandangan.
Mei Lin duduk di seberangku, mengamati Mas Arya sejenak, lalu menatapku dan Li Hua dengan sorot mata pengertian. Ia merendahkan suaranya.
“Kalian bahas Mas Arya ya?” tanyanya, berbisik.
Aku mengangguk. “Iya, Mei Lin. Aku khawatir. Tadi malam aku dengar ia pulang larut sekali, langkahnya gontai. Lalu pagi ini… wajahnya memar.”
Mei Lin menghela napas. “Ah, itu sudah biasa. Jangan terlalu dipikirkan. Mas Arya itu memang keras hidupnya. Ia menanggung banyak beban.”
“Beban apa?” tanyaku penasaran.
Mei Lin mengambil sesendok nasi goreng. “Dulu aku pernah dengar, ia tulang punggung keluarga. Adik-adiknya masih sekolah, orang tuanya sakit-sakitan. Jadi ia harus cari uang tambahan mati-matian, selain beasiswa kuliahnya.”
Hati kecilku terenyuh. Aku yang hanya merantau untuk kuliah saja sudah merasa berat, apalagi Mas Arya yang harus menanggung keluarganya. “Tapi… memar itu. Apa ia berkelahi?”
Mei Lin menatapku. “Mungkin saja. Dunia kerja sampingan itu tidak selalu bersih, Dens. Kadang harus berurusan dengan orang-orang kasar, atau bahkan menghadapi masalah yang tidak terduga. Makanya, ia selalu kelihatan lelah, dan jarang bicara. Ia menyimpan banyak sendiri.”
Li Hua yang sedari tadi diam, menambahkan, “Aku pernah melihatnya mengobati luka sendiri di dapur. Ia tidak pernah mau dibantu. Ia selalu bilang, ‘Ini bukan apa-apa’.”
Gambaran Mas Arya yang menyendiri, mengobati lukanya dalam diam, membuatku merinding. Aku merasa ngeri sekaligus kasihan. “Kalau begitu, kenapa Bu Ratih tidak menegurnya? Atau membantunya?”
Mei Lin menoleh ke arah Bu Ratih yang masih sibuk di dapur. “Bu Ratih tahu. Ia selalu tahu apa yang terjadi di kos ini. Tapi ia juga tahu batas. Ia tidak mau ikut campur terlalu dalam. Ia menghormati privasi Mas Arya. Lagipula, Mas Arya itu keras kepala. Ia tidak akan mau dibantu kalau tidak mau.”
Aku terdiam, merenungi kata-kata Mei Lin. Sosok Mas Arya yang selama ini kukira hanya misterius karena pendiam, ternyata menyimpan kisah perjuangan yang jauh lebih gelap dan menyakitkan. Aku menyadari, hidup di perantauan bukan hanya soal kuliah dan adaptasi, tapi juga menghadapi kenyataan pahit, perjuangan berat, dan terkadang, luka fisik maupun batin yang harus ditanggung sendirian.
“Dens, aku tahu kamu orang baik. Kamu cenderung ingin membantu,” kata Mei Lin, suaranya kini terdengar lebih serius, tatapannya lurus ke arahku. “Tapi ada beberapa hal yang lebih baik tidak kau campuri. Terutama jika menyangkut Mas Arya. Terkadang, menolong orang yang tidak ingin ditolong justru akan memperburuk keadaan.”
Kata-kata Mei Lin menohokku. Aku merasakan hatiku menciut. Perasaan campur aduk antara kasihan, penasaran, dan takut membaur jadi satu. Aku adalah anak rumahan yang lugu, tak pernah berhadapan dengan situasi serumit ini. Melihat penderitaan Mas Arya, aku merasa tak berdaya. Apakah benar lebih baik diam saja?
Aku menatap Mas Arya di sudut. Ia selesai makan, lalu bangkit dan kembali ke kamarnya tanpa sepatah kata pun. Pintu kamarnya kembali tertutup, mengunci semua rahasia dan lukanya di baliknya. Aku tahu, ada banyak hal di kos ini yang tidak terlihat di permukaan. Bukan hanya pintu terkunci di belakang kamarku, tapi juga rahasia dan beban yang dipikul oleh penghuni lain. Pertanyaan-pertanyaan baru bermunculan dalam benakku. Mengapa Mas Arya sampai harus terluka begitu? Apa yang sebenarnya ia hadapi? Dan apakah aku, seorang pemuda polos dari kota kecil, siap menghadapi sisi gelap dari kehidupan perantauan yang baru saja mulai terkuak di depan mataku?
Li Hua menatapku dengan tatapan prihatin, seolah membaca kegelisahanku. Di sampingnya, Mei Lin kembali menyesap teh, namun kini senyumnya telah menghilang sepenuhnya. Ia tampak berpikir keras, seolah ada hal lain yang ingin ia katakan, tetapi tertahan di ujung lidahnya. Udara di dapur mendadak terasa dingin lagi. Aku menyadari, kos ini bukan sekadar tempat tinggal sementara, melainkan sebuah rumah yang menyimpan banyak cerita, banyak luka, dan banyak rahasia yang menunggu untuk diungkap. Dan sepertinya, aku baru saja menginjakkan kaki di tepi jurang salah satu rahasia terbesar penghuninya. Aku hanya bisa berharap, rasa ingin tahuku tidak akan menyeretku ke dalam masalah yang lebih dalam.
Daftar Chapter
Chapter 1: Pintu coklat nomer tujuh
1,187 kata
Chapter 2: Bau asing Bantal kapuk
1,261 kata
Chapter 3: Sarapan omelan
1,020 kata
Chapter 4: Gula Jawa dan sapaan
1,198 kata
Chapter 5: Suara yang tak pulang
1,230 kata
Chapter 6: Kilas balik: nasehat ibu
881 kata
Chapter 7: Anak jakarta
981 kata
Chapter 8: Sketsa di teras belakang
1,180 kata
Chapter 9: Mesin cuci berulah
1,598 kata
Komentar Chapter (0)
Login untuk memberikan komentar
LoginBelum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan komentar!