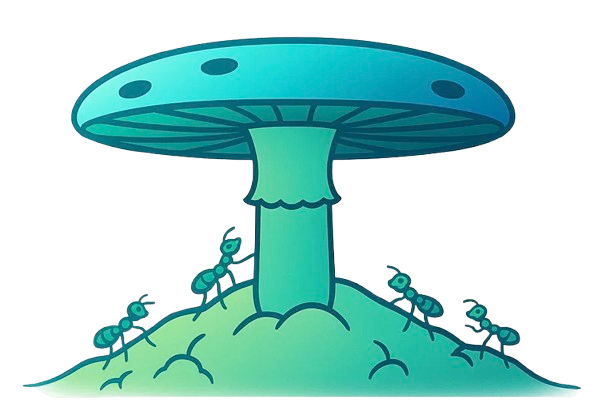Chapter 4: Gula Jawa dan sapaan
Aku masih merasakan beratnya tatapan Bu Ratih, bahkan setelah ia kembali ke cangkir tehnya. Tugas khusus? Kata-kata itu berputar-putar di kepalaku, membentuk skenario-skenario mengerikan. Apakah aku harus membersihkan seluruh kos? Atau mengepel kamar mandi setiap hari? Atau mungkin, yang paling kutakutkan, aku harus menjadi ajudan pribadinya, mendengarkan segala keluh kesahnya? Ketegangan dari pagi itu masih menggantung, membuat sisa nasi goreng di piring terasa hambar.
Mei Lin dan Li Hua terus bercakap-cakap ringan, seolah tak terpengaruh oleh aura mencekam yang baru saja berlalu. Suara tawa Mei Lin yang renyah dan senyum tipis Li Hua adalah satu-satunya pelipur lara saat itu. Namun, meski mereka ada, aku tetap merasa sendirian dengan kecemasanku.
Setelah sarapan usai dan Bu Ratih pamit ke depan, entah mengurus apa, aku merasa sedikit lega. Tapi kecanggungan masih melingkupiku. Aku segera bangkit, membawa piring kotor ke wastafel, berniat untuk mencuci piringku sendiri. Saat aku membasuh sisa nasi goreng, aroma teh hangat dari Bu Ratih masih tercium samar. Aku teringat kebiasaan di rumah, selalu minum teh hangat setelah makan. Mungkin secangkir teh bisa sedikit menenangkan sarafku yang tegang.
Aku mengambil cangkir kosong dan teko kecil dari rak. Saat aku mencari kantong teh, sebuah suara mengejutkanku.
“Wah, sudah beres sarapan, Dens? Cepat juga ya makannya.”
Mei Lin berdiri di sampingku, tersenyum lebar. Ia baru saja meletakkan piringnya di wastafel. Jantungku sedikit berdebar. Aku belum terbiasa berinteraksi sedekat ini dengan orang baru, apalagi perempuan seceria Mei Lin.
“E-eh, iya, Mei Lin,” jawabku, sedikit gagap. Aku menunduk, pura-pura sibuk mencari gula. Di rumah, Ibu selalu membuatkan teh dengan gula jawa. Aku merindukan rasa manis legit yang familiar itu.
“Cari apa? Gula? Di sana,” kata Mei Lin, menunjuk toples kaca berisi gula pasir di sudut meja. “Atau jangan-jangan mau bikin teh pakai gula jawa?” Ia terkekeh, seolah bisa membaca pikiranku.
Aku mengangkat kepala, terkejut. “Kok tahu?”
Mei Lin tersenyum semakin lebar, matanya berbinar. “Tentu saja tahu! Dulu, penghuni kamar nomor tujuh sebelum kamu juga suka pakai gula jawa. Bu Ratih sampai punya stok khusus untuk dia. Kamu mau?”
Penghuni kamar nomor tujuh sebelumnya? Aku merasa ada benang merah yang samar, tapi terlalu malu untuk bertanya lebih lanjut. Rasa penasaran bercampur dengan rasa tak enak karena merasa terlalu banyak bertanya.
“Eh, boleh… kalau ada,” kataku pelan.
Mei Lin dengan gesit meraih sebuah toples kecil di lemari atas, di dalamnya terlihat bongkahan-bongkahan gula jawa berwarna cokelat gelap. “Nih, ambil saja. Bu Ratih tidak akan marah kok. Dia justru senang kalau ada yang mau menghabiskan gula jawa. Katanya, gula jawa itu sehat.”
Aku mengambil sepotong kecil, memasukannya ke dalam cangkir, lalu menyeduh teh celup dengan air panas dari dispenser. Aroma teh dan gula jawa yang mulai larut perlahan menguar, memberiku sedikit rasa nyaman yang sudah lama tidak kurasakan sejak tiba di kota itu.
“Gimana, Dens? Sudah lebih mendingan dari semalam?” tanya Mei Lin, kini bersandar di ambang pintu dapur, mengamatiku. Wajahnya menunjukkan keprihatinan tulus.
Aku menatapnya. Kehangatan dalam suaranya membuat pertahananku sedikit runtuh. Aku menghela napas. “Semalam… aku tidak bisa tidur. Banyak pikiran.”
“Ah, pasti karena ceramah Bu Ratih, kan? Jangan terlalu diambil pusing. Bu Ratih memang begitu. Galaknya cuma di depan. Aslinya baik kok,” kata Mei Lin, lalu ia berjalan ke arah meja, mengambil sepotong kue bolu kukus yang tersisa dari sarapan tadi. “Mau kue? Ini enak. Buatan Bu Ratih.”
Aku menggeleng pelan. “Tidak usah, terima kasih.”
“Ayolah, Dens. Jangan sungkan. Ini sudah mau habis juga. Nanti kalau sisa, pasti dibuang Bu Ratih. Kan sayang,” godanya, menyodorkan piring berisi kue padaku.
Melihat desakannya yang tulus, aku akhirnya mengangguk, mengambil sepotong kue. Rasa manis dan lembutnya kue itu sedikit menghangatkan hatiku yang kaku.
“Terima kasih, Mei Lin,” ucapku, suaraku sedikit lebih jelas dari sebelumnya.
“Nah, begitu dong. Jangan tegang terus. Santai saja di sini. Kami semua juga anak rantau kok. Sama-sama berjuang,” kata Mei Lin, lalu ia menyesap tehnya. “Jadi, apa yang Bu Ratih bilang soal ‘tugas khusus’ itu?”
Pertanyaannya membuatku tersentak. Aku mengira ia sudah melupakannya. Aku menatapnya, mencari petunjuk.
“Belum tahu pasti, Mei Lin. Dia cuma bilang… karena aku anak baru di kamar nomor tujuh, ada tugas khusus. Aku jadi berpikir macam-macam,” kataku, mencoba untuk tidak terdengar terlalu cemas.
Mei Lin menatap cangkir tehnya, senyum di bibirnya sedikit memudar, digantikan oleh ekspresi yang lebih serius. “Kamar nomor tujuh… ya. Dulu, memang ada cerita tentang kamar itu.”
Aku langsung menajamkan pendengaran. “Cerita apa?”
Mei Lin menghela napas, lalu menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. “Dulu, penghuni kamar itu… dia orang yang sangat tertutup. Suka menyendiri. Tapi dia juga sangat pintar. Dia sering membantu Bu Ratih mengurus kebun belakang yang terbengkalai. Dan juga… dia suka mengajari Bu Ratih soal teknologi-teknologi baru.”
“Lalu… kenapa dia pergi?” tanyaku, semakin penasaran. Perasaan aneh mulai merayapi benakku, seolah ada beban tak terlihat yang kini berpindah padaku.
Mei Lin menyesap tehnya lagi, kali ini lebih lama. “Dia pergi mendadak. Tidak ada yang tahu alasannya. Bu Ratih juga tidak pernah mau cerita detail. Sejak itu, kamar nomor tujuh jadi… agak kosong lama.”
“Jadi, tugas khususnya itu… berhubungan dengan dia?”
Mei Lin mengangkat bahu, sorot matanya kembali ceria. “Mungkin saja. Bu Ratih kan suka ‘mewariskan’ tugas ke penghuni baru. Siapa tahu kamu disuruh merawat kebunnya, atau memperbaiki laptop Bu Ratih yang rewel. Hahaha!”
Meski ia tertawa, ada nada lain dalam suaranya yang membuatku bertanya-tanya. Aku mulai menyadari bahwa keramahan Mei Lin juga memiliki sisi misteriusnya sendiri. Entah mengapa, cerita singkatnya tentang penghuni sebelumnya itu tidak membuatku lebih tenang. Justru sebaliknya, perasaan campur aduk itu semakin membelit. Tugas apa sebenarnya yang menungguku? Dan kenapa kamar nomor tujuh ini seolah memiliki sejarahnya sendiri yang penuh rahasia? Aku meneguk teh gula jawa. Manisnya terasa pahit di ujung lidah. Mei Lin mengamati ekspresiku, senyumnya kembali menghilang.
“Dens,” katanya pelan, suaranya tiba-tiba serius. “Kamu tahu kan kalau kamar nomor tujuh ini letaknya di paling ujung, agak terpencil dari yang lain?”
Aku mengangguk, mengingat lokasi kamarku.
“Nah, di dinding belakang kamarmu itu, persis di baliknya… ada sebuah pintu kecil yang terkunci rapat. Bu Ratih tidak pernah mengizinkan siapa pun menyentuhnya. Dia selalu bilang, itu gudang pribadinya. Tapi aku sering dengar suara-suara aneh dari sana. Kadang seperti gesekan, kadang seperti orang menangis.”
Jantungku berdebar kencang. Pintu kecil? Gudang? Suara aneh? Pikiranku langsung melayang ke ketukan misterius semalam, yang menghentikan tangisanku. Mungkinkah… itu berasal dari gudang yang dimaksud Mei Lin? Dan mungkinkah ‘tugas khusus’ Bu Ratih ini ada hubungannya dengan pintu terkunci itu? Aku menatap Mei Lin, rasa penasaran dan ketakutan bercampur aduk menjadi satu. Wajahnya kini tidak lagi ceria, melainkan serius, seolah ia baru saja memberitahuku sebuah rahasia besar yang seharusnya tidak diungkapkan.
Aku tidak bisa berkata-kata. Pintu kecil itu. Suara-suara aneh itu. Dan tugas khusus Bu Ratih. Semua itu kini terasa seperti potongan puzzle yang mulai menemukan tempatnya, membentuk sebuah gambaran yang jauh lebih gelap dan rumit dari yang kubayangkan. Udara di dapur mendadak terasa dingin. Aku merasakan merinding di punggungku, seolah ada sesuatu yang mengawasiku dari balik dinding kamarku sendiri. Aku menatap Mei Lin, mencari jawaban, tapi ia hanya tersenyum tipis, menyimpan lebih banyak rahasia di balik tatapan matanya. Apa yang sebenarnya menungguku di tempat baru ini? Dan apa isi di balik pintu terkunci itu? Aku merasa seperti baru saja melangkah masuk ke dalam sebuah labirin tanpa peta, dengan sebuah misteri yang perlahan mulai terkuak di setiap sudutnya.
Daftar Chapter
Chapter 1: Pintu coklat nomer tujuh
1,187 kata
Chapter 2: Bau asing Bantal kapuk
1,261 kata
Chapter 3: Sarapan omelan
1,020 kata
Chapter 4: Gula Jawa dan sapaan
1,198 kata
Chapter 5: Suara yang tak pulang
1,230 kata
Chapter 6: Kilas balik: nasehat ibu
881 kata
Chapter 7: Anak jakarta
981 kata
Chapter 8: Sketsa di teras belakang
1,180 kata
Chapter 9: Mesin cuci berulah
1,598 kata
Komentar Chapter (0)
Login untuk memberikan komentar
LoginBelum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan komentar!