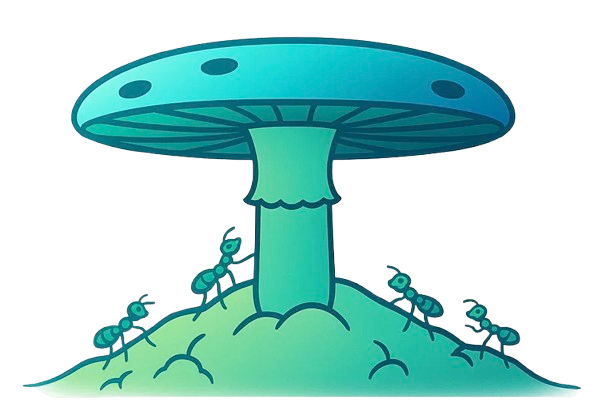Chapter 3: Surat Ketiga, Perihal Lelaki Tua
3 Juli 2024
Untuk Kamu
Sesungguhnya pikiranku lagi kacau-kacaunya, tapi karena kamu butuh tahu banyak untuk meyakinkan dirimu, maka aku pun memaksa diri menulis lagi di tanggal yang sama. Berjam-jam selepas surat kedua. Nantinya bakal kamu baca bersamaan. Kenapa gitu? Ya, karena rasanya sayang banget bila pena dan buku pemberianmu nggak aku isi, seperti katamu, “Tulis apa pun yang kurasakan. Apa pun!”
Rasa-rasanya ingin sekali menulis yang panjang, tapi dalam situasi seperti ini, itu seperti melajukan mobil di jalanan berlumpur. Kamu paham, kan? Nggak mudah.
Sejak lama aku ingin membongkarnya, tapi ketakutan pada stigma buruk dari masyarakat pada tahun itu, bikin keberanianku melempem sebelum mengungkapkan. Bahkan, menulis ini pun, rasa-rasanya seperti sebuah kesia-siaan. Mengapa begitu? Seperti apa yang terjadi sekarang, biarpun aku nggak melihat atau membaca setiap reaksi orang-orang di luar sana, tapi dari respons selepas peristiwa beberapa hari lalu, aku merasa nggak mendapatkan keadilan, selain dirimu yang bagiku pun terlihat ‘mencoba keras untuk bersimpati tapi dengan syarat’.
Maaf bila terlalu jujur mengenai dirimu. Namun, biarpun aku menganggap begitu, aku akan tetap menulis kisah lanjutannya. Oh, iya, sebelum masuk dalam duniaku lagi, terlebih dahulu aku ingin memujimu. Ya, kemarin-kemarin … maaf banget … begini, responsku barangkali terlihat olehmu kayak nggak ingin diganggu dan bikin kurang nyaman. Namun, sejujurnya kamu cantik. Jika kamu terlahir jadi laki-laki, pasti sebandinglah, gantengnya. Ups.
Nggak perlu senyum-senyum baca ini. Eh, tapi kalau mau senyum silakan saja, toh aku nggak melihatnya. Okelah, aku lanjut kisahnya.
~•~
Masih di kala itu, hujan nggak kunjung reda. Aku yang masih kecil, sama sekali nggak tebersit pikiran aneh-aneh. Ustaz Nur bersama dengan Kakek dan Nenek lagi ngobrol. Entah apa yang mereka obrolkan, bahkan aku pun nggak tahu maksud dan tujuan dia bertamu. Yang jelas, setelah Kakek dan Nenek mempersilakan Ustaz Nur duduk di sofa, aku menyingkir dan tiduran di ruang tengah di atas kasur busa yang bertahun-tahun belum diganti.
Kasurnya masih empuk kok, tapi nggak dengan sofa yang berdiri di atas lantai semen di ruang tamu. Semenjak aku dititipkan dan ditinggal merantau orang tua ke Kota Jakarta, dari awal kedatanganku, sofa itu belum pernah diganti. Ya, tinggal di keluarga petani, bisa makan di hari esok itu sudah sangat beruntung.
Omong-omong, sofa itu berjumlah tiga dan diatur menyerupai bentuk huruf L. Terkadang, bagian tubuhku yang bersentuhan langsung dengan kain pelapisnya jadi agak gatal-gatal. Nggak digaruk-garuk sampai lecet kok. Warna kain pelapisnya yang dahulu hijau muda, sekarang kayak warna lumut yang menempel di bebatuan sungai.
Selain itu, setiap sisi sofa, beberapa di antaranya sudah robek, oleh sebab itu, lapisan busa kecokelatan di dalamnya jadi terlihat. Bahkan ada bercak warna dari abu rokok di lengan sofa—Kakek perokok dan pernah aku melihat abu tembakaunya berjatuhan di lengan sofa, saat dibersihkan, ada noda warna abu-abu tertinggal. Nah, Bila kamu mendudukinya, akan terdengar bunyi derit lirih. Kayaknya bunyi itu berasal dari pegas-pegas di dalamnya yang sudah menua.
Biasanya, saat aku pulang mengaji bakal disuruh menyapu ruangan, dan ketika membersihkan bagian bawah sofa, debu dan remah-remah segala macam yang nggak terhitung jumlahnya ikutan tersapu.
Entah berapa menit kemudian, saat hujan reda, aku dipanggil, “Damaiii ….” Suara Kakek resonansinya dalam dan terdengar berat.
Aku nggak menyahut, karena tiduran sekian menit lamanya bikin ngantuk, juga memang malas merespons. Biarlah.
“Damai ….” Nah, saat suara lembut milik Nenek terdengar, dengan masih malas-malas aku duduk selonjor. “Ustaz Nur mau pulang, Dam.”
Aku pun menyahut sambil berdiri dan melangkah menuju ruang tamu. Sekilas aku memandang Kakek dan Nenek, lalu aku tersenyum sebagai bentuk sopan santun pada Ustaz Nur.
“Besok, Senin, mainnya jangan lupa waktu, Dam. Ingat waktu ngaji. Tidak boleh pura-pura kelupaan lagi.” Suara yang keluar dari bibir tipis keunguan Ustaz Nur bikin aku cengar-cengir.
Entah mengapa, pembawaan dia saat bicara nggak bikin anak kecil takut. Dari yang kulihat, biasanya, lelaki beristri yang usianya sudah kepala empat, kebanyakan terlihat muka boros. Entahlah, Ustaz Nur agak berbeda. Wajahnya mungkin tampak ada kerutan halus, tapi masih terlihat awet muda. Dan lagi, wajahnya tirus, bikin tulang pipinya agak terlihat menonjol, tapi garis rahangnya tampak tegas.
Yang bikin aku iri, kulit Ustaz Nur putih tapi agak pucat, nggak kayak aku yang cokelat. Rambutnya belum beruban, entahlah, mungkin dia pakai semir rambut hitam. Rambutnya nggak lurus juga nggak keriting, jadi saat dia menutup kepala dengan kopiah, akan tampak semacam gelombang di bagian yang terlihat. Namun, pada mata sebelah kiri, pupilnya berwarna agak putih keruh. Aku nggak pernah bertanya mengapa begitu.
“Janji berangkat ngaji ya?” Dengan suara yang terdengar agak lembut, Ustaz Nur mendekat dan mengulur tangannya padaku.
Kendatipun paham maksudnya, aku enggan berjabat tangan, dan aku berpaling dari tatapannya.
“Ehem.” Itu bunyi dehaman Kakek. “Sama guru ngaji jangan ….” Aku lupa lanjutan omongan Kakek. Namun, yang jelas, aku lekas menyambut jabatan tangan Ustaz Nur.
~•~
Sampai di sini dulu ya. Sebenarnya bisa lebih panjang lagi, tapi entah mengapa … kamu paham, kan, betapa beratnya mengisahkan ini? Seandainya aku diberi tahu Tuhan, atau mungkin bila Tuhan memberikan kekuatan untuk melawan, dan mungkin jika Tuhan mengasihi aku, kejadian itu nggak akan pernah terjadi, kan?
Dahulu, selama bertahun-tahun, bahkan sampai aku menuliskan kisah ini untuk kamu, aku masih sulit ikhlas menerima jalan dari Tuhan. Boleh, kan, aku kecewa? Namun, yang menjengkelkan itu saat orang-orang yang katanya paling paham agama, justru menghakimi kekecewaan dari orang macam diriku. Selalu saja, orang-orang yang kecewa atas jalan dari Tuhan, dicap sebagai hamba yang nggak tahu cara mensyukuri hidup. Semudah itu terucap tanpa mau tahu dan peduli dengan kekecewaan yang dirasakan.
Kamu nggak begitu, kan? Bila kamu merasa aku termasuk salah karena telah kecewa atas takdir dari Tuhan, nggak apa-apa. Namun, lagi-lagi seperti katamu, “Tulis apa pun yang kurasakan. Apa pun!” Maka inilah perasaan yang sesungguhnya.
Kamu tenang saja. Aku nggak akan menangis. Air mataku sudah banyak tumpah selama ini, sampai-sampai aku sering nggak sadar menggigit-gigit kuku dan terlalu ketagihan mencabut-cabut rambut sendiri. Namun, yang masih menjadi pertanyaan ialah mengapa masih hidup? Katanya mengakhiri hidup sendiri itu dosa, maka dari itu aku setiap malam berdoa dan memohon untuk nggak bangun lagi, tapi sepertinya Tuhan masih ingin melihatku tersiksa menghadapi hidup.
Mungkin aku memang terlalu berprasangka buruk kepada Tuhan. Seharusnya setiap napas yang kuhirup itu disyukuri, tapi lagi-lagi, aku benar-benar lelah. Sehingga setiap kali terbangun dari tidur, yang kurasakan lebih banyak hampa. Barangkali aku sudah lupa rasanya bahagia. Kamu sehat-sehat di sana ya. Besok pasti kisahnya lanjut lagi.
—Damai Sentosa —
Daftar Chapter
Chapter 1: Surat Pertama Damai Sentosa Un...
128 kata
Chapter 2: Surat Kedua, Perihal Selepas K...
736 kata
Chapter 3: Surat Ketiga, Perihal Lelaki T...
1,054 kata
Komentar Chapter (0)
Login untuk memberikan komentar
LoginBelum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan komentar!