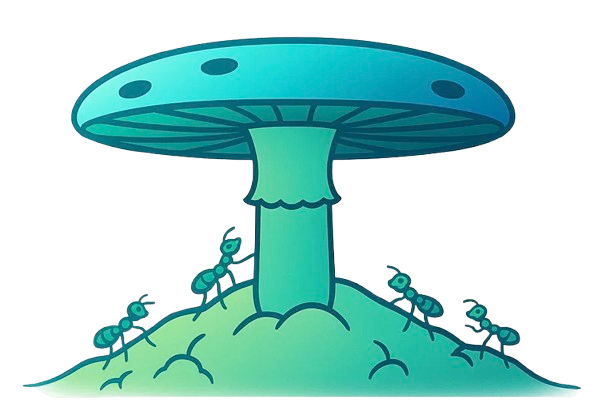Chapter 2: Surat Kedua, Perihal Selepas Kemarau Panjang
2 Juli 2024
Untuk Kamu
Kala itu, kemarau panjang telah membuat tanah gembur di ladang mengering, seolah-olah merindukan air yang telah lama sembunyi. Jalan di desa yang belum beraspal menampakkan retakan-retakan kecil di permukaannya. Daun-daun pohon pun tampak layu dan mengering, bak lelah menjalani hidup. Genting-genting rumah warga termasuk milik Kakek dan Nenek, bila dilihat dari kejauhan, atap-atapnya terlihat bagaikan permadani merah yang kehausan. Bahkan saat langkah kaki menyentuh tanah kering, debu halus mengepul ke udara dan berputar-putar di bawah terik matahari. Parahnya air di setiap sumur warga semakin surut. Semua itu kulihat saat musim kemarau berkepanjangan melanda Desa Sarang Manis.
Seolah-olah Tuhan telah merasa cukup mengunci hujan, siang di kemudian harinya, yang awalnya kuduga akan terik, tahu-tahu langit mendung. Para warga yang lagi di luar rumah termasuk aku—kendatipun aku nggak bertanya langsung—bahagia banget.
Benar saja, aroma basah yang sepertinya dirindukan banyak orang, menguar dan terhirup hidungku. Hujan turun dengan lembut, seperti tengah melepas dahaga tanah yang merindu akan tetesan air. Aku lekas masuk rumah.
Sebagaimana anak-anak seumuran, aku ingin mandi air hujan, berlari menyusuri setiap jalan pedesaan, bermain di gang-gang yang dipenuhi air dari talang atap rumah, atau sekadar berjalan santai di pematang sawah. Namun, sebelum aku bisa keluar rumah, Kakek sudah berdiri dengan sapu di genggaman yang melambai-lambai ke arahku. Jika aku berani keluar, ujung sapu itu pasti menyambar pantatku.
Namun, aku nggak takut, malah meledek beliau biar tersulut dan mendekat, tapi Nenek bilang padaku dengan aksen 'ngapaknya', “Hujan pertama isinya penyakit. Besok bolehlah hujan-hujanan.” Sering memang, kalimat semacam itu diucapkan oleh orang tua di sini, entah itu betul atau nggak.
Mendadak kami dikejutkan bunyi pintu diketuk-ketuk. Terdengar bunyi salam, “Assalamualaikum.” Aku mengenali suara itu; terdengar halus dan melodis tapi juga dengan aksen 'ngapak'.
Begitulah logat bicara semua warga di sini, 'ngapak' yang begitu kental. Sementara aku, setelah tiga tahun dititipkan dan dirawat orang tua ayahku, Kakek dan Nenek, kendatipun dahulu aksenku ala-ala anak Jakarta, kini berangsur-angsur berubah menyesuaikan lingkungan baru.
Nah, aku bersama Kakek dan Nenek menghampiri pintu depan, lalu aku ‘menarik ke bawah’ gagang pintu tuasnya.
Embusan angin menerpa wajahku, mungkin juga mengenai wajah Kakek dan Nenek. Namun, perhatianku langsung tertuju pada lelaki berumur empat puluh tahunan yang berdiri di beranda—tepat di depan kami, di dekat pintu yang sudah aku buka.
Aku mengenalnya sebagai guru ngaji di masjid, tempat aku belajar banyak tentang agama. Dalam sekejap, lelaki itu tersenyum, tapi segera menunduk lalu buru-buru menutup mulut dengan telapak tangan dan bersin-bersin, yang mungkin dikarenakan kedinginan. Matanya agak menyipit dengan alis berkerut sesaat.
Aku mundur selangkah sambil masih menggenggam gagang pintu. Seakan-akan tertular oleh bersin lelaki itu, aku juga ikutan bersin, tapi berusaha mengarahkannya ke daun pintu yang terbuka.
Ah, daun pintu yang dahulu berwarna hitam sehitam arang, sekarang dihiasi bercak-bercak keabu-abuan yang kemungkinan akibat paparan cuaca bertahun-tahun. Bahkan, serat kayu yang tadinya halus, kini tampak dan bahkan terasa kasar bila disentuh. Tadi pun saat kutarik daun pintu, terdengar bunyi derit dari engsel. Belum lagi gagang pintu tuas, bentuknya yang melengkung dan terbuat dari logam yang dahulu berwarna keemasan, sekarang pudar dan berkarat di beberapa sisi.
Nenek bertanya, “Ada apa, Ustaz?” sedangkan Kakek memandang penuh selidik.
Aku nggak ingat jelas obrolan berikutnya karena memang sudah terjadi bertahun-tahun lalu. Wajar, kan, bila nggak terlalu ingat? Momen itu terjadi dua puluh empat tahun lalu, kira-kira tahun 2000-an, sedangkan diriku sekarang berumur 32 tahun. Namun, masih ada kok bagian-bagian yang kuingat dari apa yang kurasakan: Musim dan suasananya.
~•~
Eh, nanti aku lanjut ceritanya!
Bila kamu bertanya suasana hatiku saat ini, kayak tadi kamu tanyakan di ruangan itu, sebenarnya segala macam emosi lagi campur aduk, seperti segala macam warna dipadukan dan menjadi kelabu. Maaf banget bila pertemuan pertama kita tadi, sulit bagimu mencoba dekat. Bukan karena menolak kehadiranmu, tapi lebih pada bahwa kita ini baru bertemu dan aku sungguh sulit untuk bisa percaya pada orang baru.
Aku yakin kamu mengerti karena sudah seharusnya paham terkait profesimu. Namun, di tempat ini, ketika banyak orang-orang berseragam, begitu tertarik dengan motif pembunuhan itu, dan nggak mendapat jawaban berarti sampai mendatangkan dirimu, aku ingin sekali kamu percaya bahwa diriku adalah korban. Korban yang selama ini bungkam sampai bukti-buktinya luntur termakan waktu.
Sepertinya sampai di sini dulu. Kamu nggak perlu menghubungi aku untuk meminta lanjutan. Beri saja aku waktu, dan secara bertahap aku akan membeberkan semua. Kamu sehat-sehat ya. Kira-kira kapan sesi pertemuan kita lagi? Aku nggak sabar!
—Damai Sentosa—
Daftar Chapter
Chapter 1: Surat Pertama Damai Sentosa Un...
128 kata
Chapter 2: Surat Kedua, Perihal Selepas K...
736 kata
Chapter 3: Surat Ketiga, Perihal Lelaki T...
1,054 kata
Komentar Chapter (0)
Login untuk memberikan komentar
LoginBelum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan komentar!