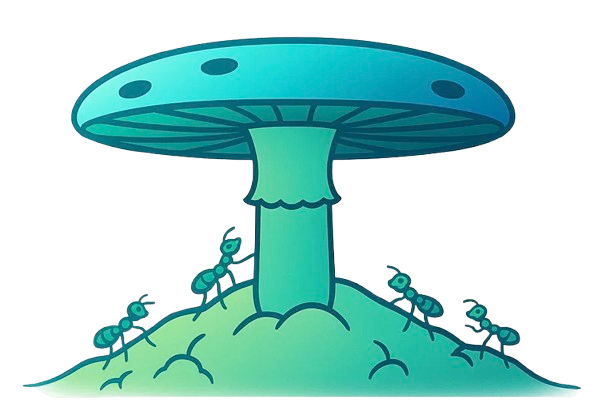Chapter 1: Debat
Ruang kelas itu mendadak terasa lebih sempit ketika nama Arka Narayana disebut.
“Siapa yang mau menanggapi analisis risiko dari kelompok Alea?” tanya dosen sambil menyilangkan tangan.
Beberapa mahasiswa saling melirik. Tidak ada yang benar-benar ingin menjadi orang pertama yang menyela. Alea Mahendra dikenal teliti. Argumennya rapi. Menyerangnya berarti siap dibalas tanpa ampun.
Namun Arka mengangkat tangan dengan santai, seolah ia tidak sedang menantang badai.
“Saya, Pak.”
Alea mendongak dari catatannya. Tatapan mereka bertemu sekilas. Dingin. Terlalu lama untuk sekadar kebetulan.
“Saya rasa pendekatan yang dipakai terlalu konservatif,” ujar Arka, suaranya tenang tapi menusuk. “Asumsi volatilitasnya terlalu ditekan. Itu bikin simulasi keuangan kelihatan aman, padahal realitanya enggak sesederhana itu.”
Beberapa kepala langsung menoleh ke Alea.
Ia tidak terburu-buru menjawab. Menutup pulpen. Menarik napas.
“Kalau kamu baca slide-nya dengan benar,” balas Alea datar, “kamu bakal sadar itu bukan konservatif. Itu realistis. Risiko bukan cuma soal agresif kelihatan pintar.”
Desis kecil terdengar dari bangku belakang.
Arka tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah tulus. “Realistis menurut siapa? Kalau semua orang main aman, perusahaan enggak akan tumbuh.”
“Dan kalau semua orang sok berani,” potong Alea cepat, “perusahaan bangkrut sebelum sempat tumbuh.”
Beberapa mahasiswa mulai gelisah. Ini bukan lagi diskusi biasa.
Arka menyandarkan punggungnya ke kursi. “Kamu selalu pakai ketakutan sebagai dasar perhitungan.”
Alea menatapnya lurus. “Dan kamu selalu menganggap risiko itu permainan ego.”
“Ini kelas manajemen keuangan, Alea,” ucap Arka, kini tanpa senyum. “Bukan kelas bertahan hidup.”
“Justru karena ini manajemen keuangan,” jawab Alea tajam, “bukan tempat buat spekulasi sok heroik.”
Ruangan hening sejenak. Bahkan dosen pun tidak langsung menyela.
“Menarik,” kata dosen akhirnya. “Arka, kamu punya data pembanding?”
Arka mengangguk, cepat. “Ada. Dan kalau Alea mau jujur, pendekatannya itu aman karena dia takut gagal.”
Beberapa orang terkejut. Ini sudah menyentuh ranah personal.
Alea berdiri. Kursinya bergeser sedikit, suaranya jelas terdengar.
“Jangan bawa asumsi pribadi ke dalam analisis profesional,” katanya dingin. “Aku enggak takut gagal. Aku cuma enggak sembrono.”
Arka ikut berdiri. Kini mereka berhadapan.
“Sering kali,” kata Arka pelan, “orang-orang menyebut kehati-hatian sebagai kebijaksanaan, padahal sebenarnya itu cara halus untuk menghindari keputusan besar.”
Alea tersenyum kecil. Senyum yang tidak pernah berarti baik.
“Dan sering kali,” balasnya, “orang-orang menyebut keberanian sebagai visi, padahal itu cuma keinginan buat terlihat unggul.”
Dosen berdeham keras. “Cukup.”
Keduanya duduk kembali, tapi udara di antara mereka belum mendingin. Teman-teman sekelas saling bertukar pandang. Tidak ada yang meragukan satu hal.
Alea Mahendra dan Arka Narayana tidak akan pernah akur.
Setidaknya, itu yang terlihat.
Alea kembali menatap layar presentasi, wajahnya kembali tenang, profesional. Arka menyilangkan tangan, rahangnya mengeras.
Tak satu pun dari mereka menoleh lagi.
Tak satu pun dari mereka menunjukkan bahwa debat itu bukan sekadar soal angka, asumsi, atau teori keuangan.
Dosen belum melanjutkan materi, tapi suasana kelas sudah terlanjur pecah.
“Baik,” kata beliau sambil menatap daftar nilai di tangannya. “Karena diskusinya cukup hidup, saya mau dengar pendapat dari sisi lain. Alea, bagaimana kamu menanggapi strategi ekspansi agresif dengan leverage tinggi di kondisi pasar seperti sekarang?”
Alea mengangkat wajahnya perlahan. Ia tahu ini bukan pertanyaan netral. Ini jebakan intelektual.
“Strategi agresif sah,” jawabnya tenang, “kalau manajemennya disiplin. Tapi leverage tinggi tanpa kontrol ketat itu bukan strategi. Itu perjudian yang dikemas rapi.”
Beberapa mahasiswa menahan napas.
Arka menggeser duduknya. “Menarik,” katanya ringan. “Jadi menurut kamu, perusahaan besar harus takut ambil langkah besar?”
“Aku enggak bilang takut,” sahut Alea cepat. “Aku bilang sadar kapasitas. Enggak semua keputusan besar itu pintar.”
“Kadang keputusan besar itu perlu,” Arka membalas. “Bukan buat aman, tapi buat unggul.”
Alea menatapnya. Kali ini lebih lama. “Unggul buat siapa?”
Pertanyaan itu menggantung.
Arka tersenyum kecil, tapi matanya dingin. “Pemegang saham.”
“Dan ketika gagal?” Alea menyahut. “Karyawan. Investor kecil. Orang-orang yang enggak punya kursi nyaman buat jatuh bangun.”
Kelas mulai berisik. Bisik-bisik muncul dari berbagai arah.
“Ini mulai melebar,” kata dosen, tapi tidak terdengar benar-benar ingin menghentikan.
Arka mencondongkan tubuhnya ke depan. “Kamu terlalu fokus pada worst case scenario.”
“Dan kamu terlalu sibuk membayangkan best case versi kamu sendiri,” balas Alea tanpa menaikkan suara. “Padahal tugas manajemen keuangan itu mengendalikan risiko, bukan memamerkan keberanian.”
Arka tertawa pendek. Bukan karena lucu.
“Kamu selalu bicara seolah-olah kegagalan itu dosa,” katanya. “Padahal kegagalan itu bagian dari pertumbuhan.”
Alea menyilangkan tangan. “Yang tumbuh itu perusahaan atau ego pengambil keputusan?”
Sekarang benar-benar sunyi.
Dosen menghela napas. “Cukup tajam,” katanya, menatap keduanya bergantian. “Tapi ingat, ini diskusi akademik, bukan debat personal.”
Alea mengangguk kecil. “Saya setuju, Pak. Karena itu saya bicara data, bukan asumsi karakter.”
Tatapan Arka mengeras. “Lucu. Padahal kamu barusan menyerang motif.”
Alea tidak berkedip. “Motif selalu memengaruhi keputusan keuangan. Kalau enggak, kita enggak perlu audit.”
Beberapa mahasiswa menunduk, menahan senyum.
Dosen akhirnya mengangkat tangan. “Baik. Kita hentikan di sini. Kalian berdua punya sudut pandang yang valid. Tapi saya harap, lain kali, debatnya tetap fokus pada materi.”
Beliau menoleh ke kelas. “Catat. Risiko bukan soal berani atau takut. Tapi soal bertanggung jawab.”
Alea kembali duduk tegak. Arka menyandarkan punggungnya ke kursi, rahangnya menegang.
Kelas dilanjutkan. Slide berganti. Angka-angka muncul di layar.
Namun tak satu pun dari mereka benar-benar mendengar.
Dosen melirik jam tangannya, lalu menutup laptop.
“Saya izin keluar sebentar,” katanya sambil merapikan map. “Diskusinya ditahan dulu, ya. Jangan ada yang lanjut debat tanpa saya.”
Beberapa mahasiswa mengangguk cepat. Pintu kelas menutup pelan.
Dan justru di situlah masalahnya dimulai.
Keheningan jatuh, tapi bukan keheningan yang tenang. Lebih seperti udara yang menunggu pecah.
Arka memutar kursinya sedikit, menoleh ke arah Alea. “Lo selalu begitu,” katanya pelan, cukup untuk didengar barisan depan. “Sok netral, padahal jelas-jelas berat sebelah.”
Alea mengangkat alis. “Aku berat ke data. Bukan ke ambisi.”
“Ambisi itu perlu,” balas Arka. “Tanpa itu, semua orang cuma jadi pengelola, bukan pemimpin.”
Alea menoleh sekarang. Tatapannya tajam. “Dan tanpa kendali, semua pemimpin cuma satu keputusan buruk dari kehancuran.”
“Lo kebanyakan mikir kemungkinan buruk.”
“Dan lo kebanyakan percaya diri,” sahut Alea cepat. “Itu beda tipis sama ceroboh.”
Beberapa mahasiswa mulai gelisah. Ada yang pura-pura fokus ke layar, ada yang terang-terangan memperhatikan.
Arka tersenyum miring. “Lucu. Lo selalu bicara seolah-olah lo paling tahu cara menyelamatkan semuanya.”
“Karena gue enggak mau jadi alasan orang lain jatuh,” jawab Alea dingin.
“Padahal,” Arka mendekatkan tubuhnya sedikit, suaranya lebih rendah, “kadang orang jatuh karena orang seperti lo terlalu takut melompat.”
Alea berdiri mendadak. Kursinya berdecit cukup keras.
“Jangan samakan keberanian dengan nekat,” katanya. “Dan jangan bawa gaya main aman ke arah seolah itu kelemahan.”
“Kalau kamu sebut itu kekuatan,” Arka ikut berdiri, “kenapa lo kelihatan selalu defensif?”
“Karena aku terbiasa mikir dampaknya,” Alea membalas tanpa ragu. “Bukan cuma hasil akhirnya.”
“Wah,” seseorang berbisik dari belakang, “ini panas.”
Rina, yang duduk di sebelah Alea, langsung menepuk lengan sahabatnya. “Eh, udah weh. Jangan berantem di kelas.”
Alea menoleh singkat. “Ini bukan berantem.”
“Iya, iya,” Rina menyeringai tipis, matanya bergantian menatap Alea dan Arka. “Debat akademis. Tapi serius deh, jodoh tahu rasa kalian.”
Beberapa mahasiswa terkekeh kecil.
Alea langsung duduk kembali. “Ngaco Lo.”
Arka tertawa pendek. “Jodoh? Jangan berlebihan.”
Rina mengangkat bahu. “Lah, orang tiap diskusi kalian kayak orang habis putus tapi belum move on.”
“Rina,” tegur Alea tajam.
“Oke, oke,” Rina menyerah, tapi senyumnya belum hilang. “Cuma bilang. Energinya terlalu niat buat sekadar beda pendapat.”
Arka kembali duduk, menyilangkan tangan. Tatapannya masih tertuju ke depan, tapi rahangnya menegang.
“Tenang aja,” katanya datar. “Gue enggak tertarik sama orang yang mikir semua hal harus aman.”
Alea tersenyum kecil. Penuh sindir. “Bagus. Gue juga enggak tertarik sama orang yang pikir risiko itu cuma angka.”
Kelas kembali sunyi. Tapi kini bukan hanya panas.
Ada rasa lain yang ikut menggantung. Rina memperhatikan mereka berdua dengan kening berkerut, seolah ada sesuatu yang tidak ia pahami, tapi terasa janggal.
Pintu kelas akhirnya terbuka. Dosen masuk kembali.
Dan dalam hitungan detik, Alea dan Arka kembali ke peran masing-masing. Duduk rapi. Wajah datar. Jarak aman.
Daftar Chapter
Chapter 1: Debat
1,271 kata
Chapter 2: Kantin
902 kata
Chapter 3: Rumah
1,728 kata
Chapter 4: 21+
1,321 kata
Komentar Chapter (0)
Login untuk memberikan komentar
LoginBelum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan komentar!