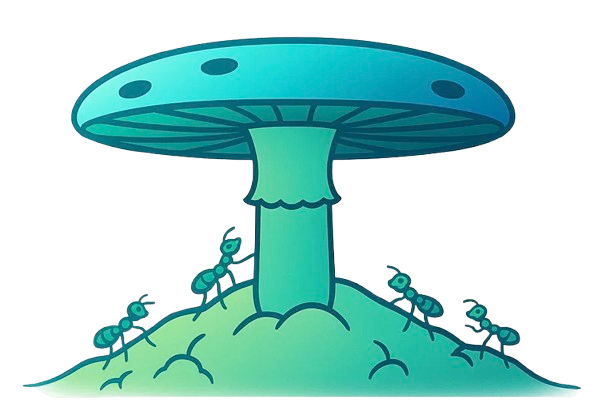Chapter 4: 21+
Arka menunduk lebih dekat.
Ciumannya jatuh pelan di bibir Alea, singkat, seperti sentuhan yang masih menahan diri. Alea tidak langsung membalas, hanya terdiam sepersekian detik sebelum jemarinya mencengkeram kaus Arka, menariknya kembali.
“Lo ngapain,” gumam Alea pelan, napasnya sudah tidak serapi tadi.
Arka tersenyum tipis di sela jarak yang nyaris hilang. “Jahil.”
Alea mendengus kecil, tapi lengannya tidak dilepas. Justru ia mendekat, bibirnya kembali bertemu dengan bibir Arka, kali ini lebih lama. Tidak terburu-buru. Seperti mereka sedang mengingat sesuatu yang sudah terlalu familiar.
Arka memutuskan ciuman itu lebih dulu. Tangannya menyelip ke bawah paha Alea.
“Eh,” Alea refleks bersuara, tapi tidak menolak saat tubuhnya terangkat.
Arka berdiri dengan mudah, menggendong Alea tanpa usaha berlebih. Alea otomatis melingkarkan kakinya, lengannya kembali mengait di leher Arka. Kepalanya bersandar di bahu cowok itu, senyum kecil terselip tanpa sadar.
“Berat,” komentar Arka asal.
“Bohong,” jawab Alea lirih. “Lo kuat.”
Arka tertawa pendek, langkahnya mantap menuju kamar. Lampu ruang tengah mereka biarkan menyala, suara TV makin menjauh, tergantikan keheningan kamar yang hanya diterangi lampu tidur.
Begitu sampai di sisi kasur, Arka menjatuhkan Alea ke atasnya dengan gerakan pelan tapi tegas. Tubuh Alea memantul sedikit di atas seprai, rambutnya berantakan di bantal.
Belum sempat Alea berkata apa-apa, Arka sudah menyusul, menahan tubuhnya dengan satu tangan di samping kepala Alea. Jarak mereka kembali hilang.
Ciuman itu datang lagi. Lebih dalam, lebih lama. Tidak tergesa, tapi penuh niat. Alea membalas dengan sama seriusnya, jarinya menyelusup ke rambut Arka, menariknya lebih dekat.
Di luar kamar ini, mereka adalah dua orang yang harus berpura-pura tidak saling memilih. Dua sosok yang berdiri di garis berbeda, selalu tampak bertentangan.
Di atas kasur ini, semua peran itu runtuh.
Hanya ada Alea yang menghela napas pelan di sela ciuman.
Ciuman itu perlahan berubah ritmenya.
Tidak lagi sekadar pertemuan bibir, tapi bahasa tubuh yang saling mengenal tanpa perlu kata. Napas Alea mulai tidak teratur, dadanya naik turun pelan, sementara Arka menahan dirinya tepat di atas gadis itu, seolah ingin memastikan Alea masih di sana, masih bersamanya.
Tangannya menyusuri sisi tubuh Alea dengan gerakan lambat, penuh kehati-hatian yang kontras dengan intensitas tatapannya. Alea membalas dengan menarik Arka lebih dekat, jarak di antara mereka makin menipis sampai nyaris tidak ada ruang untuk ragu.
“Arka,” panggil Alea pelan, bukan sebagai peringatan, tapi pengakuan.
Nama itu cukup.
Arka menunduk, meninggalkan jejak ciuman di sepanjang wajah Alea, turun ke leher, lalu berhenti di sana sejenak. Ia menghela napas, seperti menahan sesuatu yang terlalu ingin dilepaskan.
Alea menutup mata.
Ia tidak lagi memikirkan kelas, kampus, pandangan orang, atau peran yang harus ia jaga di luar sana. Yang ada hanya detak jantungnya sendiri, dan kehadiran Arka yang begitu dekat, begitu nyata.
Kasur berderit pelan saat mereka bergeser, tubuh mereka mencari posisi yang paling jujur. Lampu tidur memantulkan bayangan samar di dinding, menciptakan siluet dua orang yang saling menemukan rumah dalam pelukan yang sama.
Waktu terasa melambat.
Sentuhan menjadi lebih berani, tapi tetap lembut. Tidak ada yang terburu-buru. Mereka saling membaca, saling menyesuaikan, seolah sudah hafal bahasa masing-masing tanpa perlu dijelaskan.
Alea mencengkeram seprai ketika Arka mendekat lagi, napas mereka bertemu, panas dan dalam. Arka menyandarkan keningnya ke kening Alea, matanya terpejam.
“Lo aman,” bisiknya.
Dan Alea percaya.
Malam itu tidak diisi oleh suara keras atau gerakan kasar. Semuanya mengalir, perlahan tapi penuh makna. Seperti dua orang yang sudah lelah berpura-pura seharian, akhirnya boleh jujur satu sama lain.
Arka belum sepenuhnya menjauh, tubuhnya masih dekat, terlalu dekat untuk sekadar diam.
Alea membuka mata perlahan.
Tatapan mereka bertemu. Tidak ada senyum kali ini. Tidak ada godaan. Yang ada hanya sesuatu yang lebih dalam, lebih berat, seperti kebutuhan yang tidak perlu dijelaskan.
Arka menyingkirkan rambut Alea dari wajahnya dengan gerakan pelan. Jemarinya linger lebih lama dari yang seharusnya, seolah menghafal garis wajah itu sekali lagi.
“Lea,” panggilnya rendah.
Alea menjawab dengan menarik Arka mendekat. Tidak dengan kata. Dengan sentuhan. Dengan cara tubuhnya bergerak tanpa ragu.
Kasur kembali berderit pelan. Napas mereka menyatu, ritmenya semakin tidak teratur. Setiap sentuhan terasa lebih berani dari sebelumnya, tapi tidak kehilangan kelembutannya. Seperti mereka tahu persis batas satu sama lain, dan memilih untuk mendorongnya bersama-sama.
Alea memejamkan mata, jemarinya mencengkeram punggung Arka. Ada helaan napas tertahan, ada desahan kecil yang tidak sempat disaring. Arka menahan tubuhnya sebentar, keningnya menempel di bahu Alea, seolah berusaha menenangkan sesuatu yang sudah terlalu lama ia simpan.
Malam itu bukan tentang keinginan semata.
Ada rindu yang ikut menyusup. Ada lelah yang dilepaskan. Ada kebutuhan untuk saling memiliki, meski hanya di ruang ini, meski hanya dalam diam.
Gerakan mereka semakin menyatu, tidak lagi ragu, tidak lagi hati-hati. Alea menyesuaikan diri dengan Arka, dan Arka membalas dengan kesabaran yang jarang ia tunjukkan pada siapa pun.
Waktu kehilangan bentuknya.
Yang tersisa hanya detak jantung yang berpacu, napas yang saling mencari, dan kesadaran bahwa di dunia yang menuntut mereka berpura-pura setiap hari, momen ini adalah satu-satunya tempat mereka bisa benar-benar jujur.
Ketika akhirnya segalanya melambat, Alea masih memeluk Arka. Dahi mereka bersentuhan, mata terpejam, napas masih berat tapi perlahan kembali stabil.
Arka mengecup pelipis Alea dengan lembut, jauh dari intensitas sebelumnya. Sebuah penutup, bukan akhir.
Alea tersenyum kecil, lelah tapi puas, lalu menyembunyikan wajahnya di leher Arka.
“Jangan kemana-mana,” gumamnya pelan.
Arka mengencangkan pelukannya. “Gue di sini.”
Ponsel Alea tiba-tiba bergetar di atas nakas.
Sekali.
Lalu berhenti.
Lalu bergetar lagi.
Alea mengerjap, napasnya masih belum sepenuhnya kembali teratur. Arka masih dekat, terlalu dekat, tubuhnya belum benar-benar menjauh. Lampu kamar redup, waktu seolah berjalan lebih pelan dari biasanya.
Getaran itu muncul lagi.
Nama Rina menyala di layar.
“Arka,” bisik Alea cepat. “Hp gue.”
Arka melirik ke arah nakas, lalu kembali menatap Alea dengan ekspresi yang sama sekali tidak bersalah. “Angkat aja.”
“Enggak,” Alea menggeleng kecil. “Dia nelpon berkali-kali. Pasti penting.”
Ponsel itu bergetar lagi, lebih lama kali ini.
Alea menghela napas pendek, lalu meraih ponselnya. “Jangan ngapa-ngapain,” katanya pelan tapi tegas, matanya menatap Arka tajam. “Denger enggak?”
Arka mengangguk. Terlalu cepat.
Alea menekan tombol hijau dan langsung menjauhkan ponsel sedikit dari wajahnya, berusaha menormalkan suaranya.
“Kenapa, Rin?”
Di seberang sana, suara Rina terdengar lega. “Akhirnya diangkat. Gue kira lo kenapa-kenapa.”
“Enggak. Gue… lagi di rumah,” jawab Alea.
Arka menunduk sedikit, mendekatkan wajahnya ke leher Alea. Tidak melakukan apa-apa. Setidaknya tidak secara terang-terangan.
Alea menahan napas.
“Oh,” Rina terdengar santai. “Sendirian?”
Alea membuka mulut untuk menjawab, tapi sebelum suara keluar, Arka bergerak sedikit. Gerakan kecil, nyaris tidak terlihat, tapi cukup untuk membuat Alea kehilangan fokus sepersekian detik.
“Hh—”
Suara itu lolos begitu saja.
Alea langsung menutup mulutnya sendiri, mata membesar.
Di seberang sana, Rina terdiam. “Lea?”
“Iya?” Alea buru-buru menjawab, suaranya sedikit lebih tinggi dari biasanya.
“Lo… kenapa?”
“Enggak apa-apa,” Alea cepat-cepat berkata. “Keselek.”
Arka menahan senyum. Tangannya bergerak ringan, benar-benar seperti orang yang sengaja menguji kesabaran.
Alea menatapnya dengan peringatan jelas. Arka hanya mengangkat bahu, ekspresinya polos yang sama sekali tidak bisa dipercaya.
Rina terdengar ragu. “Sumpah?”
“Iya,” jawab Alea, kali ini lebih pelan. Ia menarik napas dalam, berusaha mengatur diri. “Kenapa nelpon?”
“Oh iya,” Rina langsung ingat tujuannya. “Gue mau bilang, besok gue enggak masuk kuliah.”
Alea mengernyit. “Kenapa?”
“Demam. Kayaknya kecapekan. Jadi kalau ada apa-apa di kelas, kabarin gue ya.”
“Yaudah,” jawab Alea. “Istirahat yang bener.”
Arka bergeser sedikit, membuat Alea refleks menggigit bibir. Tangannya mencengkeram seprai, tapi ia tetap memaksa suaranya stabil.
“Lea,” Rina memanggil lagi. “Lo yakin enggak apa-apa?”
“Iya,” Alea menjawab cepat. “Gue cuma capek.”
Rina tertawa kecil. “Capek apaan? Baru jam segini.”
“Capek mikir,” balas Alea.
“Oke, oke. Gue matiin ya. Jangan lupa besok.”
“Enggak lupa.”
Telepon ditutup.
Begitu layar ponsel mati, Alea langsung menjatuhkannya ke kasur. Tatapannya kembali ke Arka, kali ini benar-benar tidak ramah.
“Lo sengaja,” katanya lirih.
Arka tersenyum lebar. “Sedikit.”
Alea memukul dada Arka pelan. “Gila. Kalau dia curiga gimana?”
Arka menunduk, mendekatkan wajahnya. “Dia enggak tau apa-apa.”
Alea menghela napas, campuran kesal dan tidak berdaya. “Lo nyebelin.”
“Tapi lo tetep angkat teleponnya,” balas Arka.
Alea tidak menjawab. Ia hanya menutup mata sejenak, lalu menyandarkan kening ke dada Arka.
“Jangan ganggu lagi,” gumamnya.
Arka mengangguk pelan. “Sekarang fokus ke lo.”
Daftar Chapter
Chapter 1: Debat
1,271 kata
Chapter 2: Kantin
902 kata
Chapter 3: Rumah
1,728 kata
Chapter 4: 21+
1,321 kata
Komentar Chapter (0)
Login untuk memberikan komentar
LoginBelum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan komentar!