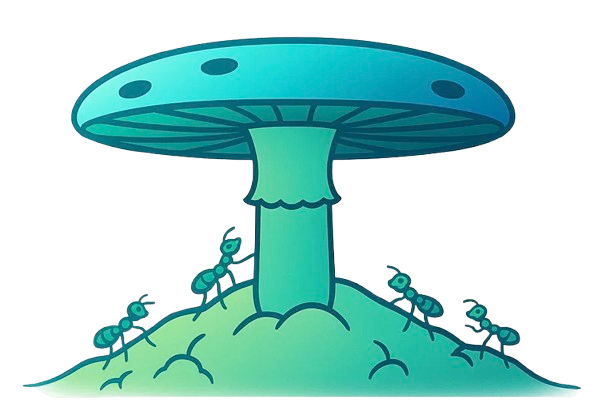Chapter 6: Menatap Lama
Pagi ini cahaya matahari hanya sedikit menembus kaca di kamar dan menimbulkan bayangan kecil yang membuat kamar masih terasa dingin. Aku terbangun dengan kepala berat, nyaris tanpa tidur semalaman. Dua kata itu masih menempel di benak, berputar seperti bisikan yang tak bisa aku abaikan.
“Dia menguji.”
Aku menatap layar ponsel yang tergeletak di meja. Pesan itu masih ada di sana, nyata seperti menertawakan ketakutanku. Jemariku ragu menyentuh layar, seolah dengan menekan tombol saja sesuatu buruk akan segera terjadi. Aku sempat berpikir untuk menghapusnya, tapi apa gunanya? Bayangannya sudah terlalu dalam menggores pikiranku.
Pertanyaan demi pertanyaan menyerbu tanpa henti. Siapa yang dimaksud pengirim pesan? Apakah Raka atau seseorang yang justru lebih dekat denganku? Sebenarnya ujian apa yang dimaksud? Apakah pertemanan kami, kedekatan kami, keberanian kami atau kewarasan kami sendiri? Aku benar-benar masih tidak mengerti.
Kepalaku berdenyut. Nafasku terasa lebih berat. Seakan pagi ini bukan lagi awal yang baru, melainkan kelanjutan dari malam yang menolak pergi.
Aku turun ke ruang tamu dengan langkah gontai. Rumahku masih sunyi, hanya suara jarum jam yang terdengar. Biasanya suara itu menenangkan, tapi kali ini malah seperti detak bom waktu yang menunggu untuk meledak. Waktu terus bergerak, mengingatkanku pada sesuatu yang tak bisa kuhindari. Tentang kesendirian, kesepian serta kurangnya dimengerti keluarga.
Aku menatap ruangan yang begitu rapi dan lengang. Sofa tersusun sempurna, meja bersih tanpa secangkir minuman. Tak ada juga aroma sarapan yang biasanya menandakan rumah penuh kehidupan. Rumah ini terlalu besar untuk kutinggali seorang diri. Terlalu lapang hingga gema langkahku sendiri terdengar asing.
Orang tuaku jauh di negeri seberang. Setiap pagi aku selalu merasakan jarak yang bukan hanya ribuan kilometer, tapi juga jarak hati yang semakin melebar. Mereka sering menelepon, tapi lebih banyak bicara soal tuntutan.
Sebagai mahasiswi harus memiliki nilai yang bagus, sikap harus sempurna, masa depan harus cemerlang, harus dekat dengan orang-orang yang berkualitas dan masih banyak lagi tuntutan lain yang aku rasa tidak seharusnya mengikat gerak langkahku, karena banyak hal yang ingin aku tahu dan pelajari.
Tuntutan menjadi sebuah tekanan yang berangsur-angsur menggerogoti rasa nyaman. Mereka seolah tidak paham jika aku merindukan sosok orang tua yang hangat dan pengertian.
Kadang mereka juga mengingatkan penampilan yang harus rapi, harus cantik, harus menjaga nama baik keluarga. Aku harus bisa bersikap anggun, harus bisa sopan di segala keadaan, harus bisa menguasai banyak hal, seakan-akan aku diciptakan tanpa ruang untuk salah.
Terlalu sering aku mendengar, “Jangan bikin malu orang tua dan kamu harus jadi kebanggaan, bukan malah jadi beban.” Kata-kata itu menempel di kepalaku, menghantui bahkan saat aku hanya ingin bernapas bebas menjadi diriku sendiri.
Di balik semua tuntutan itu, aku hanya ingin mereka mengerti, jika aku bukan boneka yang bisa dipoles agar sempurna. Aku hanya anak perempuan mereka yang kadang ingin menangis tanpa alasan, ingin dipeluk tanpa harus menjelaskan kenapa dan aku juga ingin didengar tanpa dihakimi.
Mereka lupa bahwa aku hanyalah seorang anak perempuan yang kadang ingin bercerita tentang mimpi buruk, tentang resah yang datang tiba-tiba atau sekadar ingin dipeluk tanpa syarat. Kenapa mereka tidak memahami tentang hal seperti ini?
Pagi yang cerah bagi orang lain, bagiku terasa suram. Pembantu rumahku sudah pulang kampung beberapa hari lalu dan satu-satunya orang yang masih ada hanyalah tukang kebun yang datang di siang hari dan sore pulang ke rumahnya yang berjarak satu kilo. Saat pagi seperti ini, aku benar-benar sendirian.
Aku merindukan suara orang tuaku membangunkan dengan lembut, merindukan suasana rumah yang ramai, merindukan kehangatan sederhana yang dulu kupikir biasa saja. Kini, hanya ada aku dan denting jam yang tak henti berdetak.
Kesepian ini menempel erat, bahkan sejak aku membuka mata. Rasanya seperti berdiri di tengah keramaian yang tak terlihat dan aku hidup, tapi tak ada yang benar-benar hadir untukku.
Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan membuat teh japa hangat. Aroma daun teh yang khas seharusnya menenangkan, tapi lidahku tak merasakan apa-apa selain getir. Seolah inderaku pun ikut memberontak.
Belum sempat aku meneguk setengah gelas, ponselku kembali bergetar. Degup jantungku melonjak, tubuhku menegang. Dengan tangan gemetar aku meraih layar.
Nomor asing. Pesan baru.
“Pagi ini, perhatikan baik-baik siapa yang menatapmu paling lama. Di situlah jawabannya.”
Aku terdiam. Kata-kata itu membuat tenggorokanku kering. Perhatikan siapa yang menatapku? Apa maksudnya?
Sejenak aku ingin membuang ponsel itu, menyingkirkannya dari hidupku. Tapi rasa ingin tahu jauh lebih kuat daripada rasa takut. Bagaimanapun, pesan itu terasa seperti petunjuk. Mungkin ... mungkin jika aku menuruti instruksi ini, aku bisa menemukan kebenaran.
Namun, kebenaran macam apa yang menunggu?
---
Hari berjalan pelan. Di kampus, suasana tampak normal, tapi aku tidak bisa mengabaikan rasa asing yang terus menempel. Aula dipenuhi suara riuh mahasiswa, namun semua itu hanya terdengar samar di telingaku, seperti gema dari dunia yang tidak benar-benar nyata.
Aku mencoba bertingkah biasa, tapi setiap tatapan terasa mencurigakan. Setiap senyum tampak palsu. Bahkan ketika Maya menyapaku dengan hangat, aku masih mencari apakah benar itu tulus atau hanya bagian dari permainan yang lebih gelap?
“Leza, kamu nggak apa-apa? Wajahmu pucat banget,” tanya Maya dengan menatapku penuh cemas.
Aku mengangguk cepat, memaksakan senyum. “Aku cuma kurang tidur.”
Tatapannya menahan, lama sekali. Aku tiba-tiba teringat pesan itu. “Perhatikan siapa yang menatapmu paling lama.”
Tubuhku merinding. Apakah Maya?
Sebelum pikiranku melayang lebih jauh, Dimas datang menghampiri. “Kalian lihat Raka nggak? Dari tadi dia nggak kelihatan. Padahal biasanya dia datang duluan.”
Raka. Nama itu membuat dadaku semakin sesak. Aku memutar pandangan, memastikan apakah dia benar-benar tidak ada. Tapi di sela kerumunan mahasiswa, aku tidak menemukan sosoknya. Hanya bayangan samar, seolah dia memang sengaja menghindar.
Arka muncul beberapa menit kemudian, dengan raut wajah serius. Dia menatapku, lama sekali, seakan ingin membaca isi hatiku. Pandangan itu menenangkan sekaligus menakutkan. Lagi-lagi pesan itu menggema di kepalaku. “Perhatikan siapa yang menatapmu paling lama.”
Apakah maksud pesan itu .... orangnya adalah Arka?
Aku segera mengalihkan tatapan, jantungku berdegup tak terkendali. Arka menyadarinya, tapi tidak berkata apa-apa. Dia hanya berdiri di sisiku, jaraknya cukup dekat untuk membuatku merasakan hangat tubuhnya.
Namun ketenangan itu tidak bertahan lama.
---
Saat jam kuliah berakhir, suasana kampus mendadak kacau. Dari ujung koridor terdengar suara gaduh. Beberapa mahasiswa berlari kecil, wajah mereka panik. Aku, Arka, Maya, dan Dimas spontan saling menatap.
“Ada apa?” tanya Maya.
Seorang mahasiswa yang lewat menjawab cepat, “Ada yang jatuh pingsan di dekat taman belakang!”
Kami berempat langsung menuju ke sana. Nafasku memburu, firasat buruk mencengkeram kuat.
Benar saja di dekat taman belakang ada sosok Raka terbaring. Wajahnya pucat, napasnya tersengal. Ada bercak darah tipis di pelipisnya, luka yang semalam kukira ringan ternyata masih membekas.
“Raka!” Dimas berteriak panik, berjongkok di sampingnya.
Maya menutup mulutnya dengan kedua tangan, hampir menangis.
Aku menatap Raka dengan perasaan campur aduk. Ia membuka matanya perlahan, menatapku. Tatapan itu lama, terlalu lama. Waktu seakan berhenti.
Bisikan lirih keluar dari bibirnya sungguh nyaris tak terdengar, tapi cukup jelas menusuk jiwaku.
“Aleza ... hati-hati. Semuanya ... hanya ujian ...”
Darahku membeku. Kata “ujian” lagi. Kata yang sama dengan pesan di ponselku.
Arka meraih lenganku, seakan ingin memastikan aku tidak jatuh. Aku hanya bisa berdiri kaku, mataku tak lepas dari Raka yang setengah pingsan.
Apakah dia yang mengirim pesan itu? Atau dia juga hanya korban, sama sepertiku?
---
Petugas kampus akhirnya membawa Raka ke ruang kesehatan. Maya dan Dimas ikut menemani, sementara aku dan Arka tertinggal di luar ruangan. Udara sore terasa berat, mendung mulai menggantung.
“Ada sesuatu yang nggak beres,” kata Arka akhirnya, suaranya pelan tapi tegas. “Raka ... entah kenapa aku merasa dia bukan lagi Raka yang dulu. Tapi di sisi lain, sepertinya dia juga bukan musuh. Aku sendiri bingung.”
Aku menatapnya, ingin mengatakan tentang pesan misterius itu. Tapi bibirku terkunci. Ada rasa takut kalau aku mengatakan sesuatu yang buruk akan terjadi.
Arka menunduk, lalu menatapku lagi dengan sorot penuh keyakinan. “Apapun yang terjadi, aku akan selalu melindungimu, Leza. Kamu nggak sendirian.”
Kalimat itu seharusnya menenangkan. Namun dalam benakku, pesan itu terus bergema.
“Perhatikan siapa yang menatapmu paling lama. Di situlah jawabannya.”
Aku mengingat tatapan panjang Arka barusan, tatapan yang penuh ketulusan atau mungkinkah hanya topeng yang terlalu sempurna?
Langit semakin gelap, angin berhembus dingin. Hatiku diliputi kebimbangan yang makin dalam.
Untuk pertama kalinya aku bertanya-tanya dengan serius, mungkin pesan itu benar. Mungkin jawabannya memang ada pada tatapan seseorang di antara kami.
Aku hanya belum tahu ... siapa yang sedang menguji dan siapa yang sedang diuji.
Daftar Chapter
Chapter 1: Ruang Bagi Rasa
1,043 kata
Chapter 2: Meredam Kegelisahan
1,023 kata
Chapter 3: Momen Hangat Terganggu
1,176 kata
Chapter 4: Tatapan Penuh Tanya
1,153 kata
Chapter 5: Dinginnya Malam
1,044 kata
Chapter 6: Menatap Lama
1,346 kata
Chapter 7: Bayangan Tersembunyi
1,269 kata
Komentar Chapter (0)
Login untuk memberikan komentar
LoginBelum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan komentar!