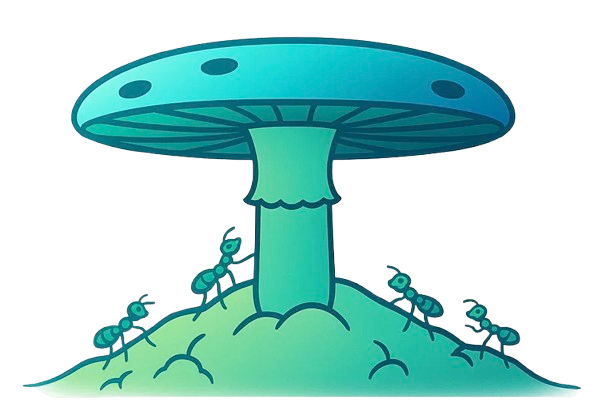Chapter 2: Jeonsa – Pagi yang Setengah Dingin
Jeonsa pagi itu berwarna abu-abu pucat.
Langit diguyur kabut tipis, dan matahari enggan menembus celah gedung-gedung kecil yang berjajar seperti papan catur. Jongdae menyukai pagi yang seperti ini—sepi, tanpa suara yang memburu. Seolah dunia memberinya jeda untuk bernapas, meski hanya sebentar.
Dalbit Coffee belum ramai.
Udara dalam ruangan masih menguarkan aroma sisa sangrai semalam, dan mesin espresso belum benar-benar panas. Jongdae berdiri di balik meja bar, jari-jarinya sibuk merapikan cangkir sambil menunggu ketel mendidih. Tangan kanannya bergerak otomatis, sementara kepalanya melayang entah ke mana. Di luar, daun-daun kering terseret angin. Musim semi belum seutuhnya tiba. Beberapa bunga magnolia sudah muncul, tapi udara masih membawa jejak musim dingin yang keras kepala.
Bel pintu berdenting lembut.
Masuklah pelanggan pertama hari itu—lelaki paruh baya berjaket kain wool, dengan kantung mata seperti luka yang tak kunjung sembuh. Tanpa perlu berbicara, Jongdae sudah tahu: Americano panas, sedikit madu. Sama seperti kemarin. Dan kemarin dulu.
"Silakan duduk, Pak," ucap Jongdae lirih, hampir seperti gumaman. "Kopi akan segera datang."
Lelaki itu mengangguk, lalu duduk di bangku dekat jendela. Tatapannya menembus kaca, tapi tak melihat apa-apa. Jongdae paham perasaan itu. Ia juga sering menatap kosong seperti itu, seakan berharap jawaban dari dunia yang tak bicara.
Tak lama, pelanggan kedua datang.
Seorang perempuan dengan kemeja putih dan coat abu yang selalu terlihat terlalu besar untuk tubuhnya. Rambutnya dikuncir asal, dan matanya sayu meski bibirnya tersenyum.
“Pagi,” katanya pelan.
Jongdae membalas senyum kecilnya.
“Earl Grey panas dan banana scone, ya?” Ia mengangguk, menunduk sedikit malu. “Kau hafal, seperti biasa.”
“Aku punya ingatan yang cukup baik… untuk hal-hal tertentu,” jawab Jongdae, kali ini dengan senyum yang tak sampai ke mata.
Perempuan itu tertawa kecil. Lelah, tapi tulus.
Dalbit perlahan hidup. Bunyi uap dari mesin espresso, denting sendok bertemu porselen, dan suara bisik-bisik pelanggan yang datang satu per satu. Tapi di dalam kepala Jongdae, pagi itu tetap sunyi. Setiap pagi terasa seperti deja vu. Ia tahu urutan waktunya, tapi tidak tahu ke mana semuanya akan menuju. Sambil menyusun gelas bersih di rak, pikirannya kembali mengembara.
Pada Seowon.
Pada Jo Anna.
Pada dirinya sendiri yang semakin tak bisa dibaca.
Dan di sela semua itu, ia bertanya dalam hati—Apakah seseorang akan benar-benar melihatku hari ini?
Americano panas untuk lelaki kantoran telah selesai disajikan. Scone pisang dan teh untuk perempuan bercoat abu juga sudah mendarat di meja langganannya. Dalbit mulai hangat oleh percakapan kecil dan aroma kopi yang menebal di udara.
Jongdae menyeka tangan dengan lap bersih saat seorang perempuan menghampiri konter. Si pelanggan dengan coat abu yang selalu duduk di pojok dekat rak buku mini.
“Jongdae-ssi,” panggilnya, lembut. “Boleh minta tisu tambahan?”
“Sebentar ya.” Ia mengambil satu set dan menyerahkannya.
“Kamu terlihat lebih lelah dari biasanya,” kata perempuan itu sambil memperhatikan wajahnya. “Kurang tidur?”
Jongdae hanya mengangkat bahu kecil. “Ada banyak hal yang butuh dipikirkan.”
Perempuan itu tersenyum kecil, dan kali ini lebih hangat. “Pikirkan perlahan. Hidup nggak sedang berlomba.”
Jongdae menunduk sedikit, mengucapkan terima kasih. Dan di saat yang sama, pintu belakang terbuka.
Langkah berat dan ritmis terdengar menyusuri lantai kayu Dalbit.
“Aku kira kamu udah bikin es kopi buatku.” Suara serak itu menghentikan sejenak suasana.
Han Yuri.
Perempuan dengan mata biru kelam seperti malam yang dalam. Rambut hitamnya diikat tinggi, bibirnya mungil tapi nada suaranya selalu terdengar seperti peringatan. Dia datang dengan hoodie oversize dan celana kuliah yang belum sempat digosok. Tangannya membawa satu bungkus rokok yang belum dibuka.
“Kamu datangnya pagi-pagi, tapi muka kayak baru tidur lima menit.” Ia melemparkan celetukan pada Jongdae sambil meletakkan tasnya di bawah rak bar.
“Aku bangun jam lima,” jawab Jongdae, membuka kulkas dan meraih botol susu dingin. “Dan kamu masih utang ngajarin aku latte art bentuk hati.”
Han Yuri mengerutkan kening, pura-pura marah. “Siapa yang ngajarin kamu bikin foam espresso sampai nggak pecah, hah?”
“Dan siapa yang bilang foam aku kayak sabun cuci tangan?”
Mereka tertawa kecil—tawa tipis yang tak pernah benar-benar lepas, tapi cukup untuk membuat pagi itu terasa sedikit lebih ringan.
Han Yuri berdiri di samping Jongdae, matanya mengawasi setiap gerakan tangannya saat Jongdae membuat cappuccino.
“Putar cangkirnya pelan, tanganmu kaku. Kamu ini barista, bukan petarung.” Jongdae menghela napas dan mencoba ulang.
“Begitu. Nah, gitu. Baru kamu pantas pakai apron Dalbit.”
“Harusnya aku dapat pin kehormatan,” canda Jongdae.
Yuri menyalakan rokok di area dapur belakang, meski dia tahu itu dilarang. “Kamu dapat bonus dari Ibu pemilik aja udah beruntung.”
Jongdae menoleh ke arah dapur, lalu berseru, “Eomoni! Yuri noona merokok lagi di dalam!”
Terdengar suara tertawa dari dapur. “Biarkan dia, kalau nggak ngerokok nanti dia marah-marah terus.”
Yuri melirik Jongdae tajam, tapi senyumnya muncul di sudut bibir. “Dasar anak bawel.”
Di tengah gurauan itu, Dalbit terus berjalan. Mesin espresso berdengung, bunyi cangkir dan piring bersahutan, dan dunia kecil di kafe itu seolah punya waktunya sendiri. Jongdae tak merasa tenang, tapi bersama Yuri dan pelanggan-pelanggan yang perlahan dikenalnya, ia merasa tidak sendirian.
Langit mendung di luar jendela Dalbit tampak seperti kanvas kelabu yang belum selesai dilukis. Udara di dalam kedai bercampur aroma kayu basah, pastry hangat, dan kopi yang baru digiling. Jongdae berdiri di balik meja bar, melipat tangannya sambil memperhatikan seorang pria tua yang berdiri kikuk di depan mesin kasir.
Laki-laki itu mengenakan jas kusam dengan kancing atas yang longgar. Wajahnya penuh kerut, matanya menyipit seperti sedang mencari sesuatu—mungkin nama kopi yang akrab, atau mungkin sekadar keberanian untuk memesan. Tangannya yang gemetar mengusap pelan kantong celana, seperti ingin memastikan dompet masih ada di sana.
"Silakan, Pak," ujar Jongdae lembut.
Pria itu tidak langsung menjawab. Ia mendekat sedikit, menunduk ke arah papan menu, lalu melirik Jongdae… dan kemudian menoleh pada Yuri yang sedang menata pastry di etalase kaca. Sekilas, matanya berhenti lebih lama di sana. Jongdae, yang mengamati diam-diam, merasa napasnya sedikit menahan.
Ada sesuatu yang janggal. Bukan dalam cara pria tua itu bergerak, tapi dalam caranya memperhatikan. Seolah-olah ia mengenali Yuri. Atau sedang menyimpan sesuatu. Tapi Jongdae tak bisa menebak pasti.
"Ada… Americano?" suara itu akhirnya keluar. Parau dan bergetar.
"Ada, Pak. Mau yang panas atau dingin?"
Lagi-lagi, jeda panjang. Pria itu menoleh ke arah jendela, lalu ke Yuri, sebelum kembali ke Jongdae. “Panas saja…”
Jongdae mengangguk pelan dan mulai menyiapkan pesanan. Di sudut lain, Yuri sempat menatap sebentar dengan pandangan tak sabar, tapi kembali sibuk dengan baki kue. Ia tidak menyadari pandangan si pria, tak menyadari keganjilan yang pelan-pelan mengusik Jongdae.
Saat kopi selesai, pria itu menyerahkan beberapa lembar uang, tangan bergetar tapi mata masih tetap—menyimpan sesuatu yang tidak dikatakan.
"Ini kembaliannya, Pak."
"Simpan saja… untuk kamu," katanya cepat, lalu meraih gelas kopi dan pergi seperti angin lewat celah pintu.
Jongdae menatap sisa uang di tangannya. Tidak banyak, tapi cukup untuk membeli dua gelas kopi lagi. Tangannya mengepal refleks, lalu membuka perlahan. Suasana Dalbit kembali tenang, hanya tersisa suara musik instrumental dan denting sendok dari arah meja.
Ia tidak tahu siapa pria itu, tapi ada sesuatu yang tertinggal. Bukan hanya aroma kopinya, tapi tatapannya. Pada Yuri. Dan pada dirinya.
Dan Jongdae tahu… ia akan memikirkan hal ini sampai malam nanti.
“Orang tadi aneh,” gumam Yuri sambil meletakkan baki pastry ke rak pendingin. “Sepuluh menit cuma buat milih kopi. Serius.”
Jongdae melirik sekilas ke arah pintu yang baru saja tertutup. Hujan mulai turun gerimis, memburamkan kaca depan Dalbit.
“Dia ngelihatin kamu terus,” bisiknya pelan.
Yuri menghentikan gerakannya. Tangannya masih memegang lap basah, tapi matanya mengarah ke luar jendela.
“Yang mana?” tanyanya, suaranya sedikit mengecil.
“Yang tadi. Americano panas. Duduknya tadi di kursi pojok. Jasnya abu-abu.”
Yuri menoleh perlahan, matanya menyipit ke arah tempat yang dimaksud Jongdae. Tak ada siapa-siapa lagi di sana, hanya jejak embun di kursi dan cangkir kopi yang tertinggal setengah kosong di meja.
Seketika, wajah Yuri berubah. Ia diam, lama, seolah waktu menahan napas. Tatapannya kosong, tapi pikirannya tidak. Jongdae tahu ekspresi itu—bukan terkejut, bukan takut, tapi seperti sedang menggali kenangan yang belum siap muncul ke permukaan.
“Yuri?” panggil Jongdae, tapi tak ada respons. Ia masih memandangi sisa kursi kosong itu, dengan wajah tak terbaca.
Baru saat lonceng di atas pintu berdenting, Yuri tersentak.
“Permisi~!” suara ceria menyela keheningan.
Seorang wanita bertubuh kecil dengan payung basah melangkah masuk, diikuti oleh seorang anak laki-laki sekitar tujuh tahun yang mengenakan jaket kuning. Rambutnya sedikit berantakan, dan matanya langsung menyala ketika melihat Jongdae.
“Oppa! Cokelat panas dua!”
Jongdae tersenyum, “Satu pakai marshmallow, satu tidak?”
Anak itu mengangguk cepat seperti anak ayam, “Iya! Yang pakai buat aku!”
Yuri, yang sudah kembali ke dirinya, menghela napas kecil. “Tiap sore ya pelanggan ini, kayak jam kerja.”
Wanita yang membawa anak itu tersenyum malu. “Maaf, anak saya nggak bisa tenang sebelum ke sini.”
“Santai, Bu. Justru dia yang bikin Dalbit hangat tiap sore,” kata Yuri dengan senyum tipis yang sulit ditebak, sambil mulai menyiapkan gelas cokelat panas.
Tapi Jongdae, diam-diam, masih memandangi Yuri. Ada sesuatu di balik tatapan kosong tadi. Sesuatu yang belum selesai. Ia tahu, cepat atau lambat, akan muncul kembali dan ketika pelanggan itu tertawa dan tawa anak kecil memenuhi Dalbit, aroma manis cokelat panas justru membuat Jongdae semakin yakin—keheningan Yuri tadi, bukan keheningan biasa.
Lampu utama Dalbit telah diredupkan, menyisakan cahaya lembut dari sudut-sudut dinding dan neon kecil di rak pastry. Di luar, hujan belum berhenti sepenuhnya. Jalanan sudah mulai sepi, hanya sesekali suara mobil melintas memantul di jendela basah.
Jongdae sedang menggulung kabel mesin kopi saat Yuri mematikan lampu kulkas. Mereka terbiasa tidak banyak bicara saat closing—semuanya sudah seperti ritme yang dihafal tubuh. Tapi malam ini ada sesuatu yang tertinggal di udara.
“Yuri,” kata Jongdae akhirnya, pelan, tanpa menoleh.
“Hmm?”
Jongdae mengambil kain lap, menyeka bagian bawah meja kasir. “Tadi kamu diam. Waktu aku bilang soal pria tua itu.”
Yuri tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri di belakang bar, merapikan gelas yang sudah kering. Suara keramik saling beradu terdengar lebih nyaring di tengah kesunyian.
“Kamu kenal dia, ya?” lanjut Jongdae.
Yuri diam beberapa detik. Lalu akhirnya bicara. “Nggak yakin.”
Jongdae berdiri tegak, memandangi Yuri yang kini sibuk menata kembali toples gula dan sirup. “Tapi kamu sempat bengong lama. Aku lihat.”
Yuri tersenyum kecil—senyum itu tidak seperti biasanya. “Kadang orang asing mirip sama kenangan. Mungkin aku cuma salah kira.”
Terdengar bunyi pintu kulkas ditutup perlahan. Jongdae masih diam, tapi matanya mengikuti setiap gerakan Yuri. Ia tahu perempuan itu bukan tipe yang mudah bercerita. Tapi malam ini, ada getaran samar yang membuatnya ingin tahu lebih.
“Aku rasa dia bukan pelanggan biasa,” gumam Jongdae, hampir tidak terdengar.
Yuri menoleh, matanya sedikit teduh dalam remang cahaya. “Kalau dia datang lagi, baru kita lihat. Mungkin kau benar. Atau mungkin aku cuma lelah.”
Ia mengambil rokok dari saku celemeknya dan berjalan ke pintu belakang.
“Kau ikut?” tanyanya singkat.
Jongdae menggeleng, lalu tersenyum. “Aku bersihin rak dulu. Nanti nyusul.”
Yuri hanya mengangkat alis, lalu membuka pintu. Udara malam langsung masuk, dingin dan berembun. Aroma rokok segera mengambang, bercampur dengan sisa wangi kopi yang belum benar-benar menguap dari ruangan. Jongdae menyeka meja terakhir, lalu berdiri sejenak memandangi tempat pria tua tadi duduk. Bangku itu kosong. Tapi di dalam kepala Jongdae, ada suara yang belum selesai.
Halaman belakang Dalbit hanya seluas satu mobil, dengan tembok bata yang sebagian mulai ditumbuhi lumut. Sebuah bangku kayu usang menempel di dinding, dan sebuah lampu gantung tua menggantung setengah mati, cahayanya bergetar pelan diterpa angin malam. Yuri duduk di sana, kaki bersilang, rokok menyala di tangan kanan, asapnya mengambang malas ke udara. Suara gerimis kecil masih terdengar jatuh ke atap seng di sudut gudang.
Jongdae menyusul beberapa menit kemudian, membawa dua cangkir kecil kopi sisa. Ia duduk di samping Yuri, tanpa berkata-kata. Cangkir disodorkan. Yuri menerima tanpa terima kasih, hanya satu anggukan pelan. Mereka sudah terlalu sering berbagi malam seperti ini untuk butuh basa-basi.
“Pria tadi...” Jongdae mulai, pelan. “Kamu yakin kamu nggak tahu?”
Yuri menghembuskan asap perlahan, lalu menjawab tanpa menoleh. “Aku pernah lihat wajah kayak gitu. Tapi aku nggak tahu dari mana.”
“Kamu kelihatan takut.”
Yuri tertawa kecil, pahit. “Bukan takut. Cuma... waspada.”
Jongdae mengangguk, mencicip kopi yang mulai dingin. Mereka diam beberapa saat.
“Kamu selalu waspada, ya,” gumamnya. “Aku nggak pernah lihat kamu benar-benar tenang.”
Yuri tersenyum di balik cangkirnya. “Tenang itu mahal. Apalagi buat orang yang harus selamat dari hidupnya.”
Ucapannya menggantung. Jongdae memandangi gadis itu lama-lama, matanya mengikuti garis rahang yang tegas, mata biru kelam yang tampak tak tergoyahkan. Tapi dari dekat, ada letih yang tak bisa disembunyikan.
“Kalau suatu hari kamu mau cerita,” kata Jongdae, “aku bisa dengar. Aku nggak jamin bisa bantu, tapi aku bisa dengar.”
Yuri menatapnya, hanya sesaat. Senyumnya sedikit lembut.
“Kalau aku cerita, kamu mungkin nggak bakal bisa tidur.”
“Aku juga sering nggak tidur,” jawab Jongdae pelan, lalu menenggak sisa kopi.
Hening kembali menyelimuti mereka, tapi kali ini lebih ringan. Bukan karena pertanyaan sudah terjawab, tapi karena dua manusia yang sama-sama menyimpan dunia dalam diam, berbagi sedikit ruang untuk saling duduk tanpa takut.
Di atas sana, langit mendung menutup bintang, tapi ada satu cahaya dari jendela Dalbit yang masih menyala, menyinari dua bayangan yang tampak kecil namun saling menguatkan.
Suara baki beradu dengan meja. Kantin siang itu lebih riuh dari biasanya. Murid-murid memenuhi bangku, suara obrolan saling tumpang tindih, dan aroma makanan mengambang samar di udara. Jongdae berdiri di antrean, sendirian, mengucek pelan mata lelahnya. Tangannya otomatis meraih botol jus jeruk dingin dari deretan lemari pendingin di sudut kantin. Begitu juga tangan di sebelahnya.
Sebuah sentuhan ringan. Jari-jarinya bertemu dengan jari lain, dingin dan halus. Sekilas saja, tapi cukup membuat dada Jongdae menegang.
“Ah, maaf,” ucap suara itu. Ringan dan biasa saja. Bukan malu, bukan juga canggung. Seperti berbicara kepada orang asing.
Jo Anna.
Gadis itu menarik tangannya lebih dulu, mengambil botol jus dan tersenyum kecil tanpa menatap terlalu lama. Lalu pergi begitu saja, menyusuri lorong meja yang ramai, langkahnya ringan, nyaris tak menyentuh lantai. Jongdae menatap punggungnya. Ada sesuatu yang bergetar di perutnya, seperti rasa kecut dari buah yang belum matang.
Ia membuka tutup jusnya dan meminum seteguk. Dingin. Asam. Tapi bukan hanya karena jeruk.
Matanya mencari tempat duduk. Ia melihat Kinam tertawa keras di ujung meja bersama teman sekelas lain. Ia bisa saja bergabung. Tapi tidak kali ini.
Jongdae memilih duduk sendiri, di meja dekat jendela, masih memegang jus jeruk yang belum habis. Pandangannya kosong ke luar—ke pohon-pohon kecil yang tertiup angin, ke langit yang sudah mulai redup, padahal belum sore.
Ada yang berdenyut pelan di dadanya. Rasanya seperti ketidakpastian, seperti pertanyaan yang tak kunjung mendapat jawaban. Seperti ingin bicara, tapi tak tahu kepada siapa. Satu tangan menahan dahinya. Dalam diam, Jongdae bertanya pada dirinya sendiri:
Apakah aku jatuh cinta? Atau hanya sedang kesepian?
Dan ia tahu, tidak akan ada yang bisa menjawab pertanyaan itu hari ini.
“Sendirian?”
Suara itu datang dari samping, akrab dan pelan, disertai suara baki ditaruh dengan lembut ke meja. Jongdae menoleh. Kinam sudah duduk di sebelahnya, membawa seporsi nasi bulgogi dan sebotol air mineral.
“Iya. Lagi males ramai-ramai,” jawab Jongdae, suaranya datar, tapi tidak menolak keberadaan Kinam.
Kinam hanya mengangguk pelan. Ia tidak bertanya lebih jauh. Begitulah Kinam: tidak banyak bicara, tapi selalu hadir di waktu yang tepat. Ia mulai makan dalam diam. Jongdae menyesap jus jeruknya lagi, rasanya sudah berubah. Tak lagi sedingin tadi. Beberapa menit berlalu tanpa percakapan. Hanya suara kantin yang riuh di latar belakang. Sampai akhirnya Kinam bersuara, setengah gumaman.
“Moon Jangmi balikan ngobrol lagi sama aku.”
Jongdae menoleh sekilas, lalu mengangguk. “Kapan?”
“Kemarin. Aku nggak nyangka dia masih mau jawab chat-ku. Padahal terakhir kali kita ngobrol, dia marah banget.”
“Karena kau menciumnya tanpa permisi?” tanya Jongdae, datar.
Kinam mengangkat bahu. “Aku pikir waktu itu momen yang pas. Ternyata cuma aku yang merasa begitu.” Ia mengunyah perlahan, lalu menatap makanannya. “Dia bilang dia benci aku, tapi aku tahu Jangmi cuma nggak ngerti gimana cara jaga jarak yang aman. Orangnya keras, galak, tapi… cengeng banget waktu nangis.”
Jongdae mengulas senyum kecil. “Kau memang suka yang begitu.”
Kinam mendesah ringan. “Mungkin. Tapi aku juga capek. Rasanya kayak main tebak-tebakan terus. Hari ini boleh dekat, besok dimarahin. Tapi tetap aja... waktu dia balas ‘iya’ kemarin, aku senang banget.”
“‘Iya’ apa?”
“‘Iya, kita ngobrol lagi.’” Kinam mengangkat kepalanya, menatap Jongdae. “Kadang kita nggak butuh ‘aku suka kamu’ buat lega. Satu kata yang nyambung aja udah cukup.”
Jongdae menunduk. Suara Kinam tenggelam perlahan dalam keramaian kantin yang tak kunjung reda.
Tapi suara di kepalanya lebih keras.
Kalau satu kata bisa membuat lega… kenapa aku tidak bisa mengucapkannya?
Pada Seowon.
Atau pada Anna.
Atau bahkan pada diriku sendiri.
“Lagi mikirin Anna?” tanya Kinam tiba-tiba, tanpa menoleh.
Jongdae terdiam. Butuh waktu untuk menjawab. “Nggak juga,” katanya akhirnya. “Cuma... banyak pikiran aja.”
Kinam tidak membalas. Ia tahu, sahabatnya itu bukan tipe yang bisa ditekan untuk bicara. Jadi ia hanya diam, memakan sisa makanannya sambil sesekali mencuri pandang ke wajah Jongdae.
Wajah itu tenang. Terlalu tenang. Seperti danau yang menyembunyikan badai di dasar airnya.
Bunyi denting sendok, langkah-langkah berat menuju tempat pengembalian baki, suara pelan dari loudspeaker kantin—semuanya terdengar seperti gema jauh bagi Jongdae. Ia berdiri pelan dari kursi, mengembalikan baki tanpa bicara, hanya memberi isyarat mata kepada Kinam yang masih duduk. Kinam membalas dengan anggukan kecil, seolah berkata: Kalau kau butuh bicara, aku ada.
Jongdae melangkah keluar dari kantin. Langit Jeonsa siang itu agak mendung, tapi udara tetap hangat. Langkahnya membawa dia ke taman kecil di antara gedung kelas dan ruang guru. Tempat itu tak pernah ramai. Biasanya dipakai oleh siswa yang ingin belajar sendiri atau sekadar menenangkan diri. Tempat itu seperti dirinya—hadir tapi tak pernah benar-benar disadari.
Ia duduk di bangku kayu yang catnya mulai pudar. Dari saku dalam jaketnya, Jongdae mengeluarkan sebuah buku catatan kecil. Halamannya sudah lecek, sebagian kertasnya melengkung karena bekas keringat atau mungkin air kopi.
Jongdae membuka halaman tengah, membaca baris-baris kalimat yang pernah ia tulis:
"Kau seperti senja yang selalu datang,
dan aku selalu takut hari akan selesai."
Ia menatap kata-kata itu lama. Lalu menarik napas dan menulis lagi.
“Aku tak tahu siapa yang harus kugenggam.
Mereka sama-sama bukan milikku, tapi kenapa hatiku terbelah?”
Hening.
Ia menyandarkan kepala ke bangku. Burung gereja bertengger di pagar besi, berkicau pelan. Tapi di dalam kepala Jongdae, semua suara bercampur. Suara Seowon, lembut dan sabar. Suara Jo Anna yang jarang didengarnya langsung, tapi membekas dalam khayalannya. Lalu suara dirinya sendiri—lelah, bingung, dan… takut.
Takut kehilangan sesuatu yang tak pernah benar-benar ia miliki.
Takut menyakiti seseorang yang terlalu baik untuk dirinya.
Takut akan hari-hari yang terus berjalan tanpa kejelasan.
Ia membuka ponsel, melihat notifikasi. Tak ada pesan dari Seowon. Tidak juga dari Jo Anna. Ia menulis sebuah pesan, tapi tidak dikirimkan:
“Kau baik-baik saja, kan? Karena aku tidak…”
Ia hapus.
Menutup ponsel.
Menatap langit.
Dan membiarkan rasa asam dari jus jeruk siang tadi masih tertinggal di lidah.
Langit mulai meluruh, mencoretkan semburat oranye di ujung gedung sekolah saat Jongdae menuruni tangga dengan langkah malas. Tasnya bergelayut di satu bahu, dan pikirannya masih tertambat pada rasa asam dari jus di kantin siang tadi—juga rasa asam lain yang belum bisa ia uraikan. Ketika ia membelok di koridor menuju gerbang belakang, langkahnya terhenti.
Jo Anna.
Gadis itu berdiri sendirian di samping rak sepatu, seperti sedang menunggu seseorang, atau barangkali sekadar menimbang waktu. Seragamnya rapi, rambutnya diikat rendah, dan wajahnya sedikit tertekuk ke arah lantai. Namun Jongdae tahu itu bukan karena sedih—Jo Anna memang tidak terbiasa menatap orang terlalu lama. Terutama dirinya.
Ia tidak tahu apakah Jo Anna menyadari kehadirannya atau tidak, tapi saat matanya terangkat dan mereka saling menatap singkat, waktu seperti mencair di antara mereka. Jo Anna menyelipkan rambut ke belakang telinga, canggung. Jongdae mengusap tengkuknya.
“Jus jeruk tadi…” suara Jo Anna pelan, hampir tenggelam dalam suara angin.
Jongdae menoleh, alisnya terangkat sedikit.
“Aku mau tadi. Tapi kamu udah beliin buat Kinam.”
“Oh…” Jongdae mengangguk pelan, kaget gadis itu memperhatikan hal kecil seperti itu. “Kalau kamu bilang, aku beliin.”
Jo Anna menggigit bibir bawahnya, lalu menunduk. “Aku... nggak tahu gimana ngomongnya.”
Jongdae nyaris tersenyum, tapi tak jadi. Rasanya dadanya disesaki sesuatu yang samar. Gadis ini—pendek, pendiam, keras kepala, dan jago Taekwondo—selalu seperti kabut. Sulit dijangkau. Dan meskipun mereka pernah berbagi momen—seperti ketika ia menggendong Jo Anna ke UKS karena gadis itu pucat dan gemetar saat haid—mereka tetap terasa jauh. Terlalu jauh.
“Jo Anna...” suaranya menggantung. Ia ingin berkata lebih, tapi pikirannya seperti lumpuh.
Gadis itu mengangguk pelan. “Aku pulang duluan, ya.”
Jongdae hanya bisa menatap punggung mungil itu menjauh, langkahnya cepat seperti ingin segera hilang dari pandangan. Ada sesuatu dalam cara Jo Anna berjalan yang membuat dada Jongdae terasa nyeri.
Ia menatap tangannya yang kosong. Jus jeruk. Seharusnya ia bisa menebak. Seharusnya ia bisa peka. Tapi bahkan hal sekecil itu pun terlambat untuk dimengerti.
Di tengah padatnya halaman sekolah yang perlahan mulai sepi, Jongdae berdiri dalam diam, membiarkan punggungnya menyandar pada dinding yang mulai menghangat oleh sinar senja. Dari tempatnya berdiri, ia melihat Kinam—teman yang paling ia percaya—sedang bicara dengan Moon Jangmi di ujung lorong. Gadis itu tertawa kecil sambil mendorong bahu Kinam dengan buku, lalu menunduk cepat karena malu. Kinam menggaruk kepala, tersenyum dengan canggung khasnya.
Satu detik.
Lalu dua.
Hingga Jongdae menyadari bahwa mereka terlihat seperti dunia kecil yang sudah menemukan orbitnya sendiri.
Dan di tengah pemandangan itu, Jongdae merasa… kosong.
Bukan karena iri.
Tapi karena ia tidak tahu harus merasa apa.
Ia merasa seperti satu-satunya orang yang tidak mendapat undangan menuju tempat yang layak. Seperti satu-satunya nama yang terlewat ditulis dalam doa-doa yang diaminkan langit. Semua orang berjalan ke arah yang mereka pilih—sementara ia hanya diam, tidak tahu arah pulang.
Ia menarik napas panjang, berusaha memalingkan wajah sebelum terlalu dalam menatap sesuatu yang bukan miliknya. Lalu pandangannya menangkap gerombolan OSIS keluar dari ruang rapat. Langkah mereka cepat, sibuk, seperti biasa. Seowon ada di tengah-tengah mereka, membalas satu dua pertanyaan, sesekali tertawa ringan pada komentar anak kelas dua yang baru masuk kepengurusan. Rambutnya diikat rapi, name tag-nya tergantung sempurna di dada. Dalam sorot matanya ada ketegasan dan kelelahan sekaligus. Ia tidak melihat Jongdae.
Atau mungkin melihat tapi memilih tidak melihat.
Jongdae tidak tahu mana yang lebih menyakitkan.
Ia hanya berdiri, membatu, lalu cepat-cepat menunduk dan membenahi ransel yang sebenarnya tak perlu disentuh. Napasnya ia tahan. Ia tidak ingin menatap gadis itu terlalu lama. Takut mengganggu. Takut terbaca. Takut berharap sesuatu yang tidak bisa ia miliki hari itu. Tak ada kata yang diucapkan. Tak ada sapa. Seperti dua planet asing yang kebetulan lewat dalam satu garis edar, tapi tidak pernah menyentuh. Dan Jongdae tahu benar, ini bukan pertama kalinya mereka saling diam. Tapi mengapa rasanya selalu seperti terluka untuk pertama kalinya?
“Sudah sore,” gumamnya pada dirinya sendiri.
Ia melangkah pergi, keluar dari gerbang yang mulai lengang, melewati deretan pohon yang daunnya gugur satu-satu. Jalan menuju Dalbit seperti jalan pulang, tapi hari ini rasanya lebih seperti pelarian.
Kepalanya penuh. Dadanya sesak. Dan semua kata yang ingin ia ucapkan menggumpal di tenggorokan. Ia ingin berkata pada Seowon. Ia ingin menyapa Jo Anna. Ia ingin bercerita pada Kinam. Tapi tak satu pun berhasil keluar dari mulutnya. Seperti namanya sendiri yang terasa asing di lidahnya. Jongdae menarik napas. Lalu berjalan lebih cepat.
Dalbit menunggu.
Dan di balik pintu kacanya, mungkin ada kehangatan yang bisa sedikit menyembuhkan hari yang berisik di dalam dadanya.
Dalbit sore itu tetap dalam pendar cahaya lampu hangat yang memantul dari ubin dan kaca. Aroma kopi hari itu terasa lebih manis dari biasanya, berpadu dengan sedikit kayu manis dan kehangatan ruang yang sudah akrab dengan suara langkah pelanggan tetap. Namun bagi Jongdae, semuanya terdengar seperti gema yang jauh. Seolah dunia berada di balik kaca, samar dan sulit dijangkau.
Ia masuk dengan langkah pelan, mengangguk kecil pada Yuri yang sedang menyeduh espresso di balik bar. Gadis itu hanya melirik singkat lalu kembali fokus pada timbangan kopi dan dengungan mesin grinder yang memenuhi udara.
“Anak magang itu... nyaris menjatuhkan portafilter dua kali,” gumam Yuri sambil menghela napas. “Sudah dua minggu, tapi masih belum bisa membedakan house blend dan single origin. Aku hampir menyiramkan susu panas ke tangannya, tahu.”
Jongdae tersenyum kecil. Tapi hanya itu. Tak ada tawa ringan seperti biasanya. Tak ada komentar iseng untuk mengimbangi nada Yuri yang kesal.
Yuri mengerutkan alis. Tangannya masih sibuk mengelap sisi mesin saat ia melirik ke arah Jongdae. “Kamu dengar, kan?”
Jongdae berdiri diam di depan rak apron, mencoba mengenakannya dengan terburu-buru. Tapi tali belakangnya terasa aneh, dan saat ia mencoba membetulkan posisi, Yuri yang akhirnya menoleh langsung melangkah mendekat.
“Jongdae,” panggilnya lembut. “Kamu pakai apron-nya terbalik.”
Jongdae menunduk. Tangannya berhenti, lalu pelan-pelan membenarkan posisinya.
Yuri menyilangkan tangan, bersandar ringan ke meja. Sorot matanya tak lagi terlihat kesal—lebih lembut, nyaris cemas. “Kamu tidak apa-apa?”
Tak ada jawaban.
Hanya helaan napas panjang yang terdengar seperti suara kecil dari dalam dirinya yang lelah. Jongdae tidak menatapnya. Ia hanya bergerak perlahan ke meja bar, membuka rak pastry, dan mulai menyusun kue-kue. Tangannya menggenggam nampan, tapi tidak secekatan biasanya. Ia menata croissant dan roti kayu manis seperti sedang mengikuti pola hafalan—rapi, namun hampa.
Yuri mengalihkan pandang ke jendela. Beberapa pelanggan mulai masuk. Ia mendekat dan mengambil alih dengan cepat.
Pelanggan pertama dan kedua mereka layani tanpa kendala. Namun saat pelanggan ketiga mulai bertanya tentang biji kopi yang digunakan, Jongdae menjawab dengan pelan—salah pula menyebutkan jenis roasting.
Yuri segera menyela dengan tenang. “Biar aku saja.”
Nada suaranya tidak tinggi. Hanya ada ketegasan dan sedikit isyarat untuk membiarkan dirinya yang menangani.
“Kamu bantu aku susun pastry saja, ya? Kasih taburan gula bubuk, dan ambil box dari storage.”
Jongdae mengangguk kecil. Matanya tampak kosong, seolah-olah ia berada di tempat lain.
Yuri memperhatikannya dari ujung matanya.
Ada yang tidak biasa.
Bukan hanya soal apron atau kesalahan menyebut kopi. Tapi cara Jongdae berjalan, cara ia merespons. Cara ia diam.
Yuri bukan seseorang yang pandai mengungkapkan kekhawatiran dengan kata-kata. Tapi ia cukup peka terhadap perubahan kecil di orang-orang yang ada di sekitarnya setiap hari. Jongdae memang tidak banyak bicara, tapi biasanya ia hadir. Selalu sigap, penuh perhatian, dan sesekali menyelipkan tawa pendek yang menyebalkan. Tapi hari ini, ia seperti tenggelam. Senyumnya tipis dan cepat pudar. Matanya tidak menyala seperti biasanya.
Yuri merapikan cup kopi ke atas nampan, lalu sebelum kembali ke bar, ia menatap Jongdae sebentar. Diam-diam, dalam jeda waktu yang nyaris tidak terlihat.
Ia ingin bertanya lagi. Tapi entah mengapa, ia memilih diam.
Dan sore itu di Dalbit, suara mesin kopi dan percikan susu tetap terdengar seperti biasa. Tapi bagi Yuri, ada sesuatu yang hilang dari irama ruang ini. Dan itu datang dari seseorang yang biasanya paling tenang dalam kesibukan.
Langit Jeonsa meredup pelan-pelan, seperti kelopak mata yang tak sanggup lagi menahan kantuk. Sisa sinar matahari membias di jendela-jendela toko, menyapu aspal yang mulai basah oleh embun petang. Udara sore itu terasa lembap, menyimpan sisa hangat siang yang melelahkan. Jalanan ramai, tetapi tak riuh. Suara langkah kaki berpadu dengan bisikan klakson dari kejauhan, dan wangi tipis daun yang luruh dari pohon-pohon kecil di sepanjang trotoar seperti mengiringi Jongdae yang berjalan sambil menunduk.
Hari ini kacau. Itu satu-satunya kata yang terulang di benaknya seperti rekaman rusak.
Tadi siang ia salah menyusun pastry di etalase, membuat croissant pisang dan kue kismis tertukar tempat. Saat mencuci gelas, ia melamun begitu dalam hingga hampir menjatuhkan cangkir keramik ke lantai. Dan yang paling memalukan, ia menjatuhkan seluruh set alat makan saat mengelap meja, membuat pelanggan di sudut kanan Dalbit menoleh serempak. Yuri, yang awalnya marah, akhirnya hanya terdiam. Tatapan gadis itu menelisik, seolah ingin menyelam masuk ke kepala Jongdae dan mencari tahu isi kepalanya yang kusut.
“Kamu nggak apa-apa, Jongdae?” suara serak khas Yuri terdengar lebih tenang hari ini. Ia menatap Jongdae dengan alis mengernyit.
“Maaf. Aku—cuma kurang tidur,” jawab Jongdae pelan, tidak menatap Yuri.
Yuri tidak menjawab. Ia hanya menatap punggung Jongdae yang terus bekerja, lalu menarik napas pelan. Tak lama kemudian, Jongdae meminta izin untuk menyelesaikan shift lebih awal. Yuri tidak banyak bertanya, hanya mengangguk dan memberitahu pemilik Dalbit. Jongdae kemudian keluar dengan langkah berat, menanggalkan apron dan menggantinya dengan seragam hitam khas Chenchun Dak.
Restoran ayam goreng itu terletak dua blok dari Dalbit Coffee. Saat Jongdae sampai, udara mulai menggigit. Angin berembus kecil membawa wangi adonan dan minyak goreng yang keluar dari ventilasi dapur restoran. Lampu neon restoran menyala terang, memantulkan bayangan di aspal basah. Di luar, ada dua-tiga pengunjung yang sedang merokok sambil menunggu pesanan dibungkus. Suara tawa pelan dan dering bel pintu terdengar berselang-seling.
Di dalam, ruangan terasa hangat dan padat. Bau ayam goreng dan saus manis pedas memenuhi udara. Suara spatula bersentuhan dengan wajan, langkah tergesa pegawai, dan deru kipas dapur menciptakan suasana sibuk yang sedikit menyesakkan.
Jongdae mengganti sepatu kerjanya di ruang belakang dengan gerakan lambat, lalu langsung masuk ke area dapur kecil di sebelah kasir. Di sana, ia melihat Areum berdiri memunggungi dapur, tubuhnya gemetar halus. Jongdae memperhatikan mata gadis itu yang sembab, merah, dan jelas-jelas baru saja menangis.
Honyun berdiri di dekatnya, tangan bertolak pinggang, menyusun ulang orderan sambil mengomel pelan pada dirinya sendiri. Ia tampaknya tidak puas dengan kecepatan Areum membersihkan meja makan. Padahal restoran sedang padat. Jongdae tahu, Areum bekerja keras, hanya saja kadang jiwanya terlalu rapuh untuk disemprot terus-menerus.
Jongdae berjalan pelan menghampiri keduanya. Ia tidak suka terlibat dalam drama remeh seperti ini, tetapi melihat mata Areum yang tidak sanggup menatap siapa pun membuatnya tidak bisa diam.
“Kamu nggak harus bentak dia seperti itu,” ucap Jongdae datar, menatap Honyun yang lebih tinggi darinya beberapa senti.
Honyun menoleh, matanya menyipit. “Aku nggak bentak. Aku cuma bilang dia lambat.”
“Tapi kamu tahu dia nangis,” Jongdae menekankan suaranya pelan, tapi mantap.
Hening beberapa detik. Areum menunduk, memegangi nampan kosong di tangannya. Honyun mendengus, melengos, lalu berjalan ke arah meja lain sambil menggerutu, “Terserah kalian, deh.”
Jongdae hanya menatap punggungnya, tidak ingin memperpanjang. Ia menoleh pada Areum, dan gadis itu berusaha tersenyum meski wajahnya kaku. Jongdae tidak bilang apa-apa, hanya mengambil celemek kerjanya dan mulai menyusun orderan ayam goreng yang harus diantar ke meja empat.
Saat itu, hatinya masih terasa berat. Ada bayangan wajah Seowon yang melintas sekilas. Lalu wajah Jo Anna. Lalu Yuri. Dan kini, Areum yang memaksakan senyum agar tidak dianggap lemah. Semua orang di sekitarnya tampak menyimpan perang sendiri-sendiri.
Sementara ia, merasa menjadi satu-satunya yang tidak tahu harus berperang melawan siapa.
Bel belakang restoran hanya dibatasi pintu logam tua yang mengarah ke gang sempit berlantai semen kasar. Di sana, udara lebih tenang. Tidak ada bunyi wajan atau piring beradu, hanya suara sepatu-sepatu pejalan kaki dari jalan besar yang terdengar sayup. Cahaya sore mengalir turun dari celah sempit antara bangunan, menyinari dinding kusam dan tanaman liar yang tumbuh liar dari retakan.
Jongdae duduk di tangga besi yang mengarah ke gudang kecil, sebuah kotak kardus terbalik ia jadikan alas. Ia mengeluarkan sebuah pastry dari kantong plastik Dalbit—croissant cokelat yang tadi pagi belum sempat disusun dengan rapi. Kini bentuknya agak peyok, tapi masih layak disantap. Ia menyodorkannya pada Areum, yang duduk diam di sisi kirinya, punggung bersandar pada dinding dingin.
“Ambil. Makan sedikit, kamu gemetaran,” ujar Jongdae pelan, tanpa banyak basa-basi.
Areum menoleh ragu, matanya sembab dan masih menyisakan bekas air mata yang belum kering sepenuhnya. Tangan gadis itu menggigil sedikit saat menerima pastry itu.
“Aku... belum makan dari pagi,” katanya lirih, matanya tetap menunduk. Ia tidak menyentuh makanan itu, hanya memegangnya erat seperti sesuatu yang rapuh.
Jongdae tidak kaget. Ia tahu, Areum sering melewatkan makan saat sedang cemas. Ia juga tahu, Areum jarang cerita soal hal-hal yang membuatnya sakit hati. Sejak dulu, gadis itu terlalu pandai menyembunyikan luka.
“Dia maki kamu lagi tadi, ya?” Jongdae bertanya, tak memaksa, hanya menebak.
Areum menggeleng cepat. “Nggak, cuma... Aku lambat, katanya. Salah bersihin meja.”
“Dia juga pernah bilang kamu bodoh, waktu kamu tumpahin saus,” kata Jongdae, suaranya tetap tenang.
Areum diam. Tidak membenarkan, tidak menyangkal. Tapi tangannya yang menggenggam pastry mulai bergetar lagi.
Dari dalam restoran, suara Honyun terdengar menggema sampai ke belakang. Kali ini ia sedang memarahi seorang pelayan muda karena salah catat pesanan. Nada suaranya tinggi, memecah sore yang tadinya hampir damai. Jongdae menutup mata sejenak, menghela napas panjang.
“Dia nggak pernah bisa bicara baik-baik, ya,” gumamnya, tidak marah, hanya lelah.
Areum menggigit bibirnya. Ia mencoba tetap kuat, tapi tubuhnya pelan-pelan terguncang kecil. Air matanya jatuh begitu saja tanpa suara, menetes satu per satu ke atas sepatu kerja yang sudah dekil. Tangannya yang bebas mengepal di pangkuan.
Jongdae menoleh. Tidak banyak yang bisa ia lakukan, tapi ia tahu Areum tidak butuh ceramah atau motivasi hari ini. Jadi ia hanya duduk lebih dekat, membiarkan jarak di antara mereka menyempit, menawarkan kehadiran diam-diam yang tidak menghakimi.
“Aku tahu rasanya dimaki,” katanya pelan. “Nggak bikin kamu buruk.”
Areum terisak kecil, menahan suaranya sebaik mungkin. Ia menyeka air mata dengan punggung tangannya dan akhirnya menggigit croissant itu sedikit, meski lidahnya terasa mati rasa.
Di dalam, suara Honyun masih terdengar samar. Tapi di belakang restoran, waktu seperti melambat. Jongdae dan Areum duduk berdampingan, sama-sama diam, sama-sama bertahan. Angin sore menyapu rambut Areum yang basah oleh peluh, dan Jongdae, tanpa sadar, memejamkan mata sejenak.
Ia tahu, hari ini belum usai. Tapi paling tidak, mereka punya jeda. Sekecil apapun, tetap bernilai.
Ketika Jongdae kembali masuk dari pintu belakang, udara hangat penuh uap bumbu langsung menyambutnya. Aroma bawang putih yang ditumis dengan minyak wijen, kecap asin, dan kaldu ayam memenuhi ruang dapur. Suara spatula menghantam wajan besar terdengar bersahutan, dan pelayan lalu-lalang membawa nampan berat berisi ayam goreng panas dan kimchi dingin yang menggoda.
Ia menggulung lengan kemejanya, membasuh tangan, lalu mengenakan apron kerja yang tergantung di paku tua dekat pintu dapur. Masih ada waktu lima menit sebelum shift resminya dimulai, tapi Jongdae tidak bisa berdiri diam saat meja-meja penuh dan suara lonceng dapur berdenting terus-menerus memanggil.
Di ruang makan depan, pelanggan memenuhi setiap sudut. Beberapa bersuara keras, beberapa hanya berbicara pelan sambil sesekali tertawa. Di salah satu meja dekat jendela, dua remaja perempuan tampak sibuk memotret ayam goreng mereka, sementara pasangan paruh baya tampak sabar menunggu minuman datang.
Cuaca di luar sudah berubah menjadi senja pucat. Matahari tertutup awan tipis, menyisakan cahaya kuning redup yang membuat jendela restoran tampak buram dari embun. Di jalanan, mobil-mobil berlalu dalam ritme lambat, klakson sesekali terdengar samar.
Di dapur, Honyun masih berdiri dengan tangan menyilang, mengawasi semua dengan pandangan tajam. Sesekali ia menyentak pada salah satu pelayan—seorang pemuda baru—karena membawa piring tanpa nampan, atau mengatur urutan pesanan dengan keliru. Areum sendiri sudah kembali ke posnya, wajahnya masih terlihat lelah, tapi ia bekerja dalam diam, menata lauk dan mencatat pesanan dengan tangan yang sedikit gemetar.
“Jongdae! Lantai dua minta refill banchan!” seru Honyun dari dekat pintu dapur, nada suaranya tak pernah terdengar ramah.
Jongdae hanya mengangguk. Ia mengambil mangkuk kecil berisi acar lobak, kimchi, dan salad kentang, lalu naik tangga sempit menuju lantai atas. Setiap langkah terasa berat, tapi pikirannya tak sempat merenung. Ia harus bergerak, harus cepat, harus tetap berpura-pura semuanya baik-baik saja.
Di sepanjang malam itu, Jongdae bekerja tanpa banyak bicara. Tubuhnya bergerak otomatis: mengantarkan pesanan, membersihkan meja, menenangkan pelanggan yang mengeluh karena pesanan terlambat. Tapi pikirannya—pikirannya masih tersangkut di percakapan pendek dengan Areum, di suara Honyun yang memotong ruang udara seperti pisau, dan di sisa lelah yang ia bawa dari pagi di Dalbit.
Sesekali ia menatap Areum dari jauh. Gadis itu bekerja dengan keras, tapi ia tahu Areum belum benar-benar pulih dari tangisannya. Dan ketika Jongdae mengantar nampan ke meja dekat dapur, ia bisa mendengar dua staf lain—seorang perempuan dan lelaki muda—berbisik soal Honyun yang “terlalu sering marah” dan “selalu keras kepala sejak putus dari pacarnya tahun lalu.”
Jongdae hanya menarik napas panjang dan kembali ke dapur.
Satu hal yang pasti, malam ini panjang. Dan Jongdae masih harus bertahan, karena inilah hidup yang ia jalani. Tanpa jeda, tanpa pilihan lain—hanya langkah-langkah kecil yang terus ia ambil, meski dadanya masih menyimpan berat yang tidak bisa ia ceritakan pada siapa pun.
Shift malam di Chenchun Dak berakhir lebih lambat dari biasanya. Suara sendok dan sumpit yang sempat gaduh akhirnya mengendap, digantikan denting pelan peralatan makan yang dibersihkan satu per satu. Lampu dapur diredupkan, dan satu per satu staff mulai melepas apron, menyimpan topi, mengelap tangan dengan ujung celemek yang lusuh.
Jongdae berjalan keluar lewat pintu samping, sedikit tertunduk, lehernya terasa berat karena terlalu sering menunduk hari ini. Di bawah lampu jalan yang temaram, ia melihat Areum tengah merapikan ransel kecilnya. Langkahnya melambat.
“Aku antar,” ucap Jongdae pelan, seperti sebuah keputusan yang tak butuh persetujuan.
Areum sontak menggeleng kecil, “Tidak usah, Jongdae-ya. Aku bisa sendiri.”
Belum sempat Jongdae membalas, suara Honyun terdengar dari dekat tempat parkir sepeda motor, “Sok baik banget, dasar penjilat.”
Nada suaranya sumbang, seperti noda di malam yang seharusnya sunyi.
Jongdae tak menoleh. Ia hanya menghela napas dan mengabaikannya sepenuhnya. Areum tampak tidak enak, matanya sedikit menunduk, tetapi akhirnya berkata lirih, “Kalau begitu... sampai stasiun trem saja, ya?”
Jongdae mengangguk. Honyun berjalan menjauh sambil menyalakan rokok, langkahnya berat dan gusar, lalu menghilang di tikungan. Jongdae menatapnya sebentar, sorot matanya menyiratkan kejengkelan yang tidak diluapkan. Lalu ia menatap Areum, mencoba tersenyum, tapi senyum itu gugur di udara malam.
Langit Seoul malam itu berwarna kelam dengan kabut tipis menggantung rendah. Lampu jalan menggurat aspal yang basah sisa hujan sore tadi. Udara menyimpan bau logam, dan dari kejauhan terdengar samar suara musik jalanan dan lalu lintas yang mulai lengang.
Mereka berjalan berdampingan tanpa suara untuk beberapa langkah pertama. Lalu Areum bersuara, pelan sekali, seolah takut suaranya sendiri akan pecah.
“Semalam… ayahku mukul ibu lagi,” bisiknya.
Langkah Jongdae melambat.
Areum terus berjalan, tatapannya lurus, tapi matanya kosong. “Dia marah karena uangnya nggak cukup buat taruhan. Ibu coba jelasin, tapi… kamu tahu kan, orang mabuk nggak bisa dengar alasan.”
Ia menarik napas, tersendat. Tangannya meremas tali ransel dengan erat. “Aku sempat mau keluar rumah. Tapi aku nggak tahu mau ke mana.”
Jongdae ingin mengatakan sesuatu, ingin menjangkau, tapi kata-katanya mati di kerongkongan. Yang bisa ia lakukan hanya menemani, dan mendengarkan.
Areum berhenti sejenak saat mereka tiba di bawah lampu jalan yang meredup, batang sinarnya terpotong dedaunan pohon ginkgo yang belum sepenuhnya rontok. Cahaya temaram jatuh di wajahnya yang tampak lebih pucat dari biasanya.
“Aku… Aku takut dipecat, Jongdae,” lanjut Areum. “Honyun… dia sering banget ngaduin aku ke pemilik restoran. Katanya aku lamban, nggak becus. Aku sudah coba cepat, tapi… kadang aku nggak bisa fokus. Kepala aku… penuh.”
Suara Areum pecah, dan begitu pula pertahanannya. Tangis itu akhirnya jatuh, pelan tapi mengoyak. Jongdae berdiri di sisinya, tangan remahnya tidak tahu harus ke mana. Ia hanya bisa menatap, merasa tubuhnya diisi oleh sesuatu yang berat dan pahit.
Dalam air mata Areum, dalam matanya yang kosong, Jongdae seolah melihat Naari—adik kecilnya yang sering menangis diam-diam jika tak sanggup menahan rindu akan ibunya. Ada rasa bersalah yang halus menyelinap di dada Jongdae. Ia tak ingin Areum merasa seperti itu: sendirian, rapuh, dan terlupakan.
Malam semakin dingin, angin meniup halus jaket Jongdae yang sudah aus. Lampu trem dari kejauhan mulai mendekat, kereta kecil yang akan membawa Areum ke sisi lain kota.
“Aku akan bicara pada pemilik restoran soal Honyun. Tapi... pelan-pelan saja, ya?” ujar Jongdae, akhirnya berbicara, suaranya nyaris bisikan.
Areum mengangguk tanpa kata. Ia mengusap air matanya buru-buru sebelum trem berhenti.
“Terima kasih,” gumamnya pelan, lalu naik ke dalam tanpa menoleh lagi.
Jongdae berdiri di sana untuk beberapa saat, menatap trem yang bergerak menjauh perlahan, membawa serta sisa tangis yang tak bisa ia benarkan.
Dan malam itu, di bawah langit yang berat dan bau trem yang meninggalkan jejak ozon, Jongdae kembali merasa seperti dunia terlalu sunyi untuk semua kesedihan yang belum bisa dikatakan.
Langkah Jongdae menyusuri trotoar sempit Jeonsa malam itu terasa lebih berat dari biasanya. Lampu jalan menyala temaram seperti mata tua yang tak sepenuhnya terjaga. Udara dingin menusuk halus di sela jaketnya yang menipis, dan dari kejauhan terdengar suara sepatu bersentuhan dengan daun-daun gugur yang belum dibersihkan dari pinggir jalan.
Ia menyusuri jalanan yang sudah sangat dikenalnya—rute pulang yang sama sejak dua tahun terakhir. Dulu, mereka tinggal di Gwanak-gu. Rumah dua lantai peninggalan keluarga ayahnya, Geum Jaebum—seorang polisi yang begitu dihormati di distrik itu. Tapi itu dulu, sebelum semua berubah pada suatu malam yang bahkan sampai sekarang enggan ia kenang terlalu lama.
Ayahnya meninggal saat sedang bertugas. Kelas dua SMP, saat dunia seharusnya hanya diisi oleh angka ujian dan latihan ekskul, Jongdae justru harus berdiri mematung di depan peti kayu berselimut bendera, menggenggam tangan adiknya yang gemetar. Ada suara sirine, ucapan belasungkawa, dan pundak ibunya yang bergetar keras dalam pelukan kerabat—semua bercampur menjadi satu kenangan yang membentuk siapa dirinya sekarang.
Sejak saat itu, ibunya, Geum Magaal, mengambil alih segalanya. Seorang penjahit dengan jemari lincah dan mata tajam terhadap garis jahit dan detail desain. Walau sederhana, pelanggannya adalah para wanita kalangan atas yang tak segan membayar mahal untuk gaun-gaun eksentrik dan modern yang hanya bisa dibuat oleh Geum Magaal. Tapi tetap saja, biaya hidup di Gwanak-gu terlalu besar, terlalu berat untuk ditanggung sendiri.
Akhirnya mereka pindah ke Jeonsa. Sebuah apartemen kecil, dua kamar, satu dapur sempit, satu kamar mandi dengan lantai ubin yang dingin, dan ruang tengah yang berfungsi ganda sebagai tempat makan dan bersantai. Tapi tempat itu hangat. Penuh canda singkat dan bau masakan malam hari. Tempat di mana tawa kecil Geum Naari kadang masih menggema saat mereka menonton acara televisi larut malam bersama.
Naari. Gadis kecil yang kini sudah menjadi remaja, dan sekaligus adik yang paling keras kepala sekaligus paling setia. Hanya terpaut satu tahun, tapi kedekatan mereka lebih menyerupai sepasang kawan karib. Naari tahu bagaimana cara membaca ekspresi Jongdae tanpa perlu banyak bicara. Ia tahu kapan harus bertanya dan kapan cukup duduk diam di sebelahnya sambil mengulurkan segelas teh panas.
Langkah Jongdae akhirnya tiba di halaman apartemen mereka. Tangga kecil menuju lantai dua sudah sedikit berkarat, tapi masih kokoh. Ia menaiki tiap anak tangga dengan pelan, seperti membiarkan malam memberi waktu pada pikirannya yang masih sibuk mengingat Areum, Seowon, Jo Anna, Kinam… dan semua kegaduhan dalam dirinya yang belum juga mereda.
Begitu ia membuka pintu, aroma kain, sabun cuci, dan sedikit wangi kue labu menyambutnya. Lampu ruang tengah menyala, dan dari sela pintu kamar, ia bisa mendengar suara mesin jahit berderak halus. Suara ibunya yang bekerja lembur, seperti biasa.
Jongdae melepas sepatunya perlahan, menaruh tas di kursi kayu tua yang bunyinya selalu berderit setiap kali ia duduki. Napasnya mengembus pelan, lalu terhenti saat dari arah dapur, Naari muncul dengan hoodie kebesaran dan rambut yang diikat asal. Ia menatap kakaknya dengan mata yang sedikit menyipit, lelah tapi penuh perhatian.
“Kamu makan?” tanyanya singkat, suara pelan seperti biasa.
Jongdae menggeleng. “Nanti aja. Capek banget hari ini.”
Naari tidak bertanya lagi. Ia hanya mengangguk, lalu masuk kembali ke kamar, menyisakan Jongdae sendirian dalam ruang yang tenang tapi tidak sepenuhnya kosong.
Jongdae duduk di lantai, bersandar di dinding, menatap lampu langit-langit yang berkedip pelan. Suara mesin jahit masih terdengar, mengisi keheningan malam seperti denting waktu yang berjalan lambat tapi pasti. Dan malam itu, dalam kesunyian apartemen kecil yang mereka sebut rumah, Jongdae menyadari bahwa sekalipun dunia luar penuh keretakan dan kebisingan, di sinilah tempat ia bisa menepi. Sejenak.
Daftar Chapter
Chapter 1: Prolog
173 kata
Chapter 2: Jeonsa – Pagi yang Setengah Di...
7,102 kata
Chapter 3: Di Bawah Langit Yang Terlalu B...
5,276 kata
Chapter 4: Langit Tak Pernah Menunggu
6,005 kata
Chapter 5: Rahasia yang Tak Pernah Dibagi
6,094 kata
Chapter 6: Seutas Benang yang Tak Pernah...
7,734 kata
Chapter 7: Rasa yang Tak Bernama
8,481 kata
Chapter 8: Dalbit dan Jam Pulang Sekolah
11,467 kata
Komentar Chapter (0)
Login untuk memberikan komentar
LoginBelum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan komentar!