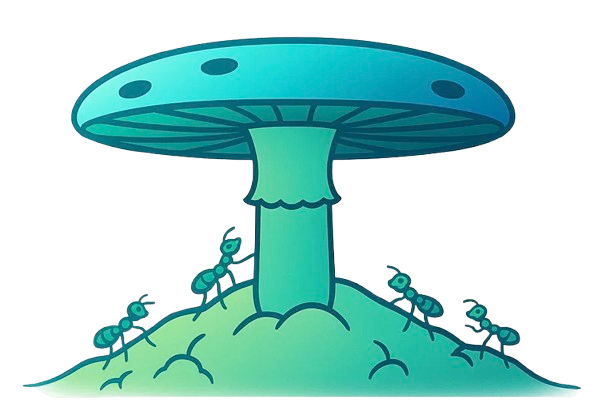Chapter 3: Di Bawah Langit Yang Terlalu Berat
Kelas 11-4 terletak di sisi timur lantai dua gedung Jeonsa High School, di koridor yang jarang terkena cahaya langsung pagi hari. Udara di ruang kelas itu terasa sedikit lembap saat musim hujan, dan terlalu hangat ketika matahari condong ke barat. Dindingnya dipenuhi tempelan pengumuman dan jadwal piket yang mulai menguning, beberapa sudutnya mengelupas karena ditempel dan dicopot berulang kali.
Bangku-bangku kayu sudah banyak yang aus di sisi pinggirnya, beberapa bahkan bergaris goresan nama siswa sebelumnya. Di sisi kiri kelas, ada jendela besar yang selalu dibuka separuh—tempat favorit Jongdae duduk karena bisa melihat pohon persimmon di luar pagar sekolah. Suara kendaraan dari jalan utama sesekali terdengar samar, bersatu dengan bising para siswa.
Kelas ini dihuni oleh siswa-siswa dengan latar belakang beragam—beberapa pendiam, beberapa ribut tak kenal lelah. Di tengah dinamika itu, Lee Kinam, si ketua kelas yang tegas tapi bersahaja, selalu menjadi penengah. Ia dikenal tidak banyak bicara, tapi sikapnya membuat orang segan. Ketika suara kelas mulai kacau, cukup satu lirikan dari Kinam untuk membuat semuanya kembali diam.
Di kelas 11-4, tidak ada yang terlalu mencolok, tapi semuanya tampak seperti sedang memikul beban masing-masing. Senyum yang sering terpaksa, tawa yang mudah padam. Termasuk Jongdae—yang duduk di barisan tengah dekat jendela—yang pikirannya selalu berisik meski wajahnya diam.
Suasana pagi di kelas 11-4 begitu biasa, tapi Jongdae merasa segalanya berjalan terlalu pelan. Langit Jeonsa mendung sejak subuh, menggelayut rendah di balik jendela besar yang setengah terbuka. Udara dingin yang masuk dari celah jendela seolah menampar pelan sisi wajahnya, tapi tak cukup untuk mengusir kantuk yang menggantung di pelupuk mata. Ia duduk di kursinya, tubuh agak bersandar, menatap buku catatannya yang kosong.
Pulpen di tangannya hanya menggambar garis lurus panjang, patah-patah. Seperti perasaannya akhir-akhir ini.
Kinam berdiri di depan kelas, memeriksa absensi dengan suara rendah tapi jelas. Ia selalu terdengar seperti orang dewasa dalam tubuh anak sekolah—tenang, penuh kontrol, sedikit terlalu serius. Tapi Jongdae sudah terbiasa dengan itu. Kinam selalu begitu, sejak mereka duduk di bangku SMP.
“Geum Jongdae,” ucap Kinam, matanya sekilas mencari ke arah bangku tengah.
“Ya,” jawab Jongdae pelan tanpa menoleh.
Kinam hanya mengangguk dan melanjutkan. Di sela suara absensi, ada celotehan kecil dari bangku belakang, suara tertawa yang terlalu keras, dan kursi yang diseret tanpa hati-hati.
Tapi di telinga Jongdae, semuanya terdengar sayup. Seperti hidupnya sedang diputar ulang dengan filter hitam putih dan suara dipelankan.
Ia tahu hari ini akan panjang.
Tugas-tugas menumpuk.
Jam pelajaran yang tak kunjung selesai.
Dan sore yang pasti kembali membuatnya bekerja hingga larut.
Di luar jendela, pohon persimmon bergoyang pelan diterpa angin. Daun-daunnya mulai menguning, sebagian gugur dan menempel di kaca. Musim gugur sudah dekat. Entah kenapa, musim itu selalu membuatnya merasa lebih sunyi.
“Hey.” Kinam tiba-tiba muncul di samping bangkunya, menyodorkan buku catatan yang tertinggal di meja guru. “Kamu lupa ini. Lagi kacau, ya?”
Jongdae mengambilnya pelan, tersenyum singkat. “Sedikit.”
Kinam tidak bertanya lebih lanjut. Ia hanya menepuk pelan bahu Jongdae, lalu berjalan kembali ke bangkunya. Gestur kecil yang cukup untuk memberi jeda dalam keheningan Jongdae. Bel pun berbunyi. Guru pertama belum datang, tapi suasana kelas mulai ramai dengan suara-suara ringan. Jongdae masih diam, menatap langit yang menggantung rendah di balik jendela. Ia merasa seperti sedang duduk di bawahnya—menanti sesuatu jatuh, menanti sesuatu pecah. Tapi belum tahu apa.
Bising dunia tak selalu mampu mengalahkan sunyi dalam kepala. Dan kadang, suara yang paling menusuk… adalah yang tak pernah terucap.
Waktu istirahat datang bersama riuh pelajar yang tumpah ke lorong-lorong sekolah. Jeonsa High School terasa hidup di jam makan siang—tempat di mana kursi dan meja bukan hanya untuk belajar, tapi juga tempat segalanya dibagikan: makanan, tawa, cerita, dan keluh kesah.
Jongdae duduk sendirian di kelas 11-4, membuka kotak bekalnya perlahan. Tangannya bergerak otomatis, menyendok nasi dan lauk tanpa terlalu mencicipi rasa. Suara gaduh dari luar kelas seolah hanya jadi latar samar dalam pikirannya yang penuh.
Tak lama, langkah tenang memasuki kelas.
“Sendirian?” tanya Kinam sambil duduk di seberang bangkunya. Nada bicaranya lembut, tapi tidak dibuat-buat—seperti biasa.
“Hm,” sahut Jongdae, tidak mengangkat kepala. “Kantinnya penuh.”
Kinam membuka roti sobek dari plastiknya dan mengambil dua kotak minuman. Satu diletakkannya di depan Jongdae. “Aku habis bantu Jangmi. Nyiapin properti buat stan kelasnya.”
Jongdae melirik. “Oh ya? Kamu bantuin?”
Kinam tertawa kecil. “Lebih kayak… dipanggil dan nggak bisa nolak. Kamu tahu kan Jangmi gimana.”
Jongdae hanya tersenyum tipis. Ia tahu. Jangmi dikenal cerewet dan galak, apalagi kalau menyangkut urusan kerja kelompok. Tapi bukan tipe yang dibenci. Lebih sering dianggap sebagai ‘komandan’ yang repot tapi selalu tahu harus apa.
“Dia bilang aku terlalu pelan, terus aku disuruh ulangin nyusun rak pajangan dua kali,” sambung Kinam. “Aku iyain aja, takut disemprot.”
“Pintar.” Jongdae akhirnya menyuap satu potong telur dadarnya. “Nggak usah ngelawan, bahaya.”
“Tapi… ya, habis itu dia kasih aku minuman. Galak tapi perhatian.”
“Cocok buat kamu, yang kebanyakan nurut,” gumam Jongdae, senyumnya masih samar.
Kinam tak membantah, hanya tertawa pelan. “Mungkin.”
Percakapan mereka mengalir, ringan, hampir menyembuhkan. Tapi itu hanya sebentar, karena setelah dua teguk minuman, Kinam berkata:
“Tadi aku ketemu Seowon.”
Sendok Jongdae terhenti, gerakannya membeku sejenak di udara.
Kinam melanjutkan dengan nada biasa. “Dia nanya kamu. Katanya akhir-akhir ini nggak kelihatan.”
Diam mengendap di sela tawa kelas. Jongdae tidak langsung merespons. Ia menurunkan sendoknya perlahan.
“Aku jawab seadanya,” ucap Kinam. “Soalnya aku juga nggak tahu kamu ke mana tiap pulang sekolah.”
Jongdae menatap meja sesaat, lalu berkata pelan, “Aku kerja. Dua tempat. Café sama restoran.”
Kinam tampak terkejut, tapi bukan karena merasa dibohongi—lebih karena baru tahu seberapa jauh sahabatnya menjalani hari. “Setiap hari?”
“Hampir.”
Kinam menggigit rotinya pelan, lalu berkata, “Kamu nggak harus sekeras ini.”
Jongdae hanya tersenyum. Senyum kecil, yang lebih mirip penyangkalan. “Kita nggak sama, Nam. Dari awal nggak sama.”
Tak ada yang merasa tersinggung. Kinam paham, meski tidak benar-benar mengerti. Ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan hanya dengan empati. Dan ia tahu kapan harus berhenti bertanya.
“Oh iya,” katanya, mengambil sesuatu dari tas. “Ini titipan dari Seowon.”
Satu kotak susu pisang diletakkan di atas meja Jongdae.
Mata Jongdae sempat membesar sejenak, tapi ia cepat menguasai diri.
Kinam menatapnya, sedikit heran. “Aku sempat mikir… dari mana dia tahu kamu suka susu pisang? Kalian kayaknya nggak pernah ngobrol.”
Jongdae tidak menjawab. Tapi dadanya menghangat sekaligus menyempit. Ada sesuatu dalam diam itu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mungkin karena rindu. Mungkin karena ketakutan. Atau mungkin, karena ia sendiri sudah lama kehilangan cara untuk menunjukkan rasa.
Bel berbunyi beberapa menit kemudian. Siswa-siswa kembali duduk. Tapi bagi Jongdae, ada yang tertinggal—dan bukan hanya susu pisang di atas mejanya.
Setelah bel akhir berbunyi, suara tawa dan langkah kaki menggema di lorong-lorong sekolah. Kelas-kelas terbuka, ransel dipanggul, pintu-pintu terbanting setengah ceroboh. Murid-murid berhamburan, menyongsong sisa hari seperti hidup yang masih punya banyak waktu.
Tapi Jongdae tetap di tempatnya, duduk diam, memandangi jendela yang mulai memantulkan cahaya lembayung. Suara Kinam tadi siang masih melekat seperti bisikan yang belum sempat dipahami penuh. Tentang Seowon. Tentang susu pisang. Tentang dirinya sendiri, yang tak pernah punya cukup kata untuk menjelaskan apa-apa.
Ia bangkit pelan. Langkahnya tidak berat, tapi juga tidak ringan. Hanya pasrah. Di luar kelas, sekolah sudah mulai lengang, hanya beberapa siswa OSIS yang masih sibuk di depan ruang organisasi. Di antara mereka, berdiri Ryu Seowon—rambutnya dikuncir longgar, tangannya sibuk menyusun map warna-warni yang tampaknya selalu lebih teratur daripada isi kepala Jongdae hari-hari ini.
Seowon tampak lelah, tapi tetap tenang. Cahaya sore menyusupi bahunya, membentuk siluet yang hampir tak tega untuk dilihat terlalu lama. Jongdae memperlambat langkah, seolah jarak antara mereka bisa dibentangkan jadi lebih dari sekadar lima meter.
Matanya terpaut pada Seowon yang sama sekali tidak menoleh. Tidak sadar. Atau mungkin pura-pura tidak. Dan Jongdae, seperti biasa, tidak memanggil. Tidak menyapa. Hanya mengalihkan pandang ke ubin, lalu ke tembok, lalu ke langit.
Ada sejenis pertanyaan di dadanya yang tak pernah berubah bentuk: kenapa mereka menjadi seperti ini?
Ia menyusuri lorong perlahan, melewati pintu ruang OSIS yang setengah terbuka. Hanya butuh satu kata untuk menjembatani waktu yang terlampau senyap. Tapi satu kata itu tak pernah datang. Ia tak tahu apakah takut merusak, atau takut berharap.
Di dalam tasnya, susu pisang pemberian Seowon masih tersimpan, suhu botolnya mulai hangat oleh waktu. Ada kejanggalan yang manis—bahwa perempuan yang seakan menjauh itu masih ingat hal kecil seperti selera minuman.
Dan Jongdae... ia hanya tertawa kecil dalam hati. Satu tarikan napas yang terlalu sunyi untuk disebut lega.
Ia keluar gerbang sekolah, diterpa angin yang membawa harum pohon pinus dan debu jalanan. Dunia tetap berjalan, bahkan saat seseorang berhenti berharap. Tapi ia tidak benar-benar berhenti. Hanya berdiri sebentar, di batas antara ingin bicara dan takut mengganggu.
Langit sore menggantungkan warna merah muda yang pucat. Seperti janji yang terlalu lambat diucapkan.
Langkah Jongdae menyusuri trotoar Jeonsa dengan irama yang pelan, seolah satu-satunya alasan ia terus bergerak adalah karena tidak tahu harus berhenti di mana. Angin sore menggugurkan serpih daun dari pohon-pohon rindang di sepanjang jalan, menggiring aroma musim panas yang mulai matang. Cahaya mentari yang mulai turun mengambang di sela gedung—melembutkan garis dunia, tetapi tak bisa menjernihkan pikirannya.
Dalbit mungkin hanya sepuluh menit lagi berjalan, tetapi hatinya belum sampai ke sana.
Dan di persimpangan depan toko roti kecil yang biasa ia lewati, Jongdae melihatnya—Jo Anna.
Gadis itu berdiri sambil menunggu lampu penyeberangan, rambutnya diikat rendah, bayang-bayang tubuhnya melintang panjang di aspal. Ia tak lebih tinggi dari Seowon, mungkin malah lebih mungil dari yang Jongdae ingat. Tapi langkahnya tegap, posisi berdirinya mantap. Tubuh yang kecil, tapi aura yang tak pernah bisa diabaikan. Jongdae tahu betul—gadis itu ikut Taekwondo, dan itu juga alasan mengapa ia dulu bergabung dalam ekskul yang sama.
Namun hari ini, ia kembali melihat sisi lain Jo Anna. Yang bukan sabuk hitam. Bukan postur tegak. Tapi yang berdiri di bawah cahaya lampu lalu lintas, menunduk sedikit, ragu.
Mata mereka bertemu. Sekilas. Ragu. Lalu saling menunduk seperti dua orang asing yang tahu terlalu banyak untuk dianggap tak saling kenal, tapi terlalu kikuk untuk benar-benar bicara.
"Geum Jongdae," Jo Anna yang lebih dulu membuka suara. Suaranya pelan, agak serak, seperti baru saja menelan keraguan. “Tadi aku mau bilang… pas di kantin.”
Jongdae menoleh pelan. "Hm?"
Jo Anna mengusap pelipisnya. “Aku tadi pengin beli jus jeruk. Tapi antrinya panjang. Terus kamu ada di depan... aku nyaris mau panggil.”
Jongdae mengangguk, pelan, terlalu pelan. “Oh. Iya. Aku nggak lihat, maaf.”
Gadis itu tertawa kecil—tawa yang lebih mirip pelarian. “Aku juga nggak panggil, jadi nggak usah minta maaf.”
Keduanya diam. Hening itu menggantung seperti awan yang enggan tumpah. Lampu penyeberangan berubah hijau, tapi tak satu pun dari mereka bergerak.
Dari tempatnya berdiri, Jongdae masih bisa mengingat jelas saat ia menggendong Jo Anna ke ruang kesehatan. Hari itu gadis itu nyaris pingsan karena haid dan kelelahan latihan. Jongdae, yang waktu itu dianggap keras kepala dan tak peduli oleh teman-temannya, tiba-tiba membawa Jo Anna dengan hati-hati, tanpa sepatah kata pun. Sejak hari itu, sesuatu dalam pandangannya terhadap Jo Anna berubah.
Dan hari ini, di bawah lampu lalu lintas yang berkedip pelan, ia tahu: Jo Anna juga mulai melihatnya berbeda. Tapi mungkin, belum cukup berani untuk mendekat.
"Eh... aku duluan, ya." Jo Anna akhirnya bicara lagi, suaranya seperti tergelincir dari sela keraguan. "Latihan hari ini dibatalin."
Jongdae hanya mengangguk. “Hati-hati.”
Dan saat gadis itu menyeberang, punggungnya menjauh pelan—namun meninggalkan bayangan yang tinggal sedikit lebih lama di mata Jongdae. Ia mengembuskan napas. Entah kenapa, setiap pertemuan hari ini seperti menyimpan banyak tanda baca yang tak selesai.
Ia melanjutkan langkah ke Dalbit, kali ini sedikit lebih berat. Hatinya berdesak-desakan oleh nama-nama yang tak bisa ia ucapkan. Seowon. Jo Anna. Dirinya sendiri.
Dan sore di Jeonsa terus berjalan seperti biasa. Tapi di dalam Jongdae, segalanya terasa asing.
Jeonsa adalah kota kecil yang tak pernah benar-benar tidur, tapi juga tidak pernah sepenuhnya terjaga. Ia berdiri tenang di antara kaki perbukitan dan jalur trem yang mengular seperti urat nadi dari pusat kota hingga ke sudut-sudut permukiman.
Gedung-gedungnya tidak tinggi—lebih banyak toko dua lantai, klinik lokal, tempat fotokopi, dan kafe kecil yang bercampur dengan apartemen sederhana, tempat kehidupan berlangsung pelan tapi pasti. Di jalan utama, papan toko berpendar dalam lampu neon tua, dan suara langkah kaki bersahutan dengan denting sepeda yang berlalu.
Udara Jeonsa sore itu lembut, membawa bau kacang panggang dan logam tua dari rel trem. Cahaya matahari mengendap di dinding bata dan jendela kaca, menciptakan semburat keemasan yang membuat segala sesuatu tampak sedikit lebih hangat dari kenyataan.
Tak jauh dari perempatan kecil, tepat di seberang toko bunga yang sudah tutup lebih awal, berdiri Cafe Dalbit—kecil, tenang, dan beraroma manis. Letaknya hanya sekitar dua ratus meter dari apartemen Jongdae, cukup dekat untuk dijangkau dengan berjalan kaki sambil memeluk jaket dari tiupan angin petang. Dalbit adalah salah satu titik paling hangat di Jeonsa, tempat cahaya dari lampu gantung mengalir ke trotoar seperti tumpahan madu.
Dan di antara semua itu, di bawah langit yang mulai berwarna ungu dan biru tua, seorang remaja berjalan pelan, dengan pikiran yang lebih berat dari tas sekolahnya.
Udara sore menyusup pelan lewat pintu kaca yang terbuka sesaat ketika Jongdae mendorongnya masuk. Gemerincing lonceng kecil di ambang pintu menyapa seperti suara lama yang dikenalnya baik—seolah Dalbit tahu betul siapa yang baru saja melangkah.
Langkah Jongdae lebih ringan hari ini, meski pikirannya belum sepenuhnya bening. Botol susu pisang itu menggantung di dalam tasnya, ikut dibawa entah kenapa, seolah menjadi bukti bahwa siang tadi memang nyata. Ia masih memikirkan Seowon, tetapi hanya sebentar—karena aroma kopi dan mentega hangat segera membalut kesadarannya, menariknya kembali ke tempat ini, tempat di mana dunia terasa lebih kecil dan bisa diatur ulang sedikit demi sedikit.
Di balik meja kasir yang sibuk, ada seorang pemuda mungil dengan wajah panik dan celemek yang terlipat miring. Ia menunduk gugup, menyadari kehadiran Jongdae. Potongan rambutnya kuno, seperti gaya anak-anak 2000-an yang tertinggal di bangku barbershop. Tapi matanya—sipit, lembut, dan jujur.
“A-Ah… sunbaenim,” sapanya dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. “Aku Park Seungjo, anak magang baru… Hari ini kita satu shift.”
Jongdae mengangguk pelan, melemparkan senyum tipis yang lebih seperti guratan simpatik di wajah lelahnya. “Halo, Seungjo. Jangan panggil aku Sunbaenim. Jongdae saja, panggil aku Jongdae saja." Ucapnya sembari mencuci tangan, "Baru sehari, sudah kena bentak Yuri-ssi?”
Seungjo tampak gugup. “Dua kali… Hari ini saja,” katanya nyaris seperti pengakuan dosa. Tangannya meremas lap dapur yang tampak terlalu bersih.
Belum sempat Jongdae membalas, dari balik mesin espresso yang berisik, muncul suara serak khas: “Dan dia pantes dapet tiga! Tapi aku ngasih dua aja karena aku masih baik hati hari ini.”
Yuri muncul dengan celemek terlipat rapi dan sebatang pensil terjepit di balik telinga. Wajahnya lelah tapi masih bisa tersenyum sinis. Ia menatap Seungjo seperti kakak perempuan yang kesal tapi diam-diam sayang.
Jongdae tertawa pelan, matanya mengerut lembut. “Kalau Yuri noona baik hati… itu pasti ada apa-apa.”
“Ya, ada. Aku kerja dari pagi sampe sekarang, tanpa istirahat. Kalau magang satu ini bikin tumpah latte lagi, aku pulang beneran,” gerutu Yuri, tapi sorot matanya melembut saat bertemu tatapan Jongdae.
Cahaya lampu kuning Dalbit menyinari rambut mereka yang basah oleh sisa hujan sore. Di luar jendela, dunia mulai menyusut ke arah malam. Tapi di dalam Dalbit, semuanya terasa hangat. Meja-meja nyaris penuh, pelanggan tetap menyelipkan tawa pelan di antara denting sendok, dan mesin kopi tak henti bekerja seperti jantung yang setia berdetak.
Jongdae menggulung lengan bajunya, menyingsingkan letih yang masih menggantung. Ia melirik Seungjo yang kini berdiri kaku seperti gelas yang takut pecah.
“Kau bantu aku susun pastry saja dulu,” ucapnya tenang. “Kopi biar Yuri yang jaga. Kita masih bisa selamat malam ini.”
Seungjo mengangguk cepat, dan seulas lega tergambar di wajahnya. Yuri hanya menghela napas panjang sambil menyambar pesanan baru, wajahnya kembali sibuk.
Di balik keributan ringan dan hangat itu, Jongdae berdiri sejenak menatap seisi ruangan. Dalbit selalu seperti ini—tempat segala yang berat tak terasa seperti beban. Di sini, dunia masih bisa terasa cukup.
Meski susu pisang di tasnya belum sempat disentuh, dan sebuah nama masih diam-diam bersarang di kepalanya.
Suasana hangat Dalbit kembali diisi tawa pelan dan percakapan ringan antara Jongdae, Seungjo, dan Yuri. Meja-meja tetap penuh, udara sedikit lebih wangi oleh aroma kopi pahit dan gula karamel. Jongdae baru saja membantu Seungjo menyusun tumpukan pastry yang hampir ambruk saat pintu kafe terbuka kembali.
Lonceng mungil itu berbunyi sekali lagi.
Seorang pria masuk—sama seperti kemarin. Mantelnya tak berubah, gelap dan panjang. Wajahnya teduh tapi anehnya mengandung sesuatu yang getir, seperti suara pintu tua yang tak bisa benar-benar tertutup rapat. Jongdae langsung mengenalinya, dan dalam diam, ia tahu siapa yang sedang diamati pria itu.
Yuri.
Pria itu kembali memesan hal yang sama seperti kemarin, dan kali ini Jongdae yang melayaninya di kasir. Tak ada banyak percakapan, hanya kode-kode formal dari dua orang asing yang seolah terikat sesuatu yang tak terlihat. Tapi begitu kopi itu siap dan Yuri datang membawanya, dunia seolah merapat.
Langkah Yuri sempat melambat. Kedua tangannya menggenggam cangkir keramik putih itu dengan ringan, nyaris gemetar. Dan saat ia menyerahkannya, ia menatap wajah pria itu sesaat. Lalu membeku.
Kaca dalam pupilnya memantulkan sesuatu yang tak dapat dijelaskan—mungkin kenangan. Atau luka. Atau keduanya.
Sekilas, Jongdae melihat perubahan itu. Yuri yang biasanya penuh kelakar, kini seperti dilucuti dari warna. Wajahnya bukan hanya pucat—tapi kosong. Ia tak mengucap apa-apa, hanya menunduk pelan sebelum berbalik dan melangkah menjauh, cepat, nyaris panik.
“Yuri noona?” panggil Jongdae pelan, hendak menyusul. Tapi Yuri tak menjawab. Ia langsung menyelinap ke balik dapur, suaranya hilang ditelan suara mesin espresso yang bergemuruh.
Seungjo menatap Jongdae, bingung. “Apa dia… kenal pria itu?” bisiknya.
Jongdae tidak menjawab. Ia hanya diam sebentar, melirik pria yang kini duduk di pojok, menyesap kopi tanpa ekspresi. Ada sesuatu yang terlalu dingin dari sosok itu—bukan hanya karena musim, tapi karena keberadaannya seperti membawa hawa yang tidak ingin dikenang siapa pun.
Yuri tak muncul kembali selama beberapa menit. Jongdae menyibukkan diri melayani pelanggan berikutnya, mencoba sekuat tenaga untuk tetap tenang. Seungjo menunduk dalam-dalam, menyusun ulang pastry seperti sedang menyusun ulang pikirannya yang kacau. Ia masih terlalu hijau untuk paham, tapi cukup peka untuk tahu bahwa udara di Dalbit tak lagi sehangat tadi.
Sementara itu, di balik dapur sempit, Yuri berdiri di sisi rak bumbu, punggungnya menempel ke dinding. Ia menekan mulutnya sendiri, seolah takut satu isakan kecil akan runtuhkan seluruh dirinya.
“Kau selalu jadi beban.”
Kalimat itu tidak terdengar oleh siapa pun, tapi menggema dalam kepalanya. Kalimat yang diucapkan pria itu bertahun-tahun lalu—tajam, berat, dan cukup kuat untuk memutuskan tali darah yang seharusnya tak bisa putus. Ia tak ingat lagi bagaimana rasanya punya ayah, dan sekarang, bahkan luka itu tak sempat ditambal. Ia telah lama menghapus nama dan wajah itu dari hidupnya, tapi ternyata tak cukup dalam.
Sore ini, luka itu kembali hidup.
Dan meski tak ada yang tahu, Yuri merasa seperti anak kecil lagi—gugup, takut, dan nyaris menangis.
Namun saat ia akhirnya keluar, wajahnya tetap tenang. Bahkan ada senyum samar yang dipaksakan, seperti seseorang yang sedang menutupi retakan di dinding rumahnya dengan wallpaper cantik. Jongdae meliriknya, menyadari semuanya, tapi memilih diam. Tak semua cerita harus diceritakan, pikirnya. Beberapa luka tak ingin disentuh, cukup dijaga dari jauh.
Dalbit tetap bekerja. Mesin espresso berdetak. Seungjo kembali menyeka meja. Dan pria itu perlahan pergi, meninggalkan jejak udara dingin yang tak bisa dibersihkan oleh aroma kopi sekali pun.
Jongdae menghela napas. Ia tak tahu apa yang terjadi, tapi tahu bahwa tak semua orang datang ke kafe untuk sekadar minum kopi.
Beberapa datang untuk mengingat.
Beberapa untuk menghapus.
Dan beberapa… hanya ingin bertahan.
Cahaya senja yang biasanya menyentuh hangat jendela, kini telah menguap jadi bayang-bayang lembut yang digantikan lampu gantung. Kafe mulai sepi, hanya tersisa dua pelanggan yang bercakap lirih di pojok ruangan, dan suara radio tua yang memutar lagu jazz pelan seperti napas terakhir dari hari yang terlalu panjang.
Jongdae menyeka loyang kosong perlahan. Tangannya bergerak otomatis, tapi pikirannya tidak. Sejak Yuri kembali dari dapur tadi, ekspresinya tak benar-benar kembali seperti semula. Ia tetap tertawa tipis, tetap bercanda ringan dengan pelanggan tetap mereka, tapi dari matanya, Jongdae tahu: ada air yang tertahan.
Seungjo duduk di kursi dekat rak majalah, pura-pura sibuk dengan laporan stok bahan, tapi sesekali melirik ke arah Yuri dengan ragu.
Sementara itu, Yuri berdiri membelakangi mereka. Di balik bar kopi, ia membersihkan mesin dengan tangan yang terlalu hati-hati, terlalu pelan. Seolah jika ia bekerja terlalu cepat, pikirannya akan ikut terseret keluar dari tempat persembunyiannya.
Jongdae akhirnya mendekat.
“Nuna, kau nggak apa-apa?”
Yuri terdiam sebentar, seakan memilih apakah perlu menjawab jujur atau tidak.
“Apa aku kelihatan tidak apa-apa?” jawabnya, pelan, masih membelakangi.
Suaranya terdengar seperti angin yang melewati celah jendela tua—tidak kencang, tapi cukup untuk membuat dada sesak.
Jongdae menyandarkan tubuh ke pinggiran bar. Ia tidak ingin mendesak, tapi tak ingin pura-pura tak tahu juga.
“Aku nggak tahu apa yang terjadi… tapi kalau ingin cerita, aku dengar,” katanya. Lirih. Tak mendesak.
Yuri tak menjawab. Ia hanya menunduk sedikit lebih dalam. Lalu menghela napas, panjang.
“Kadang aku pikir… aku sudah baik-baik saja,” ucapnya akhirnya. “Tapi ternyata tubuh ini masih bisa gemetar saat melihat wajah itu. Wajah yang mestinya kulupakan sejak lama.”
Jongdae tidak bertanya siapa. Ia tahu jawabannya. Ia tahu rasa takut macam itu tidak datang dari kekasih, atau teman, atau bahkan musuh. Hanya satu jenis hubungan yang bisa membuat luka tetap terbuka meski waktu terus berjalan.
Keluarga.
“Dia tidak akan sering datang ke sini, kan?” tanya Seungjo tiba-tiba, dengan suara hati-hati, seperti anak kecil yang takut mengganggu. “Kalau dia bikin Nuna takut, kita bisa bilang ke pemilik… untuk—”
“Tidak usah,” potong Yuri cepat, tapi nadanya tidak marah. Lebih seperti seseorang yang terlalu lelah untuk memperpanjang beban. “Dia tak akan kembali. Mungkin hanya... lewat. Atau ingin memastikan aku belum mati.”
Kalimat itu membuat ruangan terasa jauh lebih sunyi. Bahkan detak jam tua di dinding ikut terdengar lebih lambat.
Jongdae menatap Yuri dalam-dalam. Ia ingin mengatakan sesuatu—apa pun. Tapi tak ada yang cukup pantas. Tak ada kalimat yang bisa menjahit luka seperti itu.
Jadi ia hanya berdiri di sana, seperti tiang penyangga yang diam-diam menahan atap rumah.
“Kalau kau ingin cuti sehari, bilang saja ke aku,” katanya akhirnya. “Aku akan ganti shift-mu.”
Yuri menoleh, perlahan. Wajahnya lembut, letih, tapi ada senyum kecil yang muncul di sudut bibirnya. Bukan senyum karena bahagia—tapi karena merasa dimengerti, walau sedikit.
“Terima kasih, Dae.”
Malam terus merangkak. Seungjo sudah mulai membereskan meja dan membuang sisa tisu yang tercecer. Dalbit pelan-pelan kembali ke bentuk semula—tenang, rapi, seperti tak ada hal besar yang baru saja terjadi.
Tapi Jongdae tahu, untuk beberapa orang, luka yang dalam itu tidak bersuara.
Ia hanya diam, duduk manis dalam dada, menunggu hari lain untuk muncul kembali.
Dan malam ini, ia melihatnya hidup di mata Yuri.
Langit di atas Jeonsa seperti kertas buram yang basah—redup, kusam, dan tampak rapuh. Awan tipis menggantung seperti lapisan emosi yang tak bisa diseka, dan udara malam menyimpan dingin samar yang merambat sampai ke tulang.
Lampu-lampu jalan menyala satu-satu, menyinari trotoar yang sepi dan menyoroti jejak kaki yang sudah lelah. Sepeda motor sesekali melintas dengan dengung malas, dan suara televisi dari sebuah warung kecil menyelinap samar dari sela pintu kaca.
Jongdae berjalan di sisi kanan trotoar, sedangkan Yuri di sisi kiri. Keduanya melangkah tanpa tergesa, menyusuri malam yang seakan tahu kalau hati mereka tak sedang baik-baik saja. Jarak mereka hanya beberapa meter, namun pikiran mereka terasa jauh dari mana pun.
Di perempatan yang lengang, langkah mereka akhirnya melambat. Di sinilah jalan mereka berpisah—Jongdae ke arah apartemen murah di blok barat, dan Yuri ke arah timur, ke studio sewanya yang sempit dan sepi. Tak ada angin, hanya udara yang terasa berat seperti dada yang menahan tangis.
Jongdae hampir melangkah lebih jauh ketika suara lirih menahannya.
“Jongdae-ya…” suara itu kecil, serak, nyaris tenggelam oleh deru mobil dari kejauhan.
Ia menoleh. Yuri berdiri di bawah lampu jalan yang temaram. Bayangannya tercetak samar di aspal. Matanya tidak menangis, tapi di sana ada sesuatu yang lebih menyakitkan dari air mata.
“Kau juga pernah merasa hidup ini… menyebalkan?”
Pertanyaan yang sederhana. Tapi nadanya, cara Yuri mengucapkannya—seolah dunia baru saja retak sedikit lagi malam ini.
Jongdae terdiam. Tatapan mereka bertemu, dan dalam pandangan itu, Yuri tidak lagi tampak seperti perempuan dewasa yang keras kepala dan penuh lelucon sarkastik. Ia terlihat seperti seseorang yang sedang berjuang untuk tetap tegak, padahal hatinya sedang runtuh satu-satu.
“Yuri-nuna…” gumam Jongdae, pelan.
Yuri memalingkan pandangan, lalu mengangguk ke arah kursi panjang di tepi trotoar, tak jauh dari toko makanan cepat saji yang sudah tutup. Kaca tokonya memantulkan cahaya lampu jalan dan siluet mereka, seperti menyaksikan luka yang akhirnya bicara.
Mereka duduk berdampingan. Tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk merasakan napas satu sama lain.
Yuri merogoh sakunya, mengeluarkan sebungkus rokok yang isinya tinggal dua batang. Ia menyalakannya dengan jemari yang sedikit gemetar, lalu menarik napas panjang seperti seseorang yang berusaha menelan segenap kelelahan hari itu.
“Asap ini... entah kenapa rasanya lebih pahit malam ini,” katanya. Ia tersenyum tipis, tapi bibirnya seperti tak lagi percaya pada kebahagiaan kecil.
“Aku tahu pria itu akan datang lagi suatu hari,” lanjutnya. “Tapi tidak hari ini. Tidak ketika aku sedang mencoba hidup seperti biasa. Tidak ketika aku hampir melupakan suara dan wajahnya.”
Jongdae hanya mendengarkan. Tidak menjawab. Karena ada luka yang tidak minta ditambal, hanya dimengerti.
“Ayahku,” ucap Yuri akhirnya. “Dia... seperti kabut. Kadang datang diam-diam, tapi selalu meninggalkan basah. Dan aku benci karena aku masih bisa takut. Masih bisa merasa kecil.”
Ia tertawa—tawa getir yang tak naik ke mata.
“Aku minta maaf. Aku membuat Dalbit jadi sunyi hari ini.”
“Tidak apa-apa, Nuna,” jawab Jongdae pelan. “Kadang tempat paling hangat pun bisa terasa dingin kalau hati kita sedang jatuh.”
Mereka terdiam bersama. Hanya bunyi nyala rokok dan dengung lampu jalan yang menemani.
Jongdae melihat ke langit. Tidak ada bintang. Hanya kelabu yang menggantung, seperti emosi yang tak selesai.
Dalam hati, ia sadar—masing-masing dari mereka menyimpan langit yang berbeda. Dan malam seperti ini, saat semuanya terasa tak tertata, mungkin mereka hanya butuh tempat untuk duduk dan tidak apa-apa bersama.
Yuri memejamkan mata sebentar, lalu membuang napas panjang.
“Terima kasih sudah duduk di sini.”
Jongdae tidak menjawab, tapi ia tetap duduk di sana, bersama diam yang mengerti lebih dari ribuan kata.
Asap rokok menari lambat, mengambang di antara mereka seperti rahasia yang enggan jatuh ke tanah.
Yuri masih duduk di sisi kanan, tangan kirinya menggenggam rokok yang mulai pendek, dan tangan kanannya memeluk dirinya sendiri seolah dingin tak hanya datang dari malam, tapi juga dari dalam dadanya.
Ia belum berbicara lagi sejak ucapan terima kasih tadi. Tapi Jongdae tahu, ada sesuatu yang belum selesai. Matanya memandang jauh ke arah lampu lalu lintas yang berkedip merah di kejauhan, tetapi pikirannya ada di tempat lain—di masa lalu yang tak bisa ia pilih.
Lalu, suara Yuri kembali terdengar, lirih, seperti seseorang yang bicara dari bawah air.
“Jongdae-ya…” Ia tak menoleh, “Kau masih punya ayah?”
Pertanyaan itu datang seperti batu kecil yang dilempar ke danau sunyi. Riaknya pelan, tapi terasa sampai dasar.
Jongdae mengerjap, sedikit terkejut. Tapi ia tak menunjukkan itu dalam ekspresi. Ia hanya menarik napas, menahan detak yang sempat tertahan, lalu menjawab pelan.
“Sudah tiada. Meninggal… saat aku SMP.”
Yuri mengangguk sekali. “Maaf. Aku tidak tahu.”
“Tidak apa-apa.”
Diam sejenak kembali menyela. Tapi di dalam kepala Yuri, keheningan itu bukan ruang kosong. Justru sebaliknya—ia penuh. Riuh. Padat dengan kenangan yang menggulung cepat, kasar, dan dingin.
Seperti diputar ulang oleh tangan yang tak kenal belas kasihan.
Suaranya masih jelas.
Nada itu.
Nada jijik.
Nada penghakiman.
Nada yang menusuk seperti jarum halus tapi panjang.
“Kau hanya beban. Lahir pun tak diminta.”
“Apa kau pikir hidupmu penting?”
“Anak macam apa yang hanya tahu membuat malu?”
“Aku bahkan tak ingin melihat wajahmu.”
“Keluar. Sekarang. Dan jangan pernah kembali.”
Kata-kata itu menghantamnya seperti batu, berulang-ulang. Ia ingat hari itu. Langit bahkan cerah. Ironis sekali, bagaimana matahari bisa bersinar terang saat dunia di dalam dirinya runtuh seketika.
“Dia bilang aku... lebih rendah dari hama,” ucap Yuri dengan suara nyaris tenggelam.
“Katanya aku tidak pantas tinggal di rumah itu. Tidak pantas menyandang nama keluarganya. Tidak pantas jadi siapa-siapa.”
Jongdae menoleh cepat. Tatapannya tak lagi biasa. Di sana ada iba, ada ketakutan, dan ada kesadaran bahwa di sisinya malam ini duduk seseorang yang selama ini menyimpan luka sedalam lautan dan belum pernah menyentuh permukaan.
Yuri tertawa pelan—bukan karena lucu, tapi karena hanya itu yang bisa ia lakukan agar tak menangis.
“Kau tahu rasanya dipanggil anak, tapi tak pernah benar-benar diakui sebagai anak?” katanya. “Seperti... kau tumbuh dalam tubuh yang ditolak sejak awal. Seperti ruang kosong yang tetap kosong walau kau isi dengan apapun.”
Tangannya yang bebas mengusap wajahnya cepat. Tidak ada air mata yang jatuh, tapi jelas dari suara yang mulai pecah dan napas yang tak teratur, bahwa ia sedang mencoba bertahan. Menyusun dirinya kembali agar tidak runtuh di hadapan satu-satunya orang yang mendengarkan malam ini.
Jongdae masih diam. Karena kadang, tidak ada kata yang bisa cukup untuk menjahit luka sebesar itu. Kadang, cukup duduk di sana adalah bentuk empati tertinggi yang bisa diberikan.
Di matanya, Yuri tak lagi tampak seperti perempuan dewasa yang nyaring dan keras kepala. Malam ini, ia adalah seorang anak kecil yang berdiri di tengah reruntuhan rumah yang pernah ia sebut tempat pulang. Rambutnya berantakan oleh angin malam, bahunya tampak lebih kecil dari biasanya, dan matanya—ya, matanya—penuh dengan reruntuhan kata-kata yang tak pernah bisa diperbaiki.
Jongdae menarik napas panjang. Hatinya terasa penuh. Bukan karena bisa mengerti, tapi karena malam ini, untuk pertama kalinya, Yuri memperlihatkan sisi dirinya yang tak pernah ia tunjukkan kepada siapa pun.
Sisi yang rapuh.
Sisi yang hancur tapi tetap hidup.
Sisi yang tak butuh nasihat, hanya tempat untuk berhenti lari.
Dan malam itu, di bawah langit Jeonsa yang kelabu, mereka duduk diam seperti dua orang asing yang tiba-tiba diikat oleh luka. Tak saling bertukar janji, tak saling memeluk, tapi saling tahu bahwa ada sesuatu yang telah terbagi. Sesuatu yang mungkin tak akan sembuh, tapi kini tidak sendirian.
Pagi datang pelan-pelan di Jeonsa, seperti seorang ibu yang tak ingin membangunkan anaknya terlalu cepat. Sinar matahari menyusup malu-malu dari balik tirai kamar Jongdae, menyoroti rak buku tua dan botol susu pisang yang belum sempat disentuh kembali sejak tadi malam. Ia duduk di tepi tempat tidurnya, diam. Wajahnya menunduk, dan jari-jarinya menggenggam botol itu seperti sedang memeluk sebentuk tanya yang belum dijawab.
Semalam, Yuri membuka dirinya seperti halaman yang tak pernah ia biarkan orang baca. Dan pagi ini, Jongdae terbangun dengan rasa berat di dada, seolah setiap napasnya membawa sisa luka orang lain yang belum sempat sembuh.
Dari dapur, terdengar suara ibunya menyeduh teh. Aroma herbal bercampur sabun cuci piring mengisi ruang tengah apartemen sempit itu. Naari sudah sibuk dengan seragam sekolahnya—rambut diikat rapi, dan suara langkahnya cepat seperti biasa. Tapi Jongdae belum ingin beranjak.
Beberapa menit kemudian, ia melangkah keluar. Jalanan Jeonsa sudah ramai. Trotoar dipenuhi siswa berseragam dan toko-toko kecil yang membuka pintu mereka dengan malas. Langit hari itu cerah, terlalu cerah untuk isi hati Jongdae yang masih kelabu.
Koridor Jeonsa High School menyambutnya dengan suara sepatu dan obrolan semangat pagi. Seseorang memanggil nama Kinam dari kejauhan, dan ketua kelas itu membalasnya dengan anggukan ringan. Jongdae masuk kelas sedikit lebih lambat dari biasanya. Meja-meja sudah hampir terisi penuh, dan udara kelas hangat oleh hiruk-pikuk yang biasa. Tapi Jongdae merasa seperti berdiri di pinggir sesuatu yang tak bisa ia jangkau.
Kinam sudah duduk di bangkunya. Ia menoleh dan memberi senyum tipis, mengangkat selembar kertas ulangan dari tumpukan.
“Dapet bagus kemarin,” katanya pelan, lalu menyerahkan kertas itu pada Jongdae.
Jongdae mengangguk kecil. “Bagus?” suaranya nyaris tak terdengar. “Syukurlah.”
Ia duduk dan membuka kotak pensil, tapi tatapannya kosong. Di antara canda teman-teman dan suara papan tulis yang digosok kain, Jongdae merasa sepi. Mungkin karena semalam terlalu berat, atau karena pagi ini terlalu biasa.
Dan kadang, hal paling menyakitkan adalah menyadari bahwa dunia tidak pernah benar-benar berhenti untuk menunggu luka seseorang sembuh.
Daftar Chapter
Chapter 1: Prolog
173 kata
Chapter 2: Jeonsa – Pagi yang Setengah Di...
7,102 kata
Chapter 3: Di Bawah Langit Yang Terlalu B...
5,276 kata
Chapter 4: Langit Tak Pernah Menunggu
6,005 kata
Chapter 5: Rahasia yang Tak Pernah Dibagi
6,094 kata
Chapter 6: Seutas Benang yang Tak Pernah...
7,734 kata
Chapter 7: Rasa yang Tak Bernama
8,481 kata
Chapter 8: Dalbit dan Jam Pulang Sekolah
11,467 kata
Komentar Chapter (0)
Login untuk memberikan komentar
LoginBelum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan komentar!