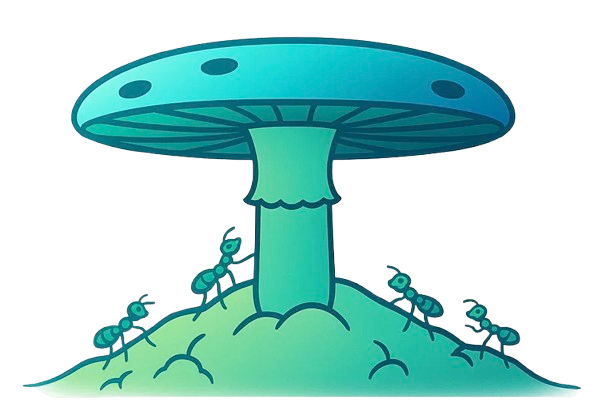Chapter 4: bab 4
Baru pukul setengah delapan malam, Bandot sudah datang ke kediaman Rumiyati. Dia sengaja membawa motor memutar, berhenti di pekarangan belakang. Rumiyati keluar dari dapur dengan tergopoh-gopoh.
“Loh, sudah dateng, toh. Sik, aku siap-siap sebentar yo, Ndot.” Rumiyati bergegas masuk. Dia tidak menyangka kalau Bandot tiba sebelum waktunya. Dia belum bersiap apa-apa.
Bandot dengan sabar menunggu di atas motor. Untuk mengusir jenuh, dia menyalakan sebatang rokok. Pemuda itu menyunggingkan senyum miring, mengingat pertemuannya dengan Mbah Siman tadi siang.
“Mbah, pokoke sampeyan harus jodohin dia sama aku. Hidupku ini biar berubah, gitu lho. Tolong ya, Mbah,” pinta Bandot, memohon-mohon pada Mbah Siman.
“Yo wis. Demi kamu, Mbah rela jadi aktor dadakan. Harus pakai apa, pura-pura jadi dukunnya?” Kakek itu balik bertanya.
Garis lengkung sempurna tergambar di wajah pemuda tersebut. Segera dia beranjak dari kursi ruang tamu, meraih mangkuk kecil dari kuningan di atas lemari pendek milik Mbah Siman. “Pakai ini, Mbah. Bilang saja, ini mangkuk sakti. Nanti Mbah isi aja sama air. Terus, Mbah bilang kalau Mbak Rum harus menikah dengan saya untuk tulak balak. Lepas sial gitulah, intinya. Poles ucapan Mbah supaya lebih meyakinkan, yo.”
Kedua manusia itu tertawa bersama. Mbah Siman ini masih kerabat Bandot. Dia adalah adik kandung kakeknya. Ditambah lagi, hubungan mereka memang terbilang akrab.
“Ayo, Ndot. Aku sudah siap.” Lima menit kemudian, Rumiyati sudah berdiri di hadapan Bandot yang masih mengulum senyum. Wanita itu tetap terlihat cantik di tengah muramnya malam. Bulan sabit membuat cahaya remang, tak seterang malam-malam sebelumnya.
“Hayuk, Mbak. Naik!” Bandot tampak sangat bersemangat.
Rumiyati sengaja mengenakan celana panjang agar mudah berboncengan. Dia letakkan tas sebagai penyekat antara tubuhnya dan punggung Bandot. Bagaimanapun, dia harus berjaga-jaga dari manusia berjenis kelamin laki-laki.
Bandot melajukan motor pelan-pelan di sepanjang pematang. Motor berwarna merah, khas kendaraan jadul, membelah sawah di belakang rumah Rumiyati. Keduanya tidak ingin warga lain sampai tahu tentang kepergian mereka. Bisa bahaya. Rumor pasti akan cepat beredar ke seluruh penjuru desa. Bisa-bisa mereka bilang kalau Bandot dan Rumiyati berzinah. Bandot tidak ingin membuat Rumiyati merasa jengah, lalu menjauh dan menghindari dirinya. Ciloko tenan!
“Ndot, rokokmu matikan! Asapnya, ampun.” Rumiyati terbatuk-batuk ketika gumpalan asap menyerbu wajah.
“Woh, sori, Mbak. Ta pikir nggak masalah. Nggak suka rokok, toh.” Bandot melempar rokok yang diapit jari telunjuk dan tengah tangan kirinya itu jauh-jauh. “Rokok idolanya Mbak Rum pasti yang nggak perlu dinyalakan itu, ya?”
“Sembarangan!” Rumiyati memukul pelan bahu Bandot.
Dua anak manusia menuju satu arah, tetapi berbeda kepentingan itu terus bercanda di sepanjang perjalanan. Harus diakui, Bandot memang pandai membuat suasana menjadi santai, ringan, dan mengalir. Waktu tempuh hampir satu jam benar-benar tidak terasa. Tahu-tahu, mereka sudah tiba di depan rumah Mbah Siman. Bangunan sederhana dengan lampu kuning yang temaram di bagian depan. Bohlam memang masih menjadi idola di kawasan desa.
Tidak ada aura seram, apalagi mencekam, seperti yang dibayangkan oleh Rumiyati sebelumnya. Semua tampak biasa saja. Normal layaknya rumah penduduk biasa.
Setelah mematikan mesin motor, Bandot mengetuk pintu. Terdengar suara langkah kaki agak diseret, berjalan mendekat. Tak berapa lama, tampak seorang kakek muncul di balik pintu yang terbuka sedikit.
“Assalamu’alaikum, Mbah. Sehat?” Bandot segera meraih tangan pria tersebut, lalu menciumnya, begitu pintu dibuka lebih lebar lagi.
“Oalah, Bandot, toh. Alhamdulillah sehat, Le. Sudah berapa tahun kamu ndak ke sini, ya.” Kakek berusia sekitar tujuh puluh tahun itu tampak semringah menyambut kedatangan Bandot.
“Sudah lima tahunan, Mbah. Eh, ini ... aku bawa tamu.” Bandot memberi tanda kepada Rumiyati untuk mendekat.
Wanita itu langsung mengulurkan tangan dan disambut dengan lembut oleh Mbah Siman yang kemudian mempersilakan mereka masuk. Manusia tua itu tampak tertatih, menyusul duduk di kursi ruang tamu.
“Mbah dulu banyak tamu. Tapi, sekarang sudah ndak mau nerima tamu dari luar. Mbah cuman ngeladenin keluarga sama kenalan baik saja. Mbah kan sudah tua. Jadi, mau banyak istirahat.” Mbah Siman mendahului bicara.
“Mbak Rum ini teman deket saya, Mbah. Sudah kayak keluarga sendiri. Jadi, tolong dibantu, ya.” Bandot pindah duduk di sebelah si kakek, lalu memijit-mijit bahunya.
Kakek itu terdiam sejenak. Dia memandang Rumiyati lekat-lekat, dari atas hingga bawah. Dia seperti mesin pemindai yang sedang meneliti target.
Ayu tenan. Pantesan, Bandot kesengsem, ucap Mbah Siman di dalam hati.
“Ya, Mbah. Saya cuman mau minta petunjuk aja biar hidup saya bisa lebih tenang. Ada beberapa hal yang pengin ta tanyakan kalau memang Mbah berkenan.” Rumiyati mencoba membujuk.
Dia mengira kalau Mbah Siman benar-benar sudah pensiun dari dunia perdukunan. Dari yang dia dengar tadi, Bandot juga sudah lama tidak ke sini, sekitar lima tahunan. Wajar kalau pemuda itu tidak tahu kalau si kakek sudah pensiun.
“Dari aura panjenengan, gelap sekali. Pasti lagi banyak masalah. Kasihan. Masih muda, cantik, tapi kok hidupnya susah. Ya sudah, karena kamu masih teman dekatnya Bandot, Mbah mau bantu. Tunggu sebentar, ya.” Mbah Siman bangkit berdiri.
Perlahan, dia masuk ke kamar depan, lalu kembali dengan membawa sebuah mangkuk kuningan berisi air. Kakek itu meletakkannya di atas meja.
“Ndak usah cerita apa-apa. Panjenengan cukup memasukkan tangan ke sini. Sebentar saja, yang kanan,” ucap Mbah Siman.
Rumiyati menuruti perintah si kakek. Dia memasukkan tangan kanan hingga sebatas pergelangan. Airnya terasa dingin sekali. Sepuluh detik kemudian, Mbah Siman mengibaskan tangan, tanda selesai.
Laki-laki tua itu kemudian mengangkat mangkuk dan meletakkannya di pangkuan. Mulutnya terus berkomat-kamit selama beberapa menit. Rumiyati tampak gelisah, menunggu dengan dilingkupi rasa penasaran.
“Buang air ini di depan, Ndot,” titah Mbah Siman. Bandot menuruti perintahnya.
Setelah Bandot kembali duduk, Mbah Siman mulai bertutur. Dia mengatakan bahwa Rumiyati terkena sebuah balak yang dia terima tanpa sengaja saat dilahirkan. Kutukan itu akan membuatnya jatuh miskin, hidup sendirian, sakit, bahkan meninggal, tak sampai usia tiga puluh tahun.
Kakek itu juga mengatakan bahwa dia melihat sosok pria tampan yang baru saja meninggal, belum empat puluh hari sedang duduk di samping Rumiyati. Hanya Mbah Siman yang bisa melihat dan berkomunikasi dengan dia.
“I-itu siapa, Mbah?” Rumiyati mulai ketakutan.
“Namanya Subandi, Mbak. Katanya, dia suami panjenengan.” Mbah Siman berucap lirih.
Rumiyati sontak terkejut, mengetahui laki-laki tua itu demikian sakti. Dia segera menanyakan keadaan almarhum Subandi, juga mungkin ada pesan yang ingin disampaikan oleh mendiang suaminya itu. Air mata langsung membanjiri pipi wanita tersebut.
Bandot menahan tawa melihat akting Mbah Siman yang sangat meyakinkan. Tentu saja, dia sudah memberikan semua informasi lengkap tentang Rumiyati dan kematian sang suami tadi siang. Tidak hanya tegas saat berbicara, kakek tua itu juga berpura-pura jalan tertatih, padahal masih gesit.
“Di-dia ... bilang apa, Mbah?”
Daftar Chapter
Chapter 1: Salahkah aku bersuami?
1,214 kata
Chapter 2: Bab 2
1,192 kata
Chapter 3: bab 3
1,195 kata
Chapter 4: bab 4
1,159 kata
Chapter 5: Bab 5
1,101 kata
Komentar Chapter (0)
Login untuk memberikan komentar
LoginBelum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan komentar!