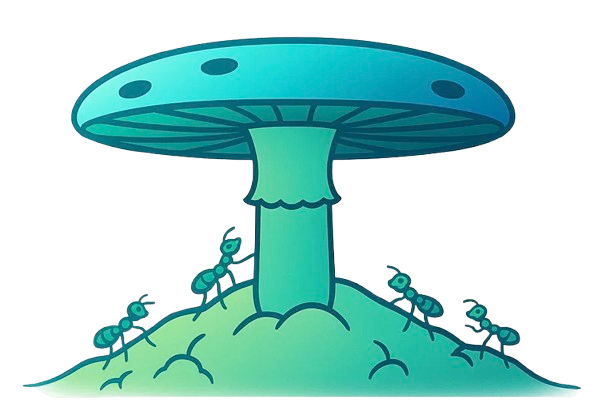Chapter 7: New Job
Waktu kecil, aku pengin banget segera jadi dewasa. Orang dewasa itu enak. Mereka nggak perlu tidur siang. Mereka bebas keluar malam dan melakukan semua hal yang disukai. Nggak ada yang akan ngomel kalau mereka bikin kesalahan. Hidup mereka tenang.
Teryata aku salah.
Aku nggak tahu kalau jadi dewasa juga harus memikirkan masalah keuangan. Kukira uang bisa datang sendiri, tanpa perlu repot dicari. Baru kusadari kalau selama tiga bulan ini keuanganku nggak ada pemasukan sama sekali. Yang kulakukan cuma menghabiskan uang, tanpa pernah sadar kalau nanti uang dalam rekening Papa dan Mama bisa habis, seperti sekarang ini.
"Mak? Ini katanya surat pemberitahuan yang ketiga, yang pertama sama kedua mana?" tanyaku dengan suara bergetar. Surat ini lumayan membuatku syok. Cicilan rumah yang harus kubayar totalnya mengerikan, lebih dari tujuh puluh juta. Sisa uang yang kumiliki bahkan nggak sampai setengahnya. Kalau begini, aku harus cari uang di mana? Nggak mungkin ada orang yang keterlaluan kaya membuang uang puluhan juta secara cuma-cuma, kan?
Jemari tangan Mak Oci saling bertautan. Kakinya bergerak gelisah. Matanya berkelana, nggak jelas mencari apa. "Maaf, Kak. Mak Oci lupa. Kayaknya, sih, memang pernah ada dua surat yang mirip itu. Tapi, Mak Oci lupa taruh di mana."
Mak Oci memang sudah nggak muda lagi. Usianya sudah 64 tahun. Rambut lurusnya nyaris putih semua, mirip gurunya naruto, tapi tanpa masker miring. Dulu, Mama sering pusing dengan sikap Mak Oci yang sering lupa. Sekarang, aku juga pusing dengan pikunnya Mak Oci.
Aku memejamkan mata sambil bernapas dalam-dalam, berharap ada banyak uang ikut mendekat sampai menutupi lubang hidungku. Sayang, yang ada malah jutaan paku menghujam kepalaku. Kepalaku ini cuma satu, tapi terus memikirkan angka tujuh puluh juta. Kekuatannya nggak seimbang. Takutnya, sebentar lagi kepalaku bisa terbelah jadi kepingan puzzle sebanyak tujuh puluh juta keping.
Kalau banyak orang menganggap angka 13 sebagai angka menyeramkan, aku nggak. Bagiku angka paling mengerikan saat ini adalah tujuh dengan tambahan nol sejumlah tujuh butir di belakangnya. Nggak ada yang spesial dari angka ini, selain aku harus segera melunasinya.
"Kenapa?" tanya Aya. Dia satu-satunya teman kuliah yang akrab denganku. Poni rambutnya selalu lucu, berbentuk love terbalik (atau sebenarnya itu bentuk pantat?). Aku nggak paham dengan seleranya. Mungkin itu ungkapan perasaannya yang sering dijungkirbalikkan cintanya atau dia ada masalah pencernaan yang membuatnya sering sembelit. Entahlah.
"Gimana cara dapet duit banyak dalam waktu singkat?" Aku balas bertanya. Pandanganku lurus ke dosen pengantar akuntansi yang baru saja keluar kelas, tapi pikiranku penuh dengan uang yang nggak bisa kumiliki.
"Ngepet, piara tuyul, atau pasang togel," jawab Aya cepat. Dia lalu tertawa dengan keras, tanpa peduli kalau aku sudah menatapnya kesal.
Sebenarnya, aku nggak terlalu suka dengan Aya. Dia sering berlebihan menanggapi semua hal. Waktu mendapatkan tugas tambahan dari dosen Pengantar Akuntansi minggu lalu saja, dia sampai menangis histeris.
"Hidupku nggak tenang lagi. Aku menderita sampai nyaris mati." Dia terus mengeluhkan penderitaannya, padahal teman-teman yang lain biasa saja. Makudnya, kami memang kesal dengan semua tugas beruntun yang nyaris nggak ada ujungnya ini. Tapi, kami menerimanya tanpa banyak mengeluh. Orang yang terlalu sering mengeluh itu memang menyebalkan.
Kurebahkan kepalaku di meja. Tubuhku lemas tanpa gairah. Sudah tiga hari sejak surat pemberitahuan itu kuterima, tapi aku nggak dapat solusi apa pun. Hidupku berjalan monoton selama tiga hari ini.
Pundaku ditepuk dengan lembut. "Sori, gue bercanda." Kali ini suara Aya rendah, menunjukkan dia serius meminta maaf.
Aku menatapnya sekilas, lalu kembali memandang lurus. Nggak ada yang menarik di hadapanku, selain bagian belakang bangku yang mulai berkarat dan penuh coretan. Ada nama Bambang dan Ujo dihubungkan dengan tanda love yang mirip poninya Aya. Ternyata, dunia memang sudah gila, bukan aku yang mendadak gila.
"Lo bisa cobain part time. Kemarin gue lihat di Jadoel Cafe ada lowongan part time. Lo bisa kerja kalau lagi nggak kuliah." Aya memberikan informasi yang kubutuhkan. Kami memang nggak terlalu dekat, tapi dia satu-satunya orang yang mau duduk di sampingku sejak awal kami resmi menjadi mahasiswa.
Demi mendapat kejelasan informasi ini aku menegakkan badan. Mataku membulat dengan semangat memandang Aya. "Jadoel Cafe itu di mana?" tanyaku. Namanya terlalu asing di telingaku.
Aya mengernyit. "Lo serius nggak tahu?"
Aku menggeleng. Memangnya ada yang aneh karena nggak tahu Jadoel Cafe itu di mana?
Aya tertawa kencang lagi sampai membuat beberapa orang di sekitar kami menatapnya heran. Pipi tembamnya sampai bergoncang mirip jelly yang terlalu banyak air. Dia berusaha keras menghentikan tawanya, tapi susah. Aku cuma menatapnya dengan mulut mengerucut sampai panjang banget. Mobil limousin pasti kalah panjang dengan bibirku.
"Oke," serunya setelah yakin nggak akan tertawa lagi. Dia menekan dadanya. "Nanti gue anterin lo ke sana."
Selesai kelas terakhir di jam lima sore, Aya memenuhi janjinya. Ternyata Jadoel Cafe letaknya nggak jauh dari kampus. Pantas saja dia tertawa mengejekku yang selalu ketinggalan info tempat nongkrong paling gaul bagi anak-anak Merva.
Jadoel Cafe sesuai banget namanya. Dari depan nggak ada yang terlalu mencolok kecuali papan nama besar yang berkelap-kelip kalau malam. Deretan meja dan bangku berbahan seng menyebar di dalam ruangan tanpa pola khusus, yang penting ruangan itu mampu menampung banyak orang, tapi nggak menghalangi jalan. Di salah satu sudut sengaja dipasang foto-foto hitam putih, yang menampilkan senyuman dari banyak orang. Senyuman mereka tulus banget, seperti nggak pernah punya banyak utang gitu. Nggak kayak aku yang sekarang malas banget buat senyum.
Nggak ada yang spesial lagi dari tempat ini. Tapi, baru sore begini, pengunjungnya sudah nyaris penuh. Di beberapa meja tercecer banyak buku dan kertas dengan laptop menyala. Wifi kafe ini mungkin cukup kencang. Harga makanan dan minumannya ternyata juga murah. Pantas banyak orang yang cuma memesan segelas es teh tanpa makanan apa pun. Mereka pasti mahasiswa yang mencari internet murah buat menyelesaikan tugas yang harus segera dikumpulkan.
Aya mengajakku berbicara dengan salah satu pelayan. "Maaf, info lowongan part time di sini masih ada nggak, ya?" Aya bertanya dengan santai.
Pelayan itu menunjuk wanita cantik yang duduk di bangku paling ujung. "Langsung ke yang punya kafe aja."
Aku dan Aya kompak memandang ke bangku paling ujung. Dres biru dengan motif bunga-bunga yang wanita itu pakai, cantik banget membalut tubuh rampingnya. Rambut cokelatnya terlihat halus, mirip model iklan kain satin yang bergerak ringan saat ada angin. Bibir mungilnya dipoles warna merah bata. Untung cuma bibirnya yang diwarnai merah. Kalau semua wajahnya berwarna merah, dia jadi mirip rumah yang dalam proses renovasi.
"Permisi," sapaku saat aku berdiri di samping mejanya. Aya membiarkanku melakukan semuanya sendiri. Dia memilih memesan minuman dan duduk di salah satu bangku kosong sambil terus mengawasiku.
Aku bisa melihat warna mata wanita ini yang ditutupi contact lens biru laut saat dia menatapku. "Ya?" tanyanya bingung. Suaranya lembut dan hangat, mirip kembang tahu yang disiram air jahe.
"Saya Vio." Suaraku sedikit bergetar karena gugup. "Saya berminat bekerja part time di sini. Masih bisakah?"
Bibir merah bata itu terbuka sedikit. Matanya mengamatiku dari kepala sampai ujung kaki. Aku jadi gelisah dan salah tingkah dibuatnya. Dentuman drum dari speaker berdetak seirama dengan debaran jantungku. Mungkin jantungku bisa ikut bergabung dalam band rock. Sepertinya dia cocok dengan musik SUM 41 ini.
"Semester berapa?" tanyanya sambil mengetukkan pulpen ke meja.
"Saya mahasiswa baru, baru semester satu." Aku berusaha setenang mungkin.
"Kenapa mau kerja di sini?"
"Saya butuh uang. Papa baru meninggal. Sekarang saya yang jadi tumpuan Mama dan adik." Begini, kan, cara orang-orang mencari simpati, dengan menceritakan penderitaannya? Aku sering nonton acara TV yang selalu menjual kesedihan begini.
Wajah kaku wanita di depanku melunak. Sepertinya aku berhasil mendapatkan simpatinya. Tangannya menjulur, lalu mengusap lenganku. "Kamu boleh mulai kerja besok sore. Bawa sekalian jadwal kuliah kamu, ya. Biar saya bisa atur jadwal kerja kamu."
Mataku berbinar cerah, mengalahkan matahari yang sekarang bersembunyi di balik gumpalan putih di langit. Ternyata mencari kerja semudah ini. Memangnya apa yang jadi kendala buat para pengangguran di luar sana, sih? Kenapa mereka masih menganggur? Mendapatkan pekerjaan semudah ini, lho!
Motor milik Mama, yang sekarang kupakai pergi ke mana pun, baru saja masuk garasi waktu Tante Lily menelepon. "Ya, Tante," sapaku riang. Helm pink milikku terjatuh waktu aku meletakkannya di spion motor.
"Kenapa, Kak?" Tante Lily panik mendengar suara dentuman kerasnya.
Aku tertawa kecil sambil mengambil lagi helm yang menggelinding cukup jauh sampai ke luar rumah. Kakiku harus bergerak cepat mengejarnya kalau nggak mau helm itu berakhir di got. "Cuma helm jatuh, Tante. Aku baru sampai rumah."
"Kok sampai malam gini?" Suara Tante Lily agak meninggi.
Kuletakkan helm di rak sepatu dekat pintu masuk, bersebelahan dengan semprotan pembasmi kecoak. "Aku barusan cari kerja part time gitu, Tante. Ya, bukan kerjaan yang pantas dibanggakan, sih, cuma pelayan kafe." Aku menahan diri nggak menceritakan tentang masalah cicilan rumah yang belum mampu kubayar. Hidup Tante Lily sudah cukup sulit tanpa ditambah dengan rengekanku.
Embusan napas Tante Lily terdengar jelas. "Alhamdulillah. Ponakan Tante beneran udah gede sekarang, udah bisa cari duit sendiri. Mas Afandi pasti bangga banget sama Kakak." Suara Tante Lily berubah serak.
Ucapan Tante Lily nggak membuatku bangga. Bayangan wajah Papa yang tersenyum lebar masih menempel jelas di kepalaku. Aku benci ini. Merindukan orang yang nggak akan pernah bisa kutemui lagi itu menyebalkan, lebih menyebalkan dibandingkan gagal mendapatkan flash sale di market place.
Pembicaraanku dengan Tante Lily nggak berlangsung lama. Tante Lily cuma menanyakan kondisi keluargaku, terutama Mama. Dia juga terus mengucapkan kalimat penyemangat sampai aku memutuskan panggilan.
Besoknya, aku datang dengan membawa cetakan jadwal kuliahku beserta berkas lamaran yang sebelumnya belum kuberikan. Mbak Erika--pemilik Jadoel Cafe yang menerimaku kemarin--mengatur jadwal kerjaku. Berhubung kuliahku selalu selesai sebelum jam empat, aku nggak ada masalah dengan jadwal baru ini. Hanya saja, aku jadi harus pulang malam hampir setiap hari.
Urusan rumah sekarang sepenuhnya dipegang Mak Oci. Aku beruntung banget punya Mak Oci. Tanpa bantuannya aku nggak tahu akan sekacau apa hidupku. Walau sedikit cemas dengan kondisi Mama, aku terpaksa harus memilih bekerja.
Semua akan baik-baik aja, kan?
Hari pertama kerja perasaanku aneh. Debaran jantungku membuatku harus berulang kali mengembuskan napas panjang. Aku harus berdiri di dekat meja kasir untuk menyapa setiap pelanggan yang datang dengan senyum manis. Nggak peduli sebenarnya aku sedang menahan mules yang hampir menyembur, senyum tetap harus menghiasi wajahku.
Tugasku mencatat setiap pesanan pelanggan, memberikan catatan itu ke dapur, mengantarkan pesanan ke pelanggan yang tepat, lalu membersihkan sisa-sisa pertarungan yang berceceran di meja. Seharusnya tugasku cukup mudah.
Pesanan pertama yang kulayani nggak ada masalah. Aku melaksanakan prosedur kerja sesuai dengan arahan Mbak Erika tadi. Pelanggan senang, Mbak Erika pun riang. Walau luar biasa capek, aku cukup bangga dengan usahaku.
Masalah mulai timbul waktu malam mulai datang. Pengunjung memenuhi ruangan ini tanpa ada tempat kosong lagi. Aku yang belum hapal nomor meja beberapa kali salah mengantar pesanan. Nomor meja yang kutulis dengan yang ditempel di meja jauh berbeda dengan ekspektasiku.
Suara musik yang kencang dan ocehan banyak orang juga berhasil membuat konsentrasiku kacau. Dua kali aku salah menulis pesanan. Iya, aku memang ceroboh banget. Itu juga belum termasuk sekali aku memecahkan gelas berisi kopi panas, dua piring kotor yang berminyak, dan vas bunga yang diletakkan terlalu berhimpitan dengan pintu dapur.
Ternyata cari duit nggak semudah menaikkan hutang negara. Baru hari pertama kerja dan belum dapat gaji, tapi aku sudah harus membayar ganti rugi.
Terus, gimana caranya aku mengumpulkan uang untuk melunasi cicilan rumah?
Daftar Chapter
Chapter 1: Dream Come True
1,723 kata
Chapter 2: Sad Story
933 kata
Chapter 3: Deep Sleep
1,079 kata
Chapter 4: Tears
910 kata
Chapter 5: Funeral
1,160 kata
Chapter 6: New Normal
1,661 kata
Chapter 7: New Job
1,829 kata
Chapter 8: Fired
1,677 kata
Chapter 9: New Bussiness
1,771 kata
Chapter 10: Old Friend
1,679 kata
Chapter 11: Sugar Baby Wanna be
2,078 kata
Chapter 12: Mission Failed
1,611 kata
Chapter 13: Confiscated
1,576 kata
Chapter 14: Separation
1,694 kata
Chapter 15: Independent Day
1,622 kata
Chapter 16: The End of The Struggle
1,451 kata
Chapter 17: Former Sugar Daddy Candidate
1,411 kata
Chapter 18: New Room
1,203 kata
Chapter 19: Grumpy Oldman
1,341 kata
Chapter 20: Goodnight
1,419 kata
Komentar Chapter (0)
Login untuk memberikan komentar
LoginBelum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan komentar!